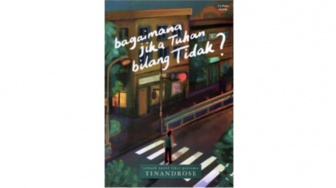Kita hidup di masa ketika berbagai persoalan birokrasi tampak berulang bagai putaran kaset yang tidak pernah berhenti. Laporan hanya tampak di atas kertas tetapi tak menyelesaikan persoalan di lapangan, kebijakan yang tampak komprehensif namun mandul dalam pelaksanaannya, serta program pemerintah yang lebih gemar dipajang di media ketimbang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketika publik mempertanyakan efektivitas layanan, sering kita hanya memperoleh jawaban yang tak seharusya. Bukan menjawab alasan dan perhitungan logis dibalik layanan, justru melemparkan alasan tersebut sebagai bentuk arahan dari atasan.
Budaya ‘asal bapak senang’ dan konflik aversi berperan dalam membentuk dinamika buruk itu. Tidak semata menuding pihak tertentu, tetapi mencoba menyingkap berbagai sebab yang selama ini sering tersamarkan di balik rutinitas kerja birokrasi.
Apa sebenarnya yang terjadi ketika pegawai lebih sibuk ‘menyenangkan atasan’ ketimbang menyelesaikan masalah lapangan? Mengapa budaya semacam ini terus bertahan, bahkan menjadi sesuatu yang nyaris dianggap wajar?
Dari Keinginan Menyenangkan Atasan ke Budaya ‘Asal Bapak Senang’
Budaya ‘asal bapak senang’ tumbuh subur di lingkungan yang sangat menghargai hierarki. Dalam struktur yang mengutamakan senioritas dan posisi, suara orang yang lebih tinggi sering menjadi penentu segala arah kebijakan.
Ketika jenjang karier dan penilaian kinerja sangat dipengaruhi oleh satu atau dua orang atasan, bukan hal aneh bila bawahan berusaha sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan ekspektasi mereka. Meskipun itu berarti mengabaikan suara hati nurani atau data obyektif.
Akibatnya, bukan kualitas kinerja yang menjadi fokus utama, tetapi kesan bahwa segala sesuatu berjalan baik. Laporan yang terlalu rapi, presentasi yang memukau, atau angka capaian yang terlihat menjanjikan lebih sering menjadi tolok ukur penilaian ketimbang dampak nyata dari layanan publik yang diberikan.
Fenomena ini tak hanya soal memberi pujian kepada pimpinan. Lebih jauh, ia mencerminkan cara berpikir yang menempatkan status di atas substansi, serta kepatuhan sekadar formal di atas keberanian untuk mengadvokasi perubahan yang sesungguhnya diperlukan.
Konflik Aversi: Takut Berbeda Pendapat Bisa Berujung Diam
Di sinilah konflik aversi memainkan peranan yang sangat krusial. Konflik aversi adalah kecenderungan untuk menghindari ketegangan atau perbedaan pendapat demi menjaga suasana tetap aman.
Dalam lingkungan birokrasi, mengungkap kritik atau menunjukkan kelemahan sebuah rencana sering kali dipandang bukan sebagai kontribusi positif, tetapi sebagai ancaman atau bentuk tidak loyal kepada atasan.
Ketika suara berbeda dipandang berpotensi merusak hubungan kerja atau posisi karier, banyak pegawai memilih untuk bungkam.
Mereka lebih suka menyetujui apa pun yang diutarakan pimpinan, berharap tidak menjadi sasaran perhatian negatif, meskipun dalam hati mereka tahu keputusan tersebut mungkin kurang tepat. Sikap tidak enak untuk mengutarakan pendapat ini secara tidak langsung memperkuat budaya ‘asal bapak senang’.
Lingkaran setan pun terbentuk. Bawahan menghindari konflik demi rasa aman, kekeliruan tetap berlanjut, dan pimpinan melihat semua berjalan lancar karena tidak ada suara berbeda yang muncul. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, tetapi pola perilaku yang mengokohkan budaya ketidakkritisan.
Dampak Buruk pada Reformasi dan Kinerja Birokrasi
Dampak gabungan budaya ‘asal bapak senang’ dan konflik aversi adalah birokrasi yang tampak gemilang tetapi nyatanya rapuh dan mudah runtuh.
Program dipuji tanpa kritik, angka capaian dipuji tanpa mencari tahu kehidupan riil masyarakat, dan rutinitas dipuji tanpa refleksi terhadap efektivitasnya. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menciptakan kegamangan. Ketika kritik hilang, pembelajaran juga hilang.
Tak hanya itu, sistem ini mengerdilkan inovasi karena pegawai yang punya ide segar lebih memilih diam demi keamanan karier. Mereka yang berani bersuara pun berisiko tersisih atau dicap sebagai troublemaker, sehingga lingkungan kerja jadi enggan membuka ruang dialog yang sehat. Reformasi birokrasi yang sering digaungkan sebagai tujuan utama justru terkubur di balik rutinitas yang nyaris dogmatis.
Komponen Psikologis dan Struktural yang Perlu Dipahami
Fenomena ini bukan hanya persoalan budaya organisasi, tetapi juga soal psikologi sosial. Dalam konteks hubungan kuasa, manusia cenderung mencari rasa aman dan penerimaan sosial. Ketika struktur organisasi memberi penghargaan pada kepatuhan, bukan pada keberanian bertanya atau berdebat, perilaku yang adaptif adalah menyamakan diri dengan arus dominan.
Struktur yang sangat hierarkis juga memperkecil ruang untuk dialog kritis. Bawahan belajar bertahan lebih baik dengan setuju daripada berbeda, sementara pimpinan sering tidak terbiasa atau bahkan enggan menerima masukan yang tidak sesuai dengan pola pikir mereka sendiri.
Mengurai lingkaran setan budaya ‘asal bapak sennag’ dan konflik aversi bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi tugas bersama untuk menciptakan birokrasi yang lebih sehat, efektif, dan bertanggung jawab.
Reformasi birokrasi sejati hanya bisa terjadi ketika ruang dialog terbuka, kritik dipandang sebagai bahan pembelajaran, dan penilaian kinerja didasarkan pada hasil nyata, bukan sekadar citra yang tampak.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS