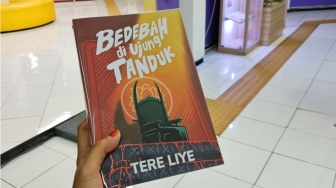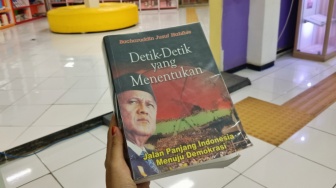Di negeri ini, ada satu ironi yang semakin terasa. Mendapat gaji UMR (Upah minimum Regional) dianggap sebagai pencapaian. Padahal, UMR atau istilah resminya kini UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) secara harfiah berarti upah minimum.
Kata kuncinya bukan “prestasi”, bukan “keistimewaan”, melainkan batas paling bawah agar pekerja bisa bertahan hidup secara layak. Minimum. Titik nol. Bukan bonus. Namun entah sejak kapan, standar paling dasar itu dipelintir maknanya.
Dengan jam kerja full time, dan pulang pergi ke tempat kerja setiap hari. Tapi gaji bahkan tak mencapai standar minimum. Ada apa dengan sistem kerja kita?
Hak yang Dibilang Manja: Salah Kaprah tentang Gaji UMR
Kita sering mendengar komentar seperti, “Gen Z cari kerja maunya langsung gaji UMR.”
Kalimat ini seolah menempatkan UMR sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal yang diminta hanyalah hak paling minimal. Ironisnya, ketika ada lowongan kerja mencantumkan “Benefit: gaji UMR”, banyak yang hanya bisa tertawa pahit. Sejak kapan kewajiban hukum berubah menjadi benefit?
Masalah ini bukan sekadar soal istilah, melainkan cerminan bobroknya cara kita memandang kerja dan upah. UMR ditetapkan pemerintah berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak. Mulai dari makan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, hingga kebutuhan sosial dasar.
Artinya, UMR bukan angka untuk hidup nyaman, melainkan angka agar seseorang tidak jatuh miskin meski bekerja penuh waktu. Ketika standar ini saja dianggap “kemewahan”, maka ada yang salah secara struktural.
Dibayar Minimum, Disuruh Bersyukur: Ada yang Salah dengan Cara Kita Memaknai Kerja
Lebih parah lagi, praktik di lapangan sering menjadikan UMR sebagai batas maksimal tak tertulis, bukan batas minimal. Banyak perusahaan merasa sudah “baik hati” karena membayar sesuai UMR. Meskipun beban kerja tinggi, jam kerja panjang, dan tuntutan keahlian tidak lagi “entry level”.
Akibatnya, pekerja dipaksa bersyukur atas sesuatu yang seharusnya otomatis mereka terima. Budaya ini mematikan daya tawar buruh sejak awal.
Fenomena lain yang tak kalah mengganggu adalah bahasa iklan lowongan kerja. Frasa seperti “gaji kompetitif” sering kali justru menjadi alarm bahaya. Alih-alih kompetitif dengan pasar dan biaya hidup, yang dimaksud kerap kompetitif dalam menekan biaya tenaga kerja.
Transparansi upah dihindari, sementara ekspektasi terhadap kandidat dibuat setinggi mungkin. Ketika gaji akhirnya disebut, nilainya sering kali berada di bawah UMR atau tepat di angka minimum, tanpa tunjangan berarti.
Normalisasi Upah Rendah dan Generasi yang Disalahkan karena Menuntut Hak Paling Dasar
Di titik ini, Gen Z sering dijadikan kambing hitam. Mereka dicap tidak tahu diri, terlalu menuntut, atau tidak mau “berproses”. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kesadaran yang lebih tinggi soal hak kerja.
Generasi ini tumbuh di tengah informasi terbuka, melihat perbandingan upah lintas negara, dan menyaksikan langsung bagaimana kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ketika mereka menolak upah di bawah standar, itu bukan manja. Itu rasional.
Masalah inti sesungguhnya bukan pada Gen Z, melainkan pada sistem yang menormalisasi upah rendah dan membingkainya sebagai kesempatan.
UMR dan Ilusi Kesejahteraan: Ketika Upah Minimum Dipuja, Ada yang Salah dengan Sistem Kerja Kita
Selama UMR terus diperlakukan sebagai hadiah, bukan kewajiban, maka eksploitasi akan selalu menemukan pembenaran moral. Pekerja disuruh bersabar, loyal, dan berterima kasih, sementara struktur upah tidak pernah benar-benar dibenahi.
Sudah saatnya kita mengembalikan makna UMR ke tempat semestinya. Lantai dasar, bukan atap. Gaji minimum bukan benefit, melainkan hak. Dan jika sebuah sistem membuat orang merasa harus berterima kasih karena dibayar paling minimum. Maka yang bermasalah bukan mental pekerjanya, melainkan sistemnya.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS