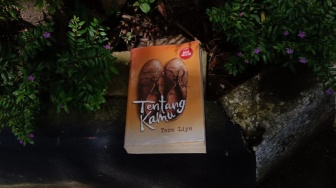Perkembangan kecerdasan buatan (AI) sering dirayakan sebagai lompatan besar peradaban manusia. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul ancaman baru yang perlahan menggerogoti fondasi demokrasi, yakni deepfake.
Teknologi ini mampu merekayasa wajah, suara, bahkan pernyataan seseorang dengan tingkat kemiripan yang nyaris sempurna. Masalahnya, regulasi dan literasi publik belum siap menghadapi dampaknya.
Di era digital, kebenaran tak lagi berdiri di atas fakta, melainkan di atas apa yang paling cepat viral. Sebuah video palsu yang menampilkan pejabat publik mengucapkan sesuatu yang kontroversial dapat menyebar luas dalam hitungan menit, jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Deepfake Ancaman Serius Bagi Negara
Dalam konteks ini, deepfake bukan sekadar masalah teknologi, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik.
Demokrasi hidup dari kepercayaan. Kepercayaan pada informasi, pada proses, dan pada aktor publik. Ketika masyarakat tak lagi yakin apakah yang mereka lihat dan dengar itu nyata, ruang publik berubah menjadi arena kecurigaan.
Semua bisa dipalsukan, semua bisa dimanipulasi. Akibatnya, klarifikasi dianggap pembelaan, bantahan dianggap pengalihan, dan fakta kehilangan otoritasnya.
Bahaya deepfake tidak berhenti pada isu politik. Reputasi individu, terutama tokoh publik, jurnalis, hingga aktivis dapat hancur hanya karena satu konten palsu.
Dalam banyak kasus, kerusakan sudah terjadi bahkan sebelum kebenaran terungkap. Di dunia digital, jejak fitnah sering lebih abadi daripada klarifikasinya.
Dilansir dari puskinas Polri, Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipitsiber) menangkap pelaku penipuan menggunakan teknologi AI Deepfake yang mencatut nama pejabat negara. Pengungkapan bermula dari Tim Siber yang menemukan aktivitas mencurigakan.
Hal ini bisa disimpulkan bahwa negara kita telah mengalami kasus deepfake yang banyak hingga dititik mencatut nama berbagai kalangan.
Hukum yang Datang Terlambat
Ironisnya, hukum sering kali datang terlambat. Regulasi terkait AI dan manipulasi digital masih bersifat umum, sementara teknologi berkembang sangat spesifik dan cepat.
Penegakan hukum juga kerap kesulitan membuktikan niat, pelaku, dan dampak, apalagi jika konten dibuat secara anonim atau lintas negara. Tanpa payung hukum yang jelas, korban deepfake berada di posisi lemah.
Negara tidak bisa terus bersikap reaktif. Menunggu kasus viral lalu mengeluarkan pernyataan keprihatinan bukanlah solusi. Dibutuhkan kerangka regulasi yang tegas mulai dari definisi hukum, sanksi yang proporsional, hingga mekanisme pelaporan dan pemulihan korban.
Lebih dari itu, negara perlu berinvestasi pada teknologi pendeteksi konten palsu, bukan hanya membiarkan publik “lebih berhati-hati”.
Ini Tanggung Jawab Bersama
Namun, yang harus dipastikan adalah tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada negara. Platform digital memegang peran krusial.
Algoritma yang mengutamakan engagement sering kali justru mempercepat penyebaran konten bermasalah. Jika platform menikmati keuntungan dari lalu lintas viral, maka mereka juga harus bertanggung jawab atas dampak sosialnya.
Di sisi lain, masyarakat pun dituntut lebih kritis. Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan menunda reaksi, memverifikasi informasi, dan menyadari bahwa tidak semua yang terlihat nyata adalah kebenaran.
Dalam ekosistem digital yang rapuh, sikap skeptis yang sehat justru menjadi bentuk tanggung jawab warga negara.
Deepfake adalah cermin dari zaman kita yakni, perwujudan teknologi melesat, namun etika tertinggal.
Jika dibiarkan tanpa kendali, deepfake akan membawa demokrasi kita berisiko berubah menjadi ilusi visual, di mana yang paling meyakinkanlah yang dipercaya, bukan yang paling benar. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa bahayanya deepfake melainkan seberapa siap kita mencegahnya sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.