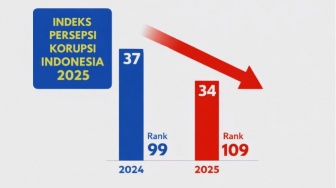Ruang publik sering dipuja sebagai simbol kemajuan kota. Namun, bagi jutaan penyandang disabilitas, ruang itu justru menjadi pengingat bahwa mereka belum sepenuhnya dianggap.
Tangga tanpa jalur landai, trotoar berlubang, transportasi umum yang sulit diakses, hingga gedung layanan publik yang tidak ramah—semua itu bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan cerminan cara kita memandang kemanusiaan.
Ketika fasilitas umum gagal mengakomodasi semua orang, kota sesungguhnya sedang memilih siapa yang boleh hadir dan siapa yang harus menyingkir.
Aksesibilitas Bukan Bonus, Melainkan Hak Dasar
Masih banyak yang memandang fasilitas ramah disabilitas sebagai tambahan opsional, seolah hanya pelengkap estetika pembangunan. Padahal, aksesibilitas adalah hak dasar. Penyandang disabilitas tidak meminta perlakuan istimewa; mereka hanya ingin dapat bergerak, bekerja, belajar, dan berinteraksi tanpa hambatan yang sebetulnya bisa dihindari sejak tahap perencanaan.
Ketika trotoar dibangun tanpa mempertimbangkan pengguna kursi roda atau tanpa guiding block bagi tunanetra, yang terjadi bukan sekadar kelalaian desain, melainkan pengabaian kebutuhan warga. Hak atas ruang publik seharusnya berlaku setara. Kota yang adil adalah kota yang sejak awal mengakui keberagaman kondisi fisik dan sensorik warganya, bukan memaksakan satu standar tubuh yang dianggap “normal”.
Kota yang Melelahkan bagi Mereka
Bagi sebagian orang, pergi ke kantor, halte, atau pusat layanan hanyalah rutinitas. Namun, bagi penyandang disabilitas, aktivitas sederhana dapat berubah menjadi perjuangan yang menguras energi mental dan fisik. Tangga yang terlalu curam, pintu yang sempit, atau informasi yang hanya tersedia secara visual membuat mereka harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ramah.
Kondisi ini menciptakan kelelahan yang jarang dibicarakan. Bukan lelah karena disabilitas itu sendiri, melainkan lelah menghadapi sistem yang tidak berpihak. Ketika ruang publik tidak inklusif, penyandang disabilitas dipaksa mengeluarkan usaha berlipat hanya untuk mencapai hal yang bagi orang lain terasa biasa. Ini bukan soal ketahanan pribadi, melainkan kegagalan kolektif dalam membangun lingkungan yang manusiawi.
Desain Inklusif yang Menguntungkan Semua Orang
Ada anggapan keliru bahwa fasilitas ramah disabilitas hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu. Kenyataannya, desain inklusif justru menguntungkan hampir semua orang. Jalur landai membantu orang tua dengan stroller, lansia, hingga pekerja yang membawa barang berat. Informasi visual yang jelas serta penunjuk arah berbasis suara memudahkan pendatang baru di sebuah kota.
Dengan kata lain, ketika kota dirancang agar mudah diakses oleh yang paling rentan, kota itu otomatis menjadi lebih nyaman bagi semua. Prinsip ini dikenal luas dalam perencanaan modern, tetapi penerapannya masih setengah hati. Padahal, investasi pada aksesibilitas bukanlah pemborosan anggaran, melainkan langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan.
Di Antara Regulasi dan Realitas Lapangan
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan yang melindungi hak penyandang disabilitas. Undang-undang, peraturan daerah, hingga standar bangunan telah cukup jelas mengatur soal aksesibilitas. Masalahnya, implementasi sering kali berhenti di atas kertas. Banyak fasilitas dibangun sekadar untuk memenuhi syarat administrasi, bukan agar benar-benar dapat digunakan.
Rampa yang terlalu curam, lift yang sering rusak, atau toilet khusus yang berubah fungsi menjadi gudang menunjukkan adanya jurang antara niat dan realitas. Pengawasan yang lemah serta minimnya pelibatan komunitas disabilitas membuat kesalahan desain terus berulang. Padahal, merekalah sumber pengetahuan paling nyata tentang apa yang benar-benar dibutuhkan.
Mengubah Cara Pandang tentang Ruang Publik
Membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas pada dasarnya adalah soal cara pandang. Selama disabilitas masih dianggap isu pinggiran, perubahan akan berjalan lambat. Namun, ketika kita mulai melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, pendekatan pembangunan pun akan bergeser.
Kota bukan hanya milik mereka yang kuat dan cepat, tetapi juga milik mereka yang bergerak pelan, yang membutuhkan alat bantu, dan yang memproses dunia dengan cara berbeda. Ruang publik seharusnya menjadi tempat semua orang merasa diakui, bukan diuji kemampuannya untuk bertahan. Inklusivitas bukan slogan, melainkan pilihan sadar untuk membangun masa depan yang lebih adil.
Pada akhirnya, fasilitas umum yang ramah disabilitas bukan hanya tentang beton, jalur, atau rambu, melainkan tentang sikap kita sebagai masyarakat.
Ketika kita bisa berjalan di kota tanpa memikirkan apakah semua orang dapat melakukan hal yang sama, di situlah refleksi perlu dimulai. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal hanya karena tubuh atau indranya bekerja dengan cara yang berbeda.