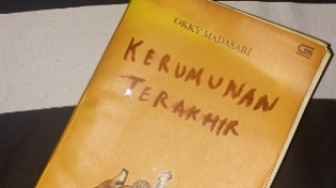Apa arti “Feminisme” hari ini? Seberapa perlunya kita menjadi feminis? Dua pertanyaan ini kiranya menjadi landasan dari apa yang dibahas oleh Chimamanda Ngozi Adichie dalam bukunya, A Feminist Manifesto. Dalam buku yang cenderung tipis ini, penulis mengupas soal pengalamannya terkait feminis dengan padat dan ringkas.
Di bagian awal, ia mengajak pembaca untuk duduk sejenak untuk mendengarkan kisahnya terkait feminisme. Dari paparannya, secara singkat dan sederhana, kita bisa mengartikan feminis, atau seorang feminis sebagai orang yang sadar dan percaya akan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi bagi kedua jenis gender.
Apa saja wujud ketidakseteraan tersebut? Beberapa mungkin kita sudah sering mendengarnya, bahwa laki-laki memiliki kesempatan untuk berkarier lebih luang dari perempuan, bahwa tugas domestik adalah sepenuhnya milik perempuan, bahwa perempuan yang melajang bertahun-tahun lebih sering digunjingkan ketimbang laki-laki, bahwa kedudukan tinggi seorang perempuan sungguh tak diharapkan sebab hal tersebut dapat mengintimidasi para lelaki, dan banyak lagi bentuk-bentuk lain yang mengisyaratkan perempuan sebagai manusia nomor dua. Tak perlu jauh-jauh untuk melihatnya, sebab kita sangat mungkin mendapati bentuk-bentuk ketidakseteraan ini di lingkungan terdekat kita, baik itu rumah, kompleks perumahan, tempat kerja, bahkan lembaga pendidikan. Ya, bisa dibilang, bentuk-bentuk tersebut telah membudaya.
Perihal budaya inilah yang digugat oleh penulis. Kita mungkin pernah mendengar, bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terjadi sejak dahulu kala, ketika manusia hanya mengenal berburu dan bercocok-tanam untuk bertahan hidup. Saat itu, pembagian ini terjadi sebab untuk memaklukan seekor Mammut atau mamalia besar lainnya dibutuhkan tenaga dan usaha keras. Maka sudah jelas, perempuan yang diciptakan dengan tubuh biologis tak sekuat laki-laki, otomatis tersingkirkan dalam proses perburuan tersebut, dan ditempatkan di ranah yang ramah bagi mereka, yakni domestik. Sialnya, situasi ini terus terjadi sampai beradab-abad kemudian. Kita kadung menempatkan laki-laki lebih tinggi di atas perempuan berdasarkan sejarah ini.
Untuk menyikapi hal itu, penulis menekankan bahwa, “Budaya tidaklah membentuk manusia, tetapi manusialah yang membentuk budaya.” Maka dalam tulisan selanjutnya, penulis memberi penjelasan beserta contoh, misalnya, persepsi bahwa ranah domestik melulu kepunyaan perempuan, sudah semestinya diubah. Kita perlu membiasakan diri bahwa tugas-tugas semacam itu dilakukan bukan karena ia bergender X, dan apabila Y berkenan melakukannya, maka itu patut dipuji. Alih-alih demikian, kita bisa mengambil alternatifnya dengan menanamkan pikiran bahwa baik X maupun Y bisa melakukan hal tersebut karena mereka setara, mampu, dan memang sudah tanggung jawab bersama.
Soal gender tidak berhenti sampai di situ saja. Di ranah lain, dalam hal perkembangan anak, misalnya, penulis menyontohkan kalau kita masih kerap menjumpai aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana anak perempuan bersikap dan berpenampilan. Jagalah sikapmu, jadi gadis yang baik, dan berpakaian sopan; merupakan ujaran yang sering didapat perempuan sejak dini. Alih-alih tampil dan menjadi diri mereka sendiri, mereka justru dibentuk dengan aturan yang apabila terjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka, pihak pertama yang patut dipertanyakan adalah mereka.
Di dunia nyata, bentuk ketidakadilan ini sangat mudah terlihat: Datanglah ke kantor polisi yang tengah menangani kasus pemerkosaan, dan dengarkan bagaimana si polisi justru menanyakan hal-hal semacam “Pakaian apa yang kamu kenakan saat itu” dan Kamu pulang jam berapa”, yang jelas menunjukkan bahwa si korban adalah biang perkara.
Melihat contoh-contoh tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa yang bermasalah dengan gender adalah ia menentukan bagaimana kita seharusnya, bukan mengakui siapa kita sebenarnya. Hal ini semakin ia perlihatkan dalam bagian kedua buku ini, yakni surat yang berisi anjuran untuk mendidik anak secara feminis untuk sahabatnya. Di bagian ini, ia member nasihat kepada sahabat dengan anjuran-anjuran yang memiliki semangat feminis seperti, jangan batasi minat anak tak peduli ia laki-laki atau perempuan, jangan tentukan bagaimana si anak harus berpakaian dan memilih mainan, sampai jangan ragu untuk membicarakan perihal seks dan organ reproduksi bersama si anak.
Dengan bahasa yang terasa dekat, penulis kian menekan betapa pentingnya menjadi seorang feminis. Ia tak memakai teori asing nan muluk yang kadang membuat gagasan feminism terkesan berat. Sebaliknya, ia menarasikan itu semua dengan jelas dan ringkas. Apalagi, baginya, untuk menjadi seorang feminis kita tak perlu mengerti teori yang macam-macam. Baginya, orang sudah bisa dikatakan feminis bila ia, baik laki-laki maupun perempuan menyadari adanya masalah ketidaksetaraan di tengah masyarakat, dan tergerak untuk memperbaikinya. Sesederhana itu.