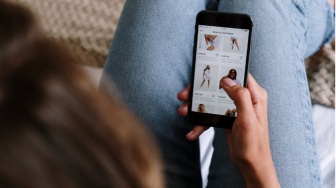Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk membangun masa depan bangsa. Tetapi, jika melihat kondisi sekarang, rasanya pendidikan kita seperti kehilangan jati dirinya. Alih-alih mencerdaskan manusia Indonesia secara utuh, sekolah justru sibuk mengejar angka, laporan, dan aturan yang makin hari makin menumpuk.
Nilai kemanusiaan, yang seharusnya menjadi inti pendidikan, pelan-pelan menghilang di balik tumpukan administrasi dan standar teknis yang kaku.
Kelas yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh, berdialog, dan menemukan makna justru berubah menjadi mesin produksi nilai ujian. Anak-anak diperlakukan seperti angka, guru diperlakukan seperti operator, dan sekolah seperti pabrik yang harus memenuhi target. Padahal, pendidikan itu jauh lebih besar daripada angka di rapor atau peringkat sekolah. Pendidikan adalah soal manusia, perasaan mereka, relasi mereka, dan bagaimana mereka memaknai dunia.
Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau IPA. Sekolah adalah ruang sosial tempat karakter dibentuk, tempat nilai-nilai tumbuh, dan tempat anak-anak belajar memahami orang lain. Tetapi, fungsi luhur itu makin tergerus oleh logika kompetisi dan birokrasi. Peringkat dilebih-lebihkan, prestasi akademik diagung-agungkan, sementara kemampuan bersikap empati dan berpikir kritis malah dianggap pelengkap.
Padahal, guru adalah sosok yang seharusnya menuntun anak melihat dunia dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, banyak guru justru terjebak dalam rutinitas laporan, pelatihan yang serba formal, dan target administratif yang tak ada habisnya. Waktu untuk memahami murid sebagai manusia pun ikut menghilang. Hubungan guru-murid menjadi kering, seperti hubungan pegawai dengan klien. Padahal, dari interaksi yang personal dan hangat, anak belajar tentang empati, tanggung jawab, dan keberanian menjadi dirinya sendiri.
Durkheim pernah mengatakan bahwa pendidikan seharusnya membangun rasa kebersamaan. Tetapi kenyataannya, sekolah kita malah menanamkan kompetisi berlebihan sejak anak masih kecil. Mereka diajarkan untuk mengalahkan, bukan memahami; untuk menonjol, bukan berkolaborasi; untuk mengejar nilai, bukan mengejar makna. Tidak heran jika banyak anak tumbuh menjadi pintar secara akademis, tetapi rapuh secara emosional, kaku dalam bersosial, dan mudah kehilangan arah ketika berhadapan dengan masalah nyata.
Sementara itu, Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh memperlakukan murid sebagai wadah kosong. Namun, pola itu masih terus berulang. Anak hanya diminta mendengar, bukan bertanya; menghafal, bukan menganalisis; patuh, bukan berdialog. Di sinilah pendidikan kehilangan fungsi kritisnya. Kita lupa bahwa membangun kesadaran jauh lebih penting daripada mengumpulkan hafalan.
Jika kita melihat lebih dalam, sekolah juga punya peran besar dalam membentuk struktur sosial. Bourdieu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpendidikan lebih tinggi punya peluang lebih besar untuk sukses, sementara anak yang tumbuh dalam keterbatasan sering kali tertinggal bukan karena mereka kurang mampu, tetapi karena sistem tidak berpihak pada mereka. Jika ini dibiarkan, pendidikan justru menjadi alat yang memperlebar ketimpangan, bukan menjembatani perbedaan.
Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang bagi semua anak untuk merasa diterima, tumbuh, dan menemukan versi terbaik dirinya. Pendidikan seharusnya merayakan keberagaman, bukan menakutinya. Ilmu seharusnya dikaitkan dengan persoalan sosial di sekitar: lingkungan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Anak bukan hanya perlu tahu teori demokrasi, mereka perlu merasakan bagaimana rasanya didengarkan di kelas.
Sudah saatnya kita meninjau ulang ukuran keberhasilan pendidikan. Sekolah yang “baik” bukan hanya yang banyak meluluskan mahasiswanya ke perguruan tinggi, tetapi yang membentuk manusia yang peduli, berempati, dan mampu hidup bersama dalam perbedaan. Pendidikan tidak boleh berhenti pada angka, ia harus menyentuh hati.
Pada akhirnya, pendidikan bukanlah soal siapa yang paling pintar, paling cepat, atau paling unggul di atas kertas. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita menumbuhkan manusia yang mampu merasakan, memahami, dan peduli pada dunia di sekitarnya. Jika sekolah kehilangan hati, maka semua pengetahuan yang diajarkan akan kehilangan makna. Anak bisa saja menjadi juara kelas, tetapi tetap tersesat ketika berhadapan dengan realitas kehidupan.
Karena itu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: Untuk apa sekolah didirikan? Untuk apa anak belajar? Untuk apa guru mengajar? Jawabannya selalu kembali pada satu hal: agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari.
Pendidikan yang memanusiakan manusia bukanlah utopia. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: guru yang mau mendengarkan, siswa yang berani bertanya, dan sekolah yang memberi ruang bagi dialog, empati, dan keberagaman. Jika perubahan kecil itu terus dijaga, maka perlahan pendidikan akan menemukan kembali hatinya.
Ketika pendidikan kembali bernapas sebagai ruang yang penuh kasih, pemahaman, dan kesadaran sosial, kita bukan hanya membentuk generasi cerdas, tetapi generasi yang mampu membawa bangsa ini melangkah dengan jiwa yang utuh dan berakar pada kemanusiaan.