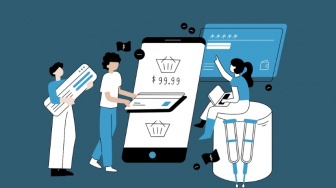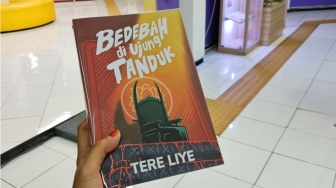Saya beberapa kali meliput bencana alam berupa banjir dan tanah longsor saat masih aktif sebagai jurnalis satu dekade lalu. Ada satu pemandangan khas yang selalu muncul ketika bencana telah berlalu, tanpa memandang lokasi: masyarakat yang berjuang menata kembali hidup mereka.
Ketika banjir surut dan tanah longsor berhenti bergerak, yang tertinggal sering kali bukan hanya lumpur, batu, atau gelondongan kayu. Ada rumah yang meski tidak hancur total, tetap harus digali dan dibersihkan.
Ada orang-orang yang tubuhnya masih gemetar setiap kali hujan turun, meskipun raga mereka telah hangat terbungkus selimut darurat di pengungsian.
Bencana, termasuk yang terjadi di Sumatera baru-baru ini, selalu meninggalkan jejak yang tidak selalu kasatmata. Ada kecemasan, kebingungan, dan ingatan tentang betapa mengerikannya alam saat peristiwa itu berlangsung.
Namun, matahari tetap terbit. Bersamaan dengan itu, hidup mau tidak mau harus terus berjalan. Para penyintas harus kembali melangkah.
Di desa-desa terdampak, warga mulai membersihkan halaman dengan peralatan seadanya. Lumpur disingkirkan perlahan. Kayu-kayu yang terbawa arus disusun rapi di tepi jalan, sebagian dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah. Tikar dan kasur yang tidak hanyut dijemur di bawah matahari, dengan harapan panas siang dapat mengusir sisa lembap yang melekat.
Anak-anak kembali bermain dan berlarian, meskipun kaki kecil mereka kerap terperosok ke tanah yang belum sepenuhnya kering. Tawa mereka mungkin belum sebebas dahulu, tetapi sering kali cukup untuk mengingatkan orang dewasa bahwa hidup tidak boleh berhenti terlalu lama.
Para ibu memasak apa pun yang tersedia. Tidak selalu lengkap, sekadar cukup untuk menguatkan tubuh. Para lelaki memperbaiki pagar, menambal atap, atau duduk sejenak sambil membicarakan rencana hari esok.
Tidak ada aksi heroik yang diumumkan. Yang ada hanyalah ketekunan kecil yang dilakukan berulang-ulang, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu hari ke hari berikutnya.
Di tengah upaya warga tersebut, proses pemulihan dan penataan ulang kehidupan sering berjalan tanpa banyak sorotan. Suara mesin perlahan terdengar, menyatu dengan denyut kampung yang kembali hidup. Alat-alat berat datang dari pemerintah bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai penopang agar warga bisa kembali bergerak.
Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, misalnya, memobilisasi puluhan unit alat berat dan truk pengangkut untuk menangani material banjir dan longsor di sejumlah titik prioritas. Pembersihan dilakukan bertahap demi membuka kembali ruas jalan yang sempat menjadi batas antara harapan dan keterisolasian.
Bagi warga Sumatera, jalan bukan sekadar lintasan kendaraan. Jalan adalah nadi ekonomi, jalur anak-anak menuju sekolah, akses petani membawa hasil kebun, serta penghubung bagi orang sakit untuk mencapai layanan kesehatan. Ketika jalan terputus, kehidupan seolah menyempit. Ketika jalan kembali terbuka, ruang hidup pun terasa lebih lapang.
Kabar dibukanya kembali Jembatan Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya disambut lega oleh banyak orang. Bagi warga, jembatan itu bukan sekadar konstruksi beton dan baja. Ia menyimpan cerita perjalanan harian, jarak yang biasa ditempuh tanpa banyak pertimbangan, serta hubungan antardesa yang sempat terhenti.
Saat jembatan kembali difungsikan, rasa aman perlahan tumbuh. Ada keyakinan bahwa mereka tidak sepenuhnya sendirian menghadapi dampak bencana.
Pemulihan pascabencana memang jarang tampil dramatis. Ia tidak selalu hadir dalam seremoni atau pidato panjang. Namun, ia nyata dalam kerja yang konsisten.
Pada akhirnya, pemulihan terbesar selalu berada di tangan warga sendiri. Pada kesabaran mereka menata ulang rumah, pada keberanian mereka memulai kembali rutinitas yang sempat runtuh.
Sebagian masih harus menghadapi kehilangan: ternak yang hanyut, ladang yang rusak, tabungan yang terkuras, bahkan anggota keluarga yang tak lagi kembali. Namun, di tengah keterbatasan itu, solidaritas tumbuh. Tetangga saling membantu, makanan dibagi, tenaga dipinjamkan.
Sumatera sedang belajar bangkit, bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan langkah-langkah sunyi yang saling menguatkan.
Di antara lumpur yang mengering, jalan yang kembali terbuka, dan jembatan yang kembali menghubungkan, harapan tumbuh perlahan, tetapi nyata. Harapan bahwa hidup bisa disusun ulang, dan bahwa dari reruntuhan, manusia selalu menemukan cara untuk berdiri dan melanjutkan hidup.