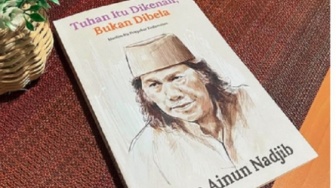Senja tak henti-henti menggodaku untuk menikmatinya. Kesunyian pun selalu berupaya menuai rinduku. Dan, keduanya memang berhasil. Aku merindukan suasananya sunyi dan awan jingga. Tapi kini, aku tak bisa memenuhi kolaborasi keduanya. Aku hendak beranjak menuju sebuah konser yang hingar bingar, meski diadakan di saat sinar mentari senja memancar.
Sore itu, Ibu Kota tengah merayakan sebuah hari raya. “Selamat Hari Raya Jazz,” begitu yang diteriakkan oleh musisi generasi muda, Barry Likumahuwa, ketika tampil dalam perhelatan akbar konser jazz tersebut. Beragam panggung menampilkan para musisi jazz dari yang amatir hingga kelas dunia. Tak jarang pula, nama-nama musisi itu telah mengharu biru dunia musik.
Tak pelak, Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, pun dipadati oleh lautan manusia. Senja menjadi saksi di saat para manusia, tua dan muda, bereksodus ke arena PRJ untuk sebuah perhelatan akbar. Mereka mulai melupaka kesunyian. Bagi mereka, inilah saatnya berpesta dengan musik jazz, sebuah aliran yang kini telah menjadi gaya hidup ketimbang aliran musik.
Kini, suara alam semesta berganti menjadi nada-nada yang dialunkan oleh para musisi jazz. Dari panggung ke panggung, aku menjelajahi, ditemani seorang sahabat. Tidak ada satupun manusia yang kukenal. Mereka datang dengan satu tujuan, mencari alternatif dari rutinitas yang saban hari membelenggu dan menyalurkannya dengan bernyanyi bersama pengalun jazz.
Hingar bingar tak buatku melupakan alam. Aku masih menghela nafas panjang saat lembayung senja bergumul mesra bermandikan cahaya jingga. Mentari pun tampak berseri, menikmati musik yang tiada kencang dan syahdu. Bagaikan suara alam yang berpadu dengan nada artifisial yang diciptakan manusia melalui alat-alat musiknya. Perpaduan yang indah jazz di kala senja.
Tampak, berpuluh-puluh dewata penghuni langit melongok ke arah buana. Mereka mungkin sedikit penasaran dengan hingar bingar yang terjadi. Namun, hingar bingar ini bukanlah perang yang mengorbankan banyak nyawa. Ini adalah hingar bingar perdamaian. Melalui musik, para pengalun jazz menyampaikan pesan-pesan cinta dan kasih sayang kepada umat manusia.
Sejenak, tugas para dewata agak ringan. Mereka pun cuti senja ini, dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyampaikan pesan perdamaian. Tentunya lewat musik mereka yang indah. Terkadang, para dewa ikut bergoyang mengikuti alunan musik. Gerakannya tak ubah seperti nyiur melambai yang diembus angin pantai. Pelan namun santai dan pasti.
Teringat pada aluan suara Orpheus yang syahdu. Penyair ini kerap menghibur para dewata dengan syair dan nada-nada indahnya. Namun, sejak dirinya terpendam dalam kesedihan akibat kematian sang kekasih, Eurydice, musik-musik itu hanya menuai tangis dan kerinduan tak berujung. Hingga akhirnya, Orpheus dipeluk ajal dan malaikat membawa raganya dengan iringan lagu sedih.
Saat ini, telah banyak Orpheus-orpheus yang lain. Mereka memainkan musik riang, bahagia, sendu maupun syahdu. Sebagai titisan Orpheus, para musisi mengemban tugas berat. Bagaimana melontarkan sebuah musik hingga akhirnya bisa membuat pendengarnya terbuai dan terbawa baik dari segi psikologis maupun emosi. Tak jarang, musik membuat para pendengar larut dalam rasa cinta.
Berbagai arena konser aku susuri. Jalan setapak demi setapak,ditemani langkah lain yang berderap. Banyak langkah manusia di sana. Mereka berbondong-bondong ingin menyaksikan penampil favorit yang tengah menyenandungkan alunan jazz. Tak jarang, mereka rela mengantre hingga belasan kilometer demi mendapatkan tempat terdepan, hingga sang musisi terlihat dekat bak dalam dekapan.
Ketika tengah mengunjungi sebuah arena expo yang terletak di dalam sebuah hangar besar, aku melihat sesosok wanita. Aku mengenal punggung wanita itu, dan jilbab sutera yang dikenakannya. Dia berjalan menyusuri setiap selasar area para penampil di sudut-sudut arena. Jalannya cukup cepat, aku tiada sanggup mengimbangi tiada pesat. Dia terus berjalan, dan aku berkali-kali terhenti sejenak.
Saat bisa melampauinya, aku membalikkan badan. Ingin kulihat wajahnya yang tersingkap. Apakah dia wanita yang aku harapkan untuk ditemui? Ternyata bukan. Sosoknya berbeda, kendati ciri fisiknya sama, dengan kulit putih yang menyinari wajah. Tapi, itu bukan dia. Sirna sudah bayangan itu, ketika harap tengah menanti untuk melihat kembali wajah yang lama kunanti.
Bukan kali ini peristiwa terjadi. Berulang kali aku melihat sesosok gadis yang menyerupai dirinya, tapi itu bukan dia. Kiranya, Sang Smara telah menancapkan erat panahnya. Nukilan kisah yang terajut pun kian membuat khayalan itu menjadi nyata. Aku terjebak antara mimpi dan nyata. Tatkala, setiap wujud nyata aku anggap sebagai dirinya. Sebuah bayang yang berulang kali menanggalkan jejak.
Di tengah keramaian, kontan tubuhku merasa sendiri. Aku melihat seluruh manusia bergerak dalam derap yang sangat lambat. Aku berada di tengah, bagai pusaran air yang membentuk sebuah lubang di lautan. Aku bagaikan mata topan yang terjebak stagnasi di tengah pusaran, ketika elemen dan mahluk lainnya tengah terombang-ambing dalam amukan sang Dewa Bayu.
Musik pun hanya sayup-sayup terdengar. Bunyi saksofon mengalun dari kejauhan, dan suara seorang lelaki yang kukenal. Dia adalah Bobby Caldwell, penyanyi yang menjadi raja romansa pada dekade 1980 dan 1990-an. Mengobati rindu, seraya memanjakan rasa, aku menyaksikan penampilan dirinya. Raut wajah renta tampak di sosok Caldwell. Namun suaranya masih menuai nostalgia para penggemar.
Pada ghalibnya, lagu-lagu itu hanya menepis sedikit telingaku. Bagai elegi yang terus bersenandung. Sedangkan, otakku masih disesaki awan mendung. Sesosok malaikat yang sempat mengisi malamku, namun kini tengah kembali ke khayangan. Yang tersisa di dunia hanyalah raga yang tiada kukenal. Hanya sesal yang kini bisa kulayangkan kepada Tuhan, meski aku tahu cinta-Nya abstrak.
“O Tuhan, berdosakah aku? Ketika aku memandang sepasang mata yang indah, dan memuja sosok yang memilikinya, sedangkan dia adalah ciptaan-Mu. Apakah aku dosa? Saat cinta ini terlontar dari hati yang paling jujur, dan getir karena takut malaikat-Mu kembali terbang ke surga. Tiada kumaksud menduakan-Mu, aku hanya ingin memuja ciptaan-Mu yang terindah dan termashyur.”
Tak seberapa lama, Bobby Caldwell menyenandungkan lagu “Back to You.” Tembang yang sejatinya dinyanyikan secara duet dengan Marilyn Scott ini, mengisahkan tentang sepasang kekasih yang kembali bersatu usai mengakui kekhilafan. Dikisahkan, keduanya merupakan sepasang jiwa yang sempurna jika tidak memiliki satu sama lain, dan meleburkan kasih mereka.
Kontan, pikiran langsung tertuju kepadanya. Bagai roket yang melesat tanpa halangan, bayangan pun terbang entah kemana mencari sang pujaan. Tapi, hanya sebatas bayangan, ketika sosok itu kian menjauh dan menjauh hingga hanya setitik debu. Dia hilang di antara bayangan hitam yang aku hadapi. Dia sirna ditelan oleh kabut penantian dan harapan, sampai saat ini.
Lagu ini menjadi pemicu, ketika jiwaku berkelana di sebuah dunia yang sarat kerinduan. Tembang lain menjadi hambar, karena aku tiada mendengar. Dalam impian itu, aku terus menggapai, meski tangan ini enggan bergeming. Hanya kelu yang kupacu. Hanya dengan mimpi aku bisa mendekap bayang itu, meski sebenarnya nyata dan dekat dengan kehidupanku.
Kebencian itu membuat dia berpaling, ketika dulu aku dan dirinya sempat berbicara seperti rumput yang tiada pernah mengering. Selalu, obrolan mengalir bagaikan hujan yang kini tengah membasahi bumi, tanpa malu-malu. Tapi, roda zaman terus bergulir. Kebingungan melanda diri, ketika dia menjauhi saat aku berkata lirih bahwa aku jatuh cinta kepadanya.
Dan, anganku pun melayang seraya menanggalkan jubah kemunafikan. Pikiran terbenam dalam kerinduan. Suara hatiku pun berkata mesra dan tangis yang senantiasa menerpa jiwa. Lalu, aku pun menggoreskan tinta jiwa dalam hati dan pikiran yang terus mengawang:
Setelah itu, hanya punggungmu yang tampak di hadapanku. Aku terus mengejarnya, tapi meraih pun tak kuasa. Suatu saat ketika kau memandang kusejenak, bulir-bulir asmara merasuk ke dalam tubuhku. Tapi, kembali kau memalingkan wajah, sehingga bulir-bulir itu tersendat dalam nadi yang tengah berdetak kencang. Dan, hanya punggungmu yang kembali kutatap.
Setiap hari, saban malam. Aku terus menggoreskan tinta, merangkai kata dan merapal kalimat kerinduan. Ketika mentari terbenam, saat bulan benderang muram. Aku pun senantiasa mencari, dan mencari nada merdu yang bisa mengusir rasa sendu. Lagu cinta, hingga tembang renta. Alunan sedih, sampai nada lirih. Musik keras, hingga syair pedas. Namun, upaya ini nihil.
Bayangmu kian nyata, rasa pun semakin bergejolak mencari dunianya. Tak ada yang sanggup mengusirmu pergi dari imaji ini. Aku mencoba teriak, hanya namamu yang tak kuasa hilang bagai karang tegak. Apa merasuki diriku? Cinta yang kian membeku, atau rasa sesaat yang nantinya akan berlalu. Rasuk nadiku, ketika jantung ini berhenti berlaku. Berhenti sejenak menuai letupan rindu.
"Aku ingin mengisi duniamu, seperti kau mengisi hariku. Aku ingin merangkai bunga kehidupan untukmu. Tatapan dinginmu, senyum ceriamu, suara lembutmu. Aku merindukanmu sungguh. Aku bisa berkaca di matamu yang menyimpan beragam rahasia. Seonggok hati memendam rasa, aku bisa mendengarnya. Kian jelas, meski sayup bersuara.Namun kini seluruh dunia sirna."
Dari balik jendela, aku selalu memandangmu, erat. Dan, aku palingkan wajahku ketika mata itu mencari secercah kebenaran. Lalu, aku pun kembali melihat dirimu. Sekat kaca, tak seberapa tebal memang. Namun, benteng di hatimu begitu kokoh. Tak kuasa aku menatap cahaya benderang. Dalam hati, aku berkata “lihatlah diriku, akulah pemuja rahasiamu. Kau mencuri hatiku yang telah membeku.Kini, kau membawaku ke sebuah padang tak bertepi. Sesatku dalam duniamu. ”
Wahai nona, aku tersesat dalam labirin di hatimu. Kini, sepenggal hati ini telah sirna, raib entah kemana. Aku enggan mencari. Sebab, tak ada daya yang bisa kulakukan. Biarlah kutitipkan hati itu di tanganmu. Buatlah dia bahagia, meski aku harus menanggung segala nestapa. Suatu saat aku akan pergi meninggalkan duniamu, agar kau bisa bahagia berlaku.
Tapi, aku senang mendengar tawamu. Andai aku bisa menuai tawa itu. Hanya ada sesal yang tersisa dalam raga hina ini. Ketika sebuah upaya yang kunjung menuai hasil, hanya doa yang kuhaturkan. Aku bahagia bisa memberikan hati ini untukmu, kendati cinta tak kunjung hinggap di sana. Tapi, apa daya kau memiliki duniamu. Dunia yang kau ciptakan dengan tangan emasmu.
Terima kasih atas inspirasi-inspirasi yang telah kau sematkan dalam bentuk cinta. Sebuah cinta impian yang kurangkai dari sederet kata-kata mesra dan puisi-puisi bernada suka. Suatu saat, aku ingin bertemu denganmu kembali, meski dalam mimpi maupun nyata, dan berkata "aku sayang kamu. Suatu kebahagiaan bisa menuai senyum di wajahmu dan hatimu. "
Hingar bingar jazz pun kembali terdengar, mesra di telinga. Aku merasa temanku telah memanggil. Berulang kali memang, namun suara itu tak singgah di telingaku. Pertunjukkan Bobby Caldwell hampir rampung. Sebuah encore memuaskan dahaga para penonton. Mereka terus bernyanyi, sedangkan aku hanya terdiam di tengah ramainya suara koor yang dirapalkan para penonton.
Raga ini telah kembali ke peraduan, meski pikiran terkadang mengambang. Aku lanjutkan petualanganku sore itu menuju ke arena konser lainnya. Senja pun berganti malam, tanpa terasa bulan kini telah berlabuh di pantai kerinduan. Bermeditasi dalam malam yang kian menusuk kalbu, dengan rindu dendam dan senyum mesra sang Putri Malam.
Sebuah bayangan terkadang membuat diri ini terlena sesaat. Menuai mimpi yang terus melontarkan kata-kata kiasan berisi harapan kepada hati yang telah. Sejenak terlampau, bayangan itupun sambil lalu. Hingga aku pun menyadari, dia hanyalah sebuah bayangan, sudut semu dari dunia yang aku ciptakan sendiri. Bukan nyata yang bisa tersentuh dan kasat oleh mata.
Hingga hari ini aku terus menulis, dan menulis tentang bayangan itu. Berupaya meraihnya lewat untaian kata-kata kerinduan dan mesra. Meski berpuisi untuknya, namun itu bukanlah dia. Tulisanku hanya sebuah bayangan yang aku anggap nyata. Dan, ternyata pun bayangan itu bisa menuai sepiku dalam hingar bingarnya suasana, sampai saat ini.