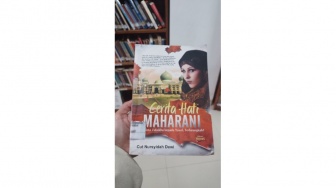Cahaya mentari mulai muncul, burung-burung berjamaah terbang berangkat mencari makan. Suara ayam jantan terdengar nyaring bergantian menghiasi hari yang masih agak petang. Afif bersiap menyusuri jalanan desa, tanpa alas kaki ia mulai melangkah perlahan. Afif memilih rute yang membawanya ke pesisir pantai, ia berniat untuk melihat dengan detail prosesi matahari mulai menampakkan diri.
Tidak ada satu pun kendaraan bermotor melintas. Jalanan masih begitu sepi, selain itu desa tempat Afif tinggal memang belum begitu banyak penduduknya. Afif meneruskan langkahnya sambil sesekali berlari kecil. Rumput-rumput di pinggir jalan telah basah diguyur embun, membuat jalanan kian terasa lebih segar.
Setelah sampai di tempat tujuan, Afif mencari tempat yang paling nyaman untuk menyaksikan matahari perlahan meninggi. Pantai itu belum terlalu ramai, jadi tak sulit untuk mencari tempat nyaman untuk diri sendiri. Afif duduk dengan meluruskan kakinya. Ia menatap cakrawala perairan yang begitu luas, menstimulasi ketenangan dalam dirinya.
Afif lantas merenung, mengingat kembali alasan mengapa dirinya selalu memilih kesendirian. Mengingat sebuah peristiwa yang benar-benar tak bisa dilupakan oleh Afif. Pikiran Afif kini berlari ke masa itu.
*****
Fitri menghubungi Afif, ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Afif di Taman. Afif menyanggupinya, ia pun langsung berangkat ke taman. Sesampainya di taman, keberadaan Fitri belum tampak. “Mungkin dia masih di jalan”, ujar Afif dalam hati. Ia pun dengan sabar menunggu kehadiran Fitri.
Lima belas menit berlalu, akhirnya sosok Fitri nampak dari kejauhan. Afif lantas berdiri untuk menyambut kehadiran Fitri. Ketika jarak sudah dekat, mereka berdua saling bertukar senyum.
“Kita mau duduk di mana?”, tanya Afif.
“Emmm.....kalau jalan-jalan dulu, bagaiaman?”, Fitri memberi saran.
“Boleh, ayo!”
Mereka berdua berjalan pelan mengitari taman, menikmati pemandangan hijau yang tentu cukup sulit ditemukan di perkotaan. Kendati matahari sudah berada di posisi yang cukup tinggi, suasana di taman itu tak terlalu panas karena banyak pohon yang berhasil memberi keteduhan. Angin berhembus tenang mengusir gerah. Hari itu tampaknya layak dijuluki hari yang sempurna.
Afif merasa tenggorokannya kering, ia kemudian mengajak Fitri untuk membeli es jeruk. Selepas mendapat apa yang dipesan, mereka berdua mencari tempat untuk duduk menikmati segarnya es jeruk. Kebetulan Afif dan Fitri melintasi sebuah tempat yang tak terlalu ramai, sehingga mereka berdua bisa dengan segera mendapat tempat. Mereka duduk meluruskan kaki, membiarkan angin berhembus melewati mereka.
“Fif! Aku ada sesuatu yang ingin kuceritakan ke kamu”, ucap Fitri tiba-tiba.
“Oh, iya, cerita aja! Aku berkenan dengerin sampai habis kok”, Afif berusaha berempati.
“Aduh! Gimana ya? Aku bingung mau mulai dari mana.”
“Terserah kamu udah mau mulai dari mana, aku bakal tetap menyimak kok”, Afif mencoba menenangkan Fitri yang tampak resah.
“Kemarin Bu Laeli bilang ke aku kalau judul KTI-nya mau diubah. Padahal, aku ngerjain kira-kira sekarang udah dapet 45 persen. Kalau judulnya diganti, berarti aku harus ngulang lagi dari awal”, Fitri memasang wajah khawatir sekaligus kecewa. Sementara itu, Afif masih terdiam menatap Fitri, ekspesinya menyiratkan ia sedang mencari jalan keluar dari problematika yang dihadapi Fitri tersebut.
“Kalau boleh tahu, kenapa kok judulnya mau diganti?”, Afif bertanya.
“Katanya sih judul itu relevansinya dengan realitas sosial nggak akan lama. Bu Laeli ingin membuat KTI yang manfaatnya bisa diambil jangka panjang, bukan cuma di momen-momen tertentu”, Fitri menjelaskan.
“Emm.....jadi gitu ya”, Afif menganguk-anggukkan kepala sebagai pertanda bahwa ia berusaha untuk memahami situasi yang dihadapi Fitri, “Kamu sendiri gimana? Udah coba memberi argumen untuk mempertahankan judul yang lama?”.
“Haduh, gimana ya!? Bu Laeli itu orangnya kayak nggak bisa diajak diskusi. Maksudnya, ketika dia minta A, maka ya harus A yang diberikan. Jika ada yang membantah, nasibnya nggak akan baik”, raut wajah Fitri tampak menyimpan beban yang begitu berat.
“Repot juga ya kalau kayak gini”, Afif merespons.
“Terus sekarang aku harus gimana?”, tanya Fitri dengan mata yang mulai tampak berkaca-kaca. Ia seolah merasa begitu frustrasi.
Afif menarik napas lalu berusaha menjawab, “Jika memang seperti itu keadannya, kita kayaknya nggak bisa berbuat banyak selain nurutin apa yang diminta Bu Laeli. Tapi tenang, aku akan selalu bersedia membantu kok. Jangan dipendam dalam pikiran sendiri, ya!”, Afif tersenyum meyakinkan Fitri.
“Makasih banyak ya, Fif!”, Fitri balas tersenyum.
“Kita pulang sekarang?”, Afif bertanya demikian setelah menyadari bahwa es jeruk miliknya dan Fitri sudah habis. Selain itu, rasa penat di kaki karena jalan-jalan tadi sepertinya sudah berlalu.
“Boleh!”, Fitri mengangguk. Ketika Afif sudah berdiri, tiba-tiba Fitri berteriak ke arahnya. “Eh! Tunggu, Fif! Kamu mau duduk lagi? Sebentar aja. Aku ingin kamu menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Selama ini kamu sepertinya nggak pernah cerita sama aku tentang problematikamu.”
“Cerita apa? Hidupku ya gitu-gitu aja, pengulangan setiap hari. Makan-mandi-tidur-bangun, gitu terus”, Afif tersenyum.
“Nggak mungkin. Pasti kamu menghadapi masalah. Udah, ayo cerita aja!”, Fitri memaksa.
“Ya masalahku gitu-gitu aja sih kayaknya.”
“Kamu ini kenapa sih, Fif, kok kayak gitu?”
“Iya, iya. Aku bakal cerita, tapi kamu janji ya...”, belum selesai Afif dengan kalimatnya tersebut, Fitri tiba-tiba memotongnya.
“Nggak usah, kamu ngomong aja sama pohon sana!”. Fitri lantas berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Afif tanpa pamit.
Afif terdiam menerima perlakuan Fitri barusan. Ia tertunduk. Dalam pikirannya kalimat Fitri tadi terus terngiang. Afif bertanya-tanya apa salah dia sebenarnya sampai-sampai diperlakukan seperti itu. Sosok Fitri sekarang sudah jauh tak terlihat. Suasana yang tadinya menyenangkan, kini berubah menjadi menyakitkan. Angin berhembus menerbangkan dedaunan yang tak hijau lagi. Menciptakan sebuah pemandangan seolah pohon-pohon tengah menangis dan merasakan kepedihan nurani Afif.
Semenjak kejadian itu Afif berubah menjadi individu yang sangat pendiam, ia bahkan seolah tak akan bicara jika tak diajak bicara. Afif telah menutup rapat pintu niatnya untuk bercerita pada orang lain. Ia merasa diam akan lebih baik daripada disuruh bicara dengan benda mati.
*****
Pikiran Afif kembali, matanya berkaca-kaca tapi ia menahannya agar tak terjatuh. Afif menghirup napas dalam, mencoba menenangkan pikiran. “Barangkali hanya Tuhan yang berkenan mendengar segala resah dan tangisku”, ucap Afif dalam hati. Lantaran apa yang dialaminya tersebut, Afif belajar untuk selalu berusaha mendengarkan seseorang ketika ia bercerita padanya. Ia juga menyadari bahwa semua manusia memiliki telinga, tapi tak semua manusia berkenan mendengar.
Barangkali orang yang seperti itu lebih tuli dari orang tuli. Orang tuli secara fisik kadang masih berkenan mendengarkan dan memahami meski dengan cara yang berbeda. Hal inilah yang membuat orang tuli lebih baik daripada orang yang bisa mendengar tapi menutup telinganya.
Dilihat dari posisi matahari saat ini, sepertinya sudah menunjukkan pukul setengah 7 pagi. Sudah saatnya bagi Afif untuk kembali ke rumah. Ia merasa lebih lega, setidaknya alam tak pernah menolaknya untuk berbagi kisah. “Benar apa kata Fitri, memang sebaiknya aku bercerita pada pohon saja. Sebab, ia pasti tak akan menolak dan menghakimi. Berbanding terbalik dengan manusia”, Afif bicara dalam hati. Afif mulai mengangkat kakinya, meninggalkan pesisir yang pantai yang mulai didatangi nelayan sehabis menangkap ikan tadi malam.