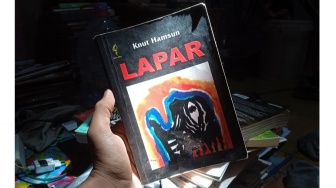Bibir menghitam tampak sedang digigitnya sebatang rokok dengan asik berbincang di serambi rumah tua. Asik berbisik dan melantur sana sini. Apalah boleh buat, kesehariannya dihabiskan untuk konsolidasi sana sini.
Keadilan dan perjuangan jadi andalan dimana ia bersinggah. Kawan-kawan melongo karena kagum omelannya bisa mengubah arah pikir yang jumud. Tak sedikit, ingin juga mencekik lehernya kala tak bisa mematahkan omelannya.
Aktivis warung kopi, begitulah sebutannya. Tiap kali jadi patron kala berdiskusi. Ada saja di dalam otaknya, hingga tak habisnya-habisnya topik yang akan disampaikan. Dari mulai seonggok jagung hingga konspirasi politik global yang semakin membuat berbusa mulut mereka kala memulai diskusi.
Lusuh, pakaian seadanya. Tapi, tak akan lupa sebungkus rokok dikantong celananya yang bau itu. Idealisme masih tertancap, terpatri dan tak tau kapan itu semua mati. Di akalnya hanya ada satu, "lawan, lawan dan lawan."
Semangat waktu muda kadang jadi momen berbunga-bunga dari sekian ratus golongan tua kala meromantisir masanya pada kala itu. Darah panas dan geliat rasa ingin tahu tinggi, tak lekang dari apa itu pemuda.
Menariknya masalah studi agar lulus cepat waktu, bagi mereka asing dan tak berbobot. "Bukan tentang ijazah dan IPK tinggi, tapi tentang esensi ilmu dan subtansinya." Kala itu masih diserambi rumah tua yang disewa sebagai markas mereka.
Tetes demi tetes air kran sengaja dinyalakan agar tak kena beban bayar bulanan, mengisi sela-sela berbincangan yang lumayan hangat itu. "Apa itu idealisme?" Celetuk diantara tiga pemuda dengan pakaian yang serba gelap ditambah rambut sebahu. Khas sekali, kebebasan.
Dosen penguji mengancam, bila saja mau skripsi harus potong rambut seperti serdadu. Tak bisa semudah itu. Ia malah tancap gas membabat anti gondrong. Bukan tentang rambut, bila saja bisa dari akal kenapa harus rambut?
Elan vital mereka kadang dianggap gila, pasalnya super berani untuk jadi beda. Kadang, juga mengeluarkan jurus eksistensialis ala Sartre agar dibilang berdasar dan tak sembarangan.
"Idealisme itu tentang keberanian kita menjadi diri kita dan tak mau menjilat apa yang kita tak sepakati." Sambil menyeruput secangkir kopi Lampung dengan ciri khas serbuknya menempel di bibirnya yang menghitam pekat.
Dibeberkannya maknawi idealisme. Sampai dikaitkannya surutnya gerakan aktivisme di era hari ini. Sepi, takut senior, sampai pantikan mahasiswa lulus cepat kala menghujat gerakan aksi masa sebagai bunyi-bunyian kuno.
Bertiga berasal dari sudut pandang keluarga yang berbeda. Lui, anak seorang pengusaha, Jo, anak orang serabutan dan Deu anak serdadu berpangkat sedang. Mereka semua bertemu dalam jurang aktivisme penuh dengan bunuh diri kelas.
Dipaksa melepas segalapun melekat dari orang tua atau keluarga. Yang ada, hanyalah aku, kamu dan apa itu aku dan kamu? Kamu dan aku itu yang memilih, bukan dia ataupun mereka yang menentukan. Sering juga, orang tuanya merasa pedih, makhluk apa yang merasuki tubuhnya? Tak sesuai ekspektasi mamak atau bapaknya. Lebur, hancur dan pasrah, begitulah ibu bapaknya mengharap pada Tuhannya.
Disekeliling markasnya banyak sekali rumah reot, dan beberapa melacurkan diri untuk sesup nasi. Mobil motor bersliweran diperhatikan mereka dan tak kaget karena keramaiannya jadi lokalisasi penjemputan di rumah bordil kata emak-emak penjual rokok. Masalah Ekonomi jadi faktornya kalau kata ekonom. Kalau kata kyai, karena tak giat menyembah Tuhannya. Deu merenung, meresapi lingkungan mereka.
Terbentur kepalanya sampai akal idealismenya itu ketika melihat sekeliling manusia dan segala hiruk pikuk desa itu. Mampus, semua butuh sesuap nasi, bukan obrolan kritis yang tak membuat kenyang. Terbesit sesaat kala, nenek tua dengan rambut kusut tak tau arah pulang dan tak tahu, mengapa anaknya tak merawat.
"Nampakanya, kamu ada tekanan?" celetuk Jo kala melihat muka Deu kosong karena terbentur pikirannya. Terkaget deu, dan disampaikannya pikiran yang baru saja mengetuk kalbunya.
Semua butuh sesuap nasi. Bukan lagi lanturan sana sini dengan klaim keadilan. Lantur Deu malam itu mengagetkan Jo dan Lui. "Tak bisa semudah itu menyalahkan kami yang berfikir, kita ngomong itu juga termasuk aksi." Celetuk Jo.
"Coba kau lihat di tepi sana." Dilihatnya nenek tua dengan baju bolong di bawah lengannya. Kemana pergi anaknya? Apakah tak kuat dengan kondisi, hingga giat cari nasi hidup lupa orang tua? Bukanlah miris?
Coba kau pikirkan kembali! Bisakah kau hidup dengan ngopi dan melantur saja? Dunia ini keras tak semudah dengan apa yang apa dipikiran mu semua.
Ya, minimal ahli melantur bisa sikut sana sikut sini atau bisa juga kenyang di ibukota jadi penguasa. Geremang Jo, sambil mematikan rokoknya yang membakar jarinya. Harapan Jo, jadi politikus yang selalu kenyang dan mungkin juga jadi jongos para seniornya.
"Ya, awalanya jadi jongos, lama-lama bisa jadi komisaris atau minimal dapat tanah usaha lah." Melotot Jo sambil menuding muka Deu yang melongo itu.
Deu senang ketika temannya punya visi dan misi lumayan ambisius itu. Hidupnya, yang penuh derita, tinggal di rumah reot bersama adik dan orang tuanya, semakin menjadi ambisinya untuk memutar balik keadaan. Minimal hidupnya tak sebobrok hari ini.
"Loh, lalu gimana kamu bisa teguh pada idealismemu itu?" Tanya Deu sambil meregangkan punggungnya yang lumayan pegal. "Nah itulah idealismeku, pikirku hanya satu, keadilan untuk semua, apapun itu jalannya." Diulap tetasan liur Jo, kala ngoceh begitu semangat.
Liu memperhatikan kedua temannya asik berdiskusi. Liu memikirkan lamat-lamat apa yang di pikiran Deu. Memang masalah sesuap nasi itu pelumas kehidupan. Pasti semua butuh dan tak mungkin menghindar.
Bila saja menghindar pasti saja kurus dan tak mau bergaul karena minder baju yang dipakai hanya monoton. Atau bisa saja, tak mau bergaul dengan kawan kecil karena malu terlihat kuno.
Liu masuk dengan penuh penghayatan menyikapi perdebatan malam itu. Liu menjabarkan beberapa kaitan antar tekanan hidup untuk pemenuhan kebutuhan hingga idealisme dan karakter dini menerjang peradaban.
Keberpihakan dan karakter memang sebuah perihal pelik dan patut untuk dibicarakan. Marwah dan karakter itulah kuncinya. Percuma saja bila yang diperjuangkan luput tak lagi diilhami. Semua punya jalan dan pilihan hidup.
Nenek tua yang menderita bisa jadi karena derita dari anaknya yang tak mau merawat atau karena ia tak mau menentang realitas. Pilihan dan karakter itulah yang akan jadi saksi bisu kehidupan. Nenek itu bisa hidup enak dan tak memakai pakaian bolong bila diri dan eksistensi bisa kuat. Tapi juga tak luput dengan eksistensi yang dilahirkan beliau yaitu anaknya.
Apapun itu, tanggung jawab pada karakter dan keberpihakan harus diterima penuh semua resikonya. Kembali lagi pada kamu semua, tanggung jawab kah dengan pilihan hidupmu? Atau malah menyalahkan dunia?