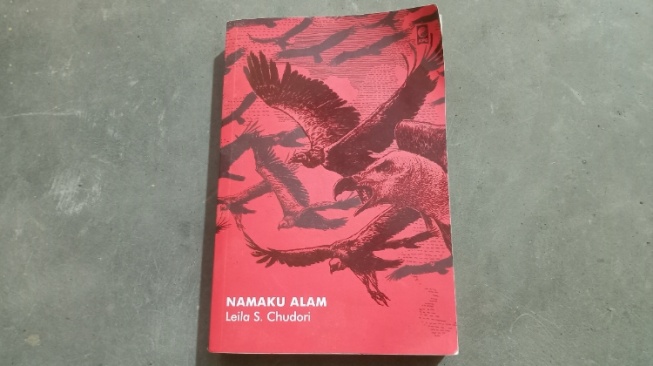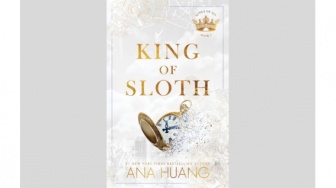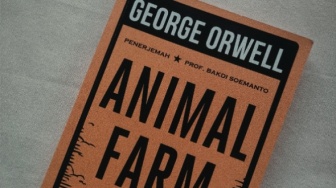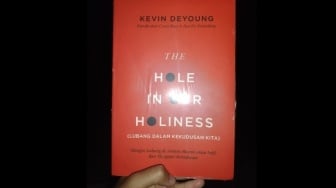Namaku Alam adalah sempalan dari novel Pulang. Keduanya berpijak dari peristiwa Gerakan September Tigapuluh (Gestapu) 1965.
Jika Pulang memfokuskan cerita perihal para eksil yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan terkatung-katung di negeri orang, Namaku Alam menuturkan liku-liku kehidupan keluarga tahanan politik (tapol) di Tanah Air.
Adalah Segara Alam, tokoh utama novel ini. Dia anak bungsu dari Hananto Prawiro, wartawan anggota Lekra; organisasi kebudayaan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Karena Hananto dianggap “terlibat” Gestapu, maka demikian pula istri dan anak-anaknya. Mereka terpaksa menanggung “dosa warisan” akibat tidak “bersih lingkungan”, kendati tidak tahu-menahu afiliasi dan aktivitas politik sang kepala keluarga.
Bersama Ibu dan kakak-kakaknya, sejak kecil, Alam mengalami diskriminasi, intimidasi, dan persekusi terkait status mereka sebagai keluarga tapol.
Celakanya, Alam memiliki photographic memory. Dia mampu mengingat dengan rinci semua peristiwa yang telah maupun sedang dialami. Tidak terkecuali peristiwa penodongan pistol oleh tentara kepadanya, di rumahnya sendiri, saat dia berusia tiga tahun.
Bagi orang-orang, kemampuan photographic memory Alam adalah anugerah. Di antaranya karena dia bisa mengingat semua pelajaran sekolah dengan baik dan bisa melibas seluruh pertanyaan cepat tepat secara sempurna.
Bagi ibu dan kedua kakaknya, ingatan tajam Alam sangat berguna menyelesaikan persoalan sehari-hari, seperti mencari kacamata, buku yang terselip entah di mana, atau tanggal penting hajatan relasi keluarga (halaman 33-34). Bagi Alam sendiri, kemampuannya adalah, “... sebuah kutukan yang sangat mengganggu.” (halaman 31).
Photographic memory seperti lingkaran setan yang terus membelit dan menjerat Alam tanpa ampun.
Alam tumbuh menjadi pribadi temperamental. Dia lekas naik darah dan tak segan-segan berbaku hantam jika keluarganya dipersekusi lantaran “status” mereka. Ini tentu memicu persoalan baru.
Keluarga terus-menerus meyakinkan Alam untuk “merunduk”. Istilah bagi keluarga tapol untuk jangan menonjolkan diri dan selalu berupaya mencari “aman”.
Nyatanya, hidup sebagai keluarga tapol seperti berjalan di atas hamparan tanah penuh ranjau di dalamnya. Tidak pernah ada kata aman, apalagi nyaman.
Apalagi bagi Alam yang kecerdasan dan kondisi fisiknya terlampau menonjol, sehingga dia selalu dilibatkan dalam kegiatan komunal, seperti klub Para Pencatat Sejarah dan berbagai pertandingan Karate maupun perlombaan guna mewakili sekolah.
Namaku Alam adalah jenis bacaan yang cenderung muram dan gelap. Novel ini tidak direkomendasikan dibaca kalangan 17 tahun ke bawah dan orang-orang yang memiliki pengalaman traumatik terkait tindak persekusi jangka panjang.
Bagi orang-orang yang terkena “dosa warisan” karena menjadi keluarga tapol, novel ini pun perlu dipertimbangkan sebagai bahan bacaan, karena barangkali bisa membangkitkan kenangan buruk.
Bagi saya sendiri, novel ini sengaja dihadirkan sebagai pengingat akan luka bangsa Indonesia di masa lalu yang belum sepenuhnya disembuhkan.
Perlu ada upaya bersama—bagi orang-orang yang pro-PKI dan organisasi-organisasi underbow-nya maupun kalangan yang kontra—untuk membicarakan secara jujur dan terbuka guna rekonsiliasi.
Kita sama-sama mafhum, sejarah tidak pernah hitam-putih, bahkan tidak jarang abu-abu. Dalam hal Gestapu 1965, kesalahan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Baik pihak yang pro-PKI maupun kontra, punya andil yang tidak sedikit.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS