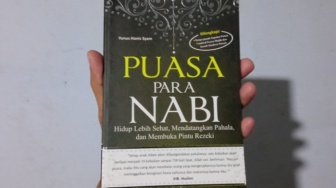Kalau ada satu hal yang selalu membuat ‘kita’ kembali ke film-film animasi Jepang, terutama dari Studio Ghibli, (mungkin) karena cerita yang disuguhkan dibalut dengan kelembutan yang begitu mengena di hati.
Ya, kisahnya nggak ada dramatisasi berlebihan, tapi menyisakan jejak dalam yang nggak mudah dilupakan. Begitu juga saat pertama kali aku nonton ‘The Wind Rises’, film yang nggak cuma bicara soal pesawat, tapi juga soal mimpi, cinta, dan kehilangan yang diam-diam menggerogoti dari dalam.
Disutradarai Hayao Miyazaki, sutradara legendaris di balik Film Spirited Away, Film Howl’s Moving Castle, hingga Film Princess Mononoke, ‘The Wind Rises’ terasa seperti film yang paling pribadi.
Dirilis pada tahun 2013 dan diproduksi Studio Ghibli, film ini menghadirkan kisah semi-biografi fiksi tentang Jiro Horikoshi, sosok insinyur Jepang yang merancang pesawat tempur legendaris Mitsubishi A5M dan A6M Zero yang digunakan dalam Perang Dunia II. Namun, alih-alih fokus pada sisi militeristik atau teknis semata, Miyazaki membawa cerita ini ke arah yang lebih humanis dan filosofis.
Film ini dibintangi oleh pengisi suara ternama, di antaranya:
- Hideaki Anno sebagai Jiro Horikoshi
- Miori Takimoto sebagai Naoko Satomi
- Hidetoshi Nishijima sebagai Honjo
- Masahiko Nishimura sebagai Kurokawa
- Dan masih banyak bintang pengisi suara lainnya
Sekilas tentang Film The Wind Rises
‘The Wind Rises’ mengikuti perjalanan hidup Jiro Horikoshi, anak laki-laki yang sejak kecil terobsesi dengan dunia penerbangan. Sayangnya, impiannya untuk menjadi pilot harus pupus karena gangguan penglihatan yang dia alami.
Namun, Jiro bukan tipe yang mudah menyerah. Dalam mimpi-mimpinya, dia sering bertemu dengan desainer pesawat asal Italia, Giovanni Caproni, yang menjadi semacam mentor spiritualnya. Caproni menyarankan: jika Jiro nggak bisa menerbangkan pesawat, maka dia bisa menciptakannya.
Dari situ, Jiro menempuh pendidikan teknik dan bekerja di Mitsubishi, di mana dia perlahan naik menjadi perancang pesawat berbakat. Namun dunia nggak hanya berputar pada desain dan mesin. Di tengah perjalanan hidupnya, Jiro bertemu kembali dengan Naoko, gadis yang pernah dia bantu saat gempa besar Kanto melanda Tokyo tahun 1923. Pertemuan yang terlihat sederhana itu menuntun mereka pada kisah cinta yang lembut, rapuh, dan pada akhirnya tragis.
Asli, sedih sih nonton ini, tapi buat Sobat Yoursay yang kepo dengan kesan-kesannya, sini merapat dan kepoin bareng!
Impresi Selepas Nonton Film The Wind Rises
Saat menonton The Wind Rises, aku merasa sedang membaca surat pribadi dari Hayao Miyazaki untuk dirinya sendiri. Film ini nggak seperti karya-karyanya yang lain yang penuh dengan makhluk ajaib atau dunia imajinatif yang liar. Di sini, semuanya terasa lebih nyata, dan justru karena itu, terasa lebih menyentuh.
Sebagai penonton, aku seperti diajak masuk ke kepala Jiro. Aku melihat dunia dari balik kacamatanya: langit yang luas, mesin yang rumit, dan cinta yang perlahan memudar karena waktu.
Salah satu hal yang langsung mencuri perhatianku adalah bagaimana film ini menyatukan realita sejarah Jepang dengan fragmen mimpi Jiro yang surealis, terutama adegan-adegan dialog dengan Caproni. Mereka seperti percakapan batin seorang pria yang mencari makna dalam karyanya, sambil menyembunyikan luka-luka yang nggak sempat dirinya obati.
Ya, aku terkesan dengan cara Miyazaki menyampaikan tragedi dengan sunyi. Nggak ada ledakan emosi, nggak ada jeritan, hanya gestur kecil dan kata-kata sederhana yang justru terasa lebih pedih. Adegan ketika Jiro melihat Naoko yang semakin lemah, tapi masih menyemangatinya dengan suara lembut, itu bukan hanya menyedihkan, tapi juga menghancurkan. Sampai-sampai aku nyaris lupa lagi nonton film animasi, soalnya emosi yang hadir terasa sangat manusiawi.
Namun, di sisi lain, aku juga harus jujur. Ada bagian tengah film yang terasa agak melandai. Proses Jiro membangun pesawat kadang terasa terburu-buru, seperti rangkaian montase yang nggak nggak cukup waktu untuk mendalami perjuangan teknis maupun emosional yang Jiro hadapi. Namun, entah kenapa, aku tetap memaafkannya. Karena ketika paruh akhir film datang, semua perasaan yang sempat teredam itu kembali mengalir deras.
Hubungan Jiro dan Naoko, meski nggak diberi banyak waktu di awal, anehnya bisa menjadi pusat gravitasi emosional cerita. Serius, aku merasa ikut tenggelam dalam konflik batin Jiro yang terjepit antara impian masa kecilnya dan kenyataan pahit bahwa impian itu mungkin menghancurkan hal-hal yang dirinya cintai.
Oke deh. Bagiku, ini bukan film yang akan aku tonton untuk bersenang-senang. Ini adalah film yang akan aku pilih ketika aku merasa perlu ‘me time’. Ups.
Skor: 4,2/5