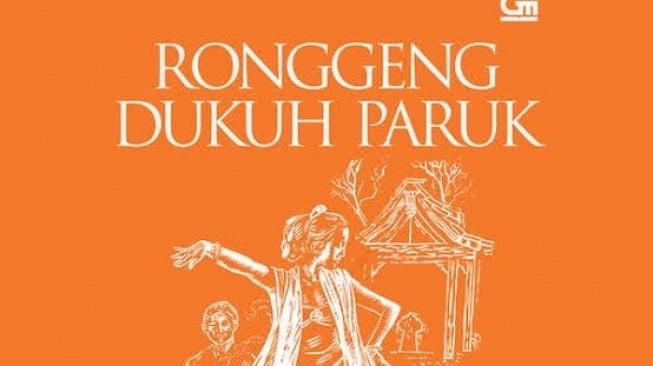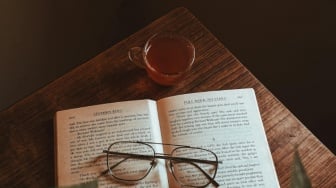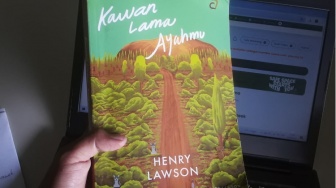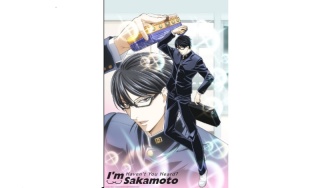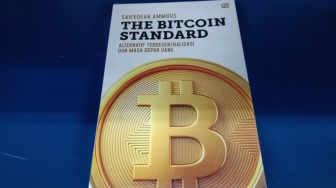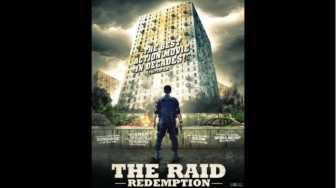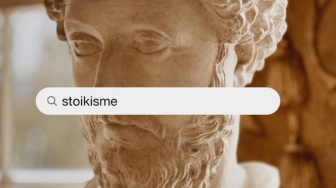Ketika sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk menjadi panggung utama, dan seorang gadis bernama Srintil menjadi penarinya, kita tidak sedang membaca dongeng tentang tarian dan kecantikan. Kita sedang memasuki dunia yang dipenuhi aroma tanah basah, suara gamelan yang menggetarkan hati, dan sejarah yang berbisik dalam senyap. Inilah kekuatan utama dari Ronggeng Dukuh Paruk, mahakarya Ahmad Tohari yang tak lekang oleh waktu.
Diterbitkan pertama kali pada 1982, novel ini membuka luka-luka sosial yang tersembunyi di balik ritual tradisional, sekaligus menjadi narasi yang kuat tentang perempuan, cinta, dan kekuasaan. Ahmad Tohari menulis dengan ketajaman mata hati: ia tak hanya bercerita, tapi mengajak kita merenung dan bertanya ulang “apa makna menjadi manusia?”
Srintil: Antara Panggung, Tubuh, dan Takdir
Di Dukuh Paruk, ronggeng bukan sekadar hiburan rakyat. Ia adalah utusan gaib, pembawa berkah, dan pelipur lara bagi desa yang hidup dalam keterasingan dan kemiskinan. Ketika Srintil terpilih menjadi ronggeng, seluruh desa bergembira, seolah kehidupan akan kembali mengalir. Namun, di balik kegembiraan itu, Srintil harus melepas keperawanannya dalam ritual "bukak klambu", menjadikan tubuhnya konsumsi publik demi tradisi.
Di sinilah paradoks terjadi. Srintil, gadis polos yang hanya ingin dihargai dan dicintai, dipuja oleh desa tapi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia menjadi simbol kekuatan sekaligus ketakberdayaan perempuan dalam jaring adat dan patriarki. Ahmad Tohari menggambarkannya dengan penuh empati, tanpa menempatkan Srintil sebagai korban pasif, tetapi sebagai sosok yang berani menyadari luka, dan perlahan berusaha melawannya.
Rasus: Cinta yang Tak Pernah Sampai
Jika Srintil adalah ronggeng, maka Rasus adalah saksi hidup dari dilema cinta dan harga diri. Sebagai sahabat masa kecil, Rasus mencintai Srintil dengan tulus. Namun cintanya diuji ketika ia harus menerima kenyataan bahwa gadis yang dicintainya telah "menjadi milik desa". Rasus memilih menjauh, menjadi tentara, dan membawa luka itu ke dunia yang lebih luas—dunia kekuasaan dan politik negara.
Hubungan Rasus dan Srintil adalah potret cinta yang kalah oleh sistem. Bukan karena mereka tak saling mencintai, tetapi karena dunia di sekeliling mereka tak mengizinkan cinta bertumbuh bebas. Di antara bayangan gamelan dan suara tembakan, mereka saling kehilangan dalam diam.
Dukuh Paruk: Desa Kecil dalam Arus Sejarah Besar
Salah satu kekuatan Ronggeng Dukuh Paruk terletak pada latarnya yang unik: sebuah desa miskin, terisolasi, dan masih sangat memegang kepercayaan animistik. Di sinilah Ahmad Tohari menghadirkan kritik sosial yang tajam, tanpa perlu berteriak. Dukuh Paruk adalah simbol dari komunitas-komunitas kecil di Indonesia yang seringkali tersingkir dari pembangunan, dan hanya menjadi objek kebijakan dari luar.
Namun sejarah tidak pernah benar-benar netral. Ketika arus politik nasional merambah desa (dalam hal ini, tragedi 1965 dan tuduhan keterlibatan Partai Komunis Indonesia)Dukuh Paruk ikut terseret. Srintil dan masyarakatnya menjadi korban dari kekerasan negara, bukan karena mereka melawan, tapi karena mereka tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Ahmad Tohari menunjukkan bahwa dalam sejarah Indonesia, banyak orang dihukum bukan karena bersalah, melainkan karena mereka tak cukup beruntung untuk dilindungi.
Seni, Tubuh, dan Moralitas
Pertanyaan yang menggema sepanjang novel ini adalah: apakah ronggeng itu seni atau dosa? Srintil adalah penari, tapi juga dianggap penggoda. Tubuhnya dipuja sekaligus dicemooh. Di sinilah Ahmad Tohari mengajak pembaca berpikir ulang tentang moralitas. Apakah kita punya hak menilai pilihan hidup seseorang ketika seluruh hidupnya ditentukan oleh tradisi dan tekanan sosial?
Ronggeng, dalam novel ini, bukan hanya simbol budaya. Ia adalah cermin. Ia memantulkan wajah masyarakat kita: yang gemar menghakimi, tetapi enggan memahami. Yang bersorak saat dihibur, tapi cepat menuding saat moralitas dipertanyakan.
Gaya Bahasa dan Keindahan Cerita
Tak hanya kuat dalam pesan, Ronggeng Dukuh Paruk juga memikat lewat keindahan narasinya. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang lembut, nyaris seperti berdoa. Ia menggunakan metafora yang hidup, bahasa yang puitis, dan narasi yang mengalir tenang namun menghantam batin.
Setiap halaman terasa seperti lukisan desa: ada sawah yang menguning, aroma nasi jagung, senyum anak kecil, dan suara gamelan yang mengiringi duka. Pembaca tidak hanya melihat cerita, mereka ikut merasakannya.
Kesimpulan: Tarian Sunyi yang Tak Pernah Selesai
Ronggeng Dukuh Paruk bukan sekadar novel. Ia adalah catatan sejarah, puisi kesedihan, dan refleksi sosial yang masih sangat relevan hingga kini. Srintil menari bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk menyampaikan pesan: bahwa menjadi perempuan, miskin, dan lahir di tempat yang salah sering kali adalah sebuah kutukan yang tak adil.
Namun di balik segala kesedihan itu, Ahmad Tohari tetap menghadirkan harapan. Harapan bahwa manusia bisa memilih. Bahwa luka bisa disembuhkan. Bahwa bahkan dalam dunia yang sunyi dan kejam, cinta dan keberanian tetap bisa tumbuh.
Dan Srintil, dengan langkah kakinya yang lembut namun pasti, menjadi simbol dari kekuatan itu “sebuah tarian sunyi yang tak pernah benar-benar selesai.”
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.