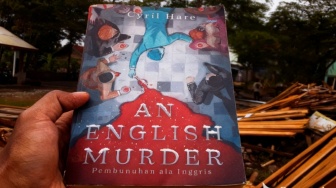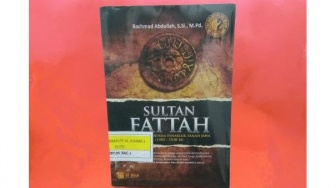Havoc merupakan film aksi-thriller yang tayang perdana di Netflix pada 25 April 2025. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Gareth Evans, yang dikenal lewat karyanya yang fenomenal seperti The Raid dan serial Gangs of London.
Film berdurasi 150 menit ini dibintangi oleh deretan aktor kenamaan seperti Tom Hardy, Jessie Mei Li, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Luis Guzman, Quelin Sepulveda, Yeo Yann Yann, Sunny Pang, dan Michelle Waterson Gomez.
Proses produksi Havoc sendiri telah dimulai sejak pertengahan 2021 di Wales dan sempat mengalami penundaan hingga menjalani syuting tambahan pada pertengahan 2024.
Konflik bermula ketika sekelompok pemuda yang terdiri dari Charlie (Justin Cornwell), Mia (Quelin Sepulveda), Johnny (Xelia Mendes Jones), dan Wes (Jom Caesar) —mencuri sebuah truk kontainer pengangkut mesin cuci yang ternyata berisi kokain dalam jumlah besar.
Aksi tersebut membuat mereka diburu oleh unit kepolisian yang dipimpin Vincent (Timothy Olyphant), bersama tiga rekannya, Hayes (Gordon Alexander), Cortez (Serhat Metin) dan Jake (Richard Harrington). Dalam pengejaran yang brutal dan menegangkan, Cortez mengalami luka parah akibat tertimpa mesin cuci.
Setelah berhasil lolos dari kejaran para polisi, Charlie dan Mia kemudian membawa kokain curian itu ke markas Triad milik Tsui Fong (Jeremy Ang Jones) , sebagai cara untuk melunasi utang Mia.
Namun, di tengah-tengah transaksi, sekelompok orang bertopeng dan bersenjata menyerbu markas tersebut dan membantai hampir seluruh orang di dalamnya, termasuk Tsui.
Charlie dan Mia berhasil melarikan diri, akan tetapi mereka kini diburu oleh banyak pihak lantaran dicurigai sebagai dalang pembantaian tersebut.
Di tengah kekacauan ini, Patrick Walker (Tom Hardy), seorang polisi 'kotor' dengan reputasi kelam, ditugaskan untuk turun tangan.
Walker selama ini bekerja sebagai fixer bagi Lawrence Beaumont (Forrest Whitaker), tokoh berpengaruh yang tengah mencalonkan diri sebagai walikota dan sekaligus ayah dari Charlie.
Ketika Lawrence mengetahui putranya dituduh membunuh Tsui, ia memerintahkan Walker untuk melacak keberadaan Charlie sebelum kelompok kriminal lain atau pihak kepolisian menemukannya.
Dalam proses pelacakan, Walker dibantu Ellie (Jesse Mei Li) , polisi muda yang masih memegang idealisme dan belum terkontaminasi sistem yang korup.
Namun, misi ini justru menyeret Walker pada kenyataan pahit tentang institusi tempatnya bekerja. Ia menemukan bahwa beberapa kolega sendiri, termasuk dari unit narkoba, terlibat dalam peredaran obat terlarang dan bersedia melakukan apa pun untuk menutup jejak.
Review Film Havoc
Nama Gareth Evans tentu tak asing bagi para penikmat sinema laga. Lewat The Raid dan sekuelnya, ia dikenal sebagai sutradara yang menghadirkan adegan kekerasan dalam bentuk koreografi laga yang artistik dan menegangkan.
Maka ketika Havoc diumumkan sebagai proyek Netflix terbaru dengan Gareth Evans di kursi sutradara dan Tom Hardy sebagai pemeran utama, ekspektasi pun langsung meroket.
Namun, apakah Gareth Evans benar-benar mampu menghadirkan kembali sensasi brutal nan elegan seperti yang dulu ditawarkan The Raid?
Meski tak seikonik pendahulunya, Havoc tetap memperlihatkan kebolehan Gareth Evans dalam merancang sederet aksi yang eksplosif dan penuh energi.
Mulai dari adegan kejar-kejaran di jalan raya di awal film, duel sengit di klub malam, hingga bentrokan berdarah di sebuah kabin bersalju— semuanya digarap lewat pengarahan kamera yang luwes serta permainan komposisi visual yang presisi.
Slow motion dramatis, pecahan kaca berhamburan, peluru yang berterbangan, tubuh terpental, dan darah berceceran berpadu untuk menghasilkan pengalaman sinematik yang memompa adrenalin penonton.
Dalam banyak momen, Havoc bahkan terasa seperti gabungan dari atmosfer John Wick dan realisme kasar Children of Men, hanya saja tanpa emosi yang benar-benar menggigit.
Salah satu adegan paling mencolok datang dari sekuens panjang di Medusa Club. Klub malam dua lantai dengan pencahayaan neon temaram tersebut, menjadi panggung aksi tanpa henti.
Musik elektronik Gesaffelstein berjudul Obsession mengiringi pertarungan yang berlangsung hampir tanpa jeda, dengan senjata yang terus berganti—dari pipa logam yang diayunkan seperti pedang, ember es, botol sampanye, kapak kecil, pisau pemotong daging, hingga tongkat pemukul.
Gareth Evans dan tim bahkan menghabiskan hampir tiga minggu hanya untuk merampungkan adegan ini, dan hasilnya memang patut diapresiasi.
Namun, sayangnya, kekuatan aksi tersebut tidak diimbangi dengan narasi yang solid atau karakterisasi yang memikat.
Tom Hardy, meskipun tampil intens, tidak diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan perannya sebagai Walker.
Karakternya terasa fungsional, seolah hanya sebagai penghubung antara satu adegan aksi ke adegan aksi berikutnya. Tidak ada perkembangan karakter yang berarti, dan tidak ada konflik batin yang membuat kita benar-benar peduli padanya.
Begitu pula dengan tokoh-tokoh lainnya. Aktor-aktor berbakat seperti Forest Whitaker, Sunny Pang, dan Timothy Olyphant hanya muncul sesekali, tanpa peran yang benar-benar berkesan.
Bahkan Jessie Mei Li, yang sebenarnya tampil cukup baik sebagai partner idealis Walker, tetap tak punya banyak ruang untuk bersinar.
Narasinya juga bergerak dalam pola repetitif—Walker masuk ke wilayah musuh, bertarung, keluar, lalu mengulang siklus serupa tanpa banyak dinamika dramatis. Konflik yang melibatkan polisi, politisi, dan geng Triad juga kurang digali secara mendalam.
Secara visual, Havoc memang tampil mengesankan. Sinematografer Matt Flannery kembali menjadi partner setia Gareth Evans dalam membangun atmosfer dunia yang murung dan depresif.
Kota fiktif yang menjadi latar film dihidupkan dengan palet warna kelabu, pencahayaan redup, dan tekstur urban yang penuh gang-gang sempit, lorong gelap, dan apartemen bobrok.
Gaya shaky cam yang digunakan juga mampu menambah intensitas dan urgensi. Namun, penggunaannya yang terlalu sering, terutama dalam ruang sempit dengan cahaya minim, justru membuat pengalaman menonton menjadi melelahkan.
Ada titik di mana gerakan kamera terasa terlalu agresif, mengaburkan detail koreografi yang sebetulnya sudah kuat tanpa perlu dimanipulasi secara visual.
Aspek teknis lainnya, seperti penggunaan CGI, terutama dalam adegan kejar-kejaran, juga kurang mulus. Alih-alih mendukung imersi, efek komputer ini justru terasa artifisial dan kurang selaras dengan atmosfer gritty yang dibangun.
Sebagai penggemar film aksi, saya mengakui bahwa Havoc memang punya banyak momen yang memuaskan secara teknis—dari staging aksi yang masif, sinematografi yang cukup konsisten, hingga sound design yang menghentak.
Penonton akan dibuat tegang, meringis, bahkan terkagum-kagum oleh kebrutalan yang dipamerkan. Namun, kekosongan dalam struktur naratif serta minimnya eksplorasi karakter membuat keseluruhan film terasa kurang menggigit.
Jadi ketika film selesai, sensasinya pun cepat menguap. Tidak ada emosi yang tertinggal, tidak ada karakter yang benar-benar melekat dalam ingatan.