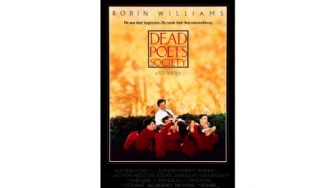Ada satu nama yang sulit dilupakan setelah nonton Film Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight, yakni karakter Bobo. Gadis kecil si tokoh utama, yang merangkap jantung dari keseluruhan cerita.
Film ini adaptasi dari buku autobiografi karya Alexandra Fuller, dan berhasil dihidupkan berkat penyutradaraan Embeth Davidtz, aktris asal Afrika Selatan yang kini menunjukkan kepiawaiannya di balik kamera. Sentuhan personalnya terasa kuat lho, seolah-olah penonton diajak menyusuri jalanan berdebu dan ruang keluarga yang nggak pernah benar-benar tenang bersama si kecil Bobo dan keluarganya yang penuh kontradiksi.
Durasinya ±98 menit, tapi perjalanannya terasa panjang, karena bukan hanya soal cerita perang, tapi juga tentang luka yang mendera, ketidakadilan yang menimpa, dan cara anak kecil menyerap dunia yang penuh kebisingan itu dalam diamnya.
Film ini tayang perdana di Festival Film Telluride pada 30 Agustus 2024, lalu di Toronto pada 6 September 2024. Kemudian, penayangan diperluas sama Sony Pictures Classics mulai 11 Juli 2025.
Wah, bikin penasaran, kan? Sini deh kepoin bareng!
Sekilas tentang Film Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight
Bobo (diperankan Lexi Venter), anak perempuan berusia delapan tahun yang tumbuh di sebuah lahan pertanian Rhodesia di tengah konflik berdarah Zimbabwe War of Independence.
Di mata Bobo, dunia adalah tempat petualangan kecil, misalnya mengendarai motor mini, merokok diam-diam, dan membuat kesal kakaknya, Van (Anina Reed).
Sayangnya memang, dunia yang Bobo huni sebenarnya bukan dunia anak-anak. Ibunya, Nicola (diperankan langsung sama Embeth Davidtz), adalah polisi wanita yang tidur sambil memeluk senapan seperti boneka beruang, dengan pandangan waspada yang nggak pernah surut. Ayahnya, tentara yang sering nggak ada di rumah karena tugas, dan di luar pagar rumah mereka, perang gerilya terus berlangsung, menebar rasa takut yang nggak bisa disembunyikan.
Keadaan dalam film ini terasa ganggu banget, ya?
Review Film Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight
Aku suka bagaimana Embeth Davidtz mengarahkan cerita ini bukan dari perspektif politikus atau prajurit, tapi dari mata anak-anak. Sebab hanya lewat kepolosan seperti itulah kita bisa melihat betapa rusak dunia yang diperbuat orang dewasa.
Bobo bersahabat dengan Sarah (Zikhona Bali), si perempuan kulit hitam yang bekerja di rumah mereka. Di sinilah muncul ironi paling tajam dalam film, yakni kasih sayang dan pengasuhan yang Bobo butuhkan justru datang dari orang yang dianggap ‘lain’ sama ibunya.
Sarah nggak sebatas jadi sosok yang hangat, tapi juga tegas. Dia menyadarkan Bobo bahwa anak-anak kulit hitam yang sering dia suruh-suruh bukanlah pelayan, tapi jelas merupakan anak-anak, teman bermain, dan tentunya manusia.
Bobo mungkin belum mengerti benar konteksnya, tapi matanya mulai terbuka. Dan mungkin, itu langkah pertama dari banyak langkah yang masih harus dia ambil.
Film ini sebagian besar berlatar di lahan pertanian keluarga Fuller dan desa sekitar. Eits, jangan bayangkan ketenangan yang damai. Lahan itu indah dan hijau, tapi juga diselimuti ketegangan. Bisa dibilang, itu tempatnya curiga, trauma, dan tempat Bobo harus nonton TV yang menampilkan kepala tentara Afrika tertembak, ementara pesta dansa orang dewasa terus berlangsung di belakangnya. Asli, aku terpaku di adegan itu, saat Bobo hanya menatap layar tanpa berkata apa-apa. Karena kadang, kesadaran paling besar hadir dalam diam.
Adegan saat Nicola berkata pada Bobo, “Kamu bukan orang Afrika,” dan Bobo menjawab polos, “Karena kulitku nggak hitam?”
Yang kemudian dijawab dengan, “It’s complicated.” Dan itu jadi jantung dari narasi ini. Dan film ini nggak mencoba menyederhanakannya, melainkan membiarkan kompleksitas itu mengendap di pikiranku.
Pada akhirnya, aku nggak akan menyebut film ini nyaman ditonton. Namun, ketika di akhir film Bobo mengenang Sarah dalam benaknya, aku rasa Bobo akan tumbuh jadi seseorang yang berbeda dari orang tuanya. Dan jika itu benar, maka film ini bukan hanya potret masa lalu, tapi juga harapan untuk masa depan. Selamat nonton!