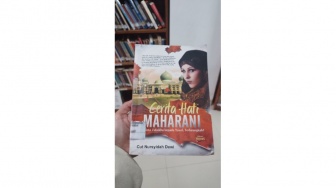The Long Walk merupakan adaptasi dari novel klasik Stephen King yang ditulis dengan nama pena Richard Bachman.
Disutradarai Francis Lawrence dengan naskah garapan JT Mollner, film ini menghadirkan kisah distopia yang kelam, menyoroti sebuah kompetisi jalan kaki mematikan yang digelar oleh rezim totaliter di Amerika Serikat.
Kompetisi itu disebut The Long Walk, sebuah ajang tahunan di mana 50 remaja laki-laki yang dipilih secara acak dari masing-masing negara bagian, dipaksa berjalan tanpa henti di jalan raya dengan kecepatan minimal tiga mil per jam.
Mereka yang melambat, berhenti, atau tak sanggup meneruskan langkah akan mendapat peringatan, dan setelah tiga kali pelanggaran, mereka akan ditembak mati oleh pasukan militer yang mengawal jalannya kompetisi.
Satu orang yang mampu bertahan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dalam jumlah besar serta satu permintaan (wish) apa pun yang akan dikabulkan oleh rezim / pengelola acara. Semua kegiatan ini disiarkan secara langsung ke publik, sebagai tontonan sekaligus propaganda.
Cerita film ini berpusat pada Ray Garraty (Cooper Hoffman), seorang remaja yang memilih ikut dalam perlombaan meski ibunya menentangnya.
Ray memiliki alasan pribadi yang kelam— ia menyaksikan ayahnya ditembak mati oleh The Major (Mark Hamill), figur otoriter yang memimpin ajang tersebut.
Dari trauma itu lahirlah tekad untuk bertahan hidup dan memenangkan kompetisi, agar ia bisa menggunakan "wish" untuk meminta sebuah senapan, yang kelak akan dipakai sebagai sarana membalas dendam kepada The Major.
Di tengah perjalanan panjang dan melelahkan itu, Ray menemukan ikatan emosional dengan Peter McVries (David Jonsson), sesama peserta yang menjadi sahabat sekaligus penopang semangatnya.
Mereka juga bertemu dengan karakter lain seperti Hanks Olson (Ben Wang), Arthur Barker (Tut Nyuot), Billy Stebbins (Garrett Wareing), Thomas Curley (Roman Griffin Davis), dan Gary Barkovitch (Charlie Plummer).
Ketika perjalanan semakin panjang, satu per satu peserta mulai tumbang. Ada yang karena kelelahan, cedera, bahkan ada pula yang memilih untuk menyerah.
Lebih dari tontonan survival, The Long Walk adalah alegori tentang kekuasaan, dehumanisasi, dan gambaran telanjang tentang sistem yang melihat rakyat tak lebih dari pion di tangan penguasa.
Review Film The Long Walk
Francis Lawrence kembali membuktikan kapasitasnya sebagai sutradara yang piawai dalam meramu kisah distopia. Setelah sukses dengan The Hunger Games, kali ini ia membawa novel klasik Stephen King, The Long Walk, ke layar lebar dengan pendekatan yang lebih suram, dan kontemplatif.
Meski premisnya sederhana, Francis Lawrence mengeksekusinya dengan detail yang matang sehingga menghasilkan pengalaman menonton yang intens, sekaligus melelahkan secara emosional.
Perlahan tapi pasti, penonton diajak masuk ke dalam perjalanan panjang yang terasa tanpa ujung. Rasa letih, takut, putus asa, dan cemas yang dirasakan para peserta tergambar begitu nyata, hingga kita seolah ikut menyeret kaki bersama mereka di jalur penuh teror itu.
Brutalitas yang menjadi inti dari cerita juga divisualisasikan dengan cara yang realistis, bahkan tak jarang terasa disturbing. Kita disuguhi bagaimana para peserta ditembak dari jarak dekat, lengkap dengan visual darah yang grafis.
Kematian para peserta juga digambarkan dengan beragam sebab. Ada yang karena kram kaki, ada yang tumbang akibat diare, ada yang mencoba kabur dan langsung ditembak di tempat, lalu ada pula yang memilih menyerah secara sukarela untuk dieksekusi. Salah satu momen paling ngilu bahkan memperlihatkan kaki seorang peserta yang dilindas kendaraan taktis.
Ragam penyebab kematian inilah yang membuat atmosfer film kian mencekam, karena penonton sadar setiap langkah bisa menjadi akhir dari salah satu peserta.
Ketegangan yang dibangun pada level naratif ini kemudian juga diimbangi dengan lapisan teknis yang sama kuatnya.
Sinematografi Jo Willems menghadirkan palet warna redup, lanskap jalan yang tak berkesudahan, serta komposisi gambar yang dingin dan monoton, seolah mencerminkan kondisi batin para peserta.
Detail tambahan seperti bangkai hewan di sisi jalan, kendaraan terbakar, dan rumah-rumah terbengkalai juga semakin mempertebal nuansa distopia yang dingin sekaligus menekan.
Kekuatan film ini juga terletak pada performa aktingnya. Cooper Hoffman sebagai Ray Garraty tampil dengan penuh nuansa emosional, memperlihatkan sisi rapuh sekaligus keras kepala dari seorang anak muda yang punya luka masa lalu.
Di sisi lain, David Jonsson juga mencuri perhatian lewat karakter Pete yang karismatik dan berapi-api, memberi dinamika yang kontras dengan Ray. Chemistry yang terjalin diantara keduanya menjadi salah satu pondasi emosional yang membuat kisah ini tetap hangat di tengah situasi yang penuh keputusasaan.
Menariknya, meskipun The Long Walk dikemas dalam format kompetisi mematikan, nuansa persaingan antar peserta tidak terlalu ditonjolkan.
Francis Lawrence justru lebih menekankan pada solidaritas di antara mereka. Ada banyak momen di mana para peserta saling menopang, memberi semangat, dan tetap memanusiakan satu sama lain meski sadar pada akhirnya hanya ada satu pemenang.
Kehadiran Gary Barkovitch memang menambah dinamika sebagai figur yang kerap mengusik ketenangan peserta lain, tetapi film ini tidak menempatkannya sebagai antagonis mutlak. Sebab di balik sikap provokatifnya, masih ada sisi rapuh dan penyesalan yang diperlihatkan menjelang akhir hidupnya.
Pendekatan ini membuat The Long Walk berbeda dari kebanyakan kisah kompetisi distopia yang biasanya hanya fokus pada adu strategi dan konflik antar individu.
Namun, di balik semua pencapaiannya, film ini masih menyisakan beberapa celah, terutama pada aspek world-building. Latar distopia yang melahirkan ajang “The Long Walk” hanya disinggung sekilas, membuat sebagian penonton, termasuk saya, merasa konteks sosial-politik di balik peristiwa ini masih kurang tergali.
Lalu, dari segi ritme, pacing film juga cenderung tidak merata, ada bagian-bagian yang repetitif sehingga ketegangannya sempat mengendur di titik tertentu.
Selain itu, karakter-karakter pendukung kerap hanya muncul sebatas tempelan, dengan satu atau dua sifat mencolok tanpa pendalaman berarti. Akibatnya, ketika mereka tumbang satu per satu, efek emosional yang ditinggalkan tak selalu kuat.
Secara keseluruhan, The Long Walk bukan sekadar kisah kompetisi mematikan, melainkan potret ketahanan dan solidaritas manusia di tengah situasi ekstrem. Lebih dari itu, film ini juga menyampaikan kritik tajam terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang serta masyarakat yang menjadikan penderitaan sebagai hiburan.
Pada intinya, film ini worth it untuk ditonton, khususnya bagi penonton yang menyukai drama distopia dengan lapisan psikologis mendalam dan atmosfer mencekam. Hanya saja, bagi mereka yang mencari aksi cepat dan bombastis, The Long Walk mungkin terasa terlalu suram dan repetitif.