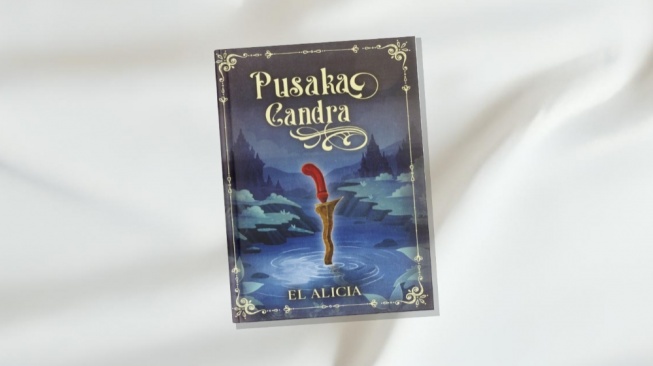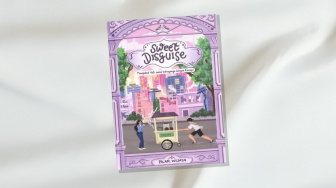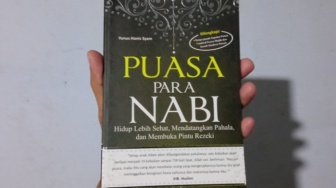Novel Pusaka Candra karya El Alicia menghadirkan sebuah kisah berlatar abad ke-17 di tanah Jawa, ketika kekuasaan kadipaten, pengaruh spiritual, dan dinamika politik berjalan berdampingan.
Penulis membawa pembaca memasuki masa ketika mitos dan kekuasaan saling terkait, dan perempuan—tanpa peduli seberapa kuat mereka—sering kali diposisikan sebagai alat politik. Di sinilah cerita Kirana menemukan tempatnya.
Dikisahkan bahwa masyarakat pesisir percaya pada hari ketika candra—sang rembulan—mencapai titik paling terang dan seimbang dengan aditya, sang matahari. Menurut para tetua, pada hari itu Dewi Ratih turun ke dunia dalam rupa seorang bayi perempuan sebagai berkah bagi tanah tersebut.
Bayi inilah yang dipercaya sebagai Pusaka Candra: perempuan dengan takdir besar, kecantikan memesona, kecerdasan tajam, dan kekuatan spiritual yang menjadikannya rebutan para adipati.
Namun, kepercayaan itu tidak membawa kebebasan. Justru, gelar pusaka membuat perempuan yang memikulnya rentan menjadi objek kekuasaan.
Dalam dialog yang kuat, seorang perempuan pernah berkata, “Kamu tahu apa yang terjadi pada pusaka yang elok di lingkungan keraton? Mereka tidak sekadar diperebutkan. Mereka dimasukkan ke dalam kotak kayu emas seumur hidup—dijadikan pajangan.” Kalimat ini menjadi gambaran jelas tentang bagaimana posisi perempuan dalam politik keraton saat itu: sangat berharga, tetapi tidak berdaya.
Dalam alur utama cerita, kita diperkenalkan kepada Kirana, gadis pantai cerdas dan pemberani yang hidupnya berubah drastis setelah dirinya ditarik masuk ke lingkungan bangsawan.
Awalnya ia diangkat sebagai selir Adipati Pasuruan, tetapi ketika Pasuruan jatuh ke tangan Kadipaten Surabaya, Kirana menjadi bagian dari rombongan yang dibawa sebagai “putri boyongan” ke wilayah baru. Posisi itu kemudian kembali bergeser ketika Prabu Aditya, sang adipati Surabaya yang terkenal kuat dan disegani, memilih Kirana sebagai selirnya.
Perjalanan Kirana dari gadis pesisir menjadi perempuan istana bukanlah kisah naik derajat semata. Ada banyak lapisan intrik, rumor, dan tekanan yang menyertai langkahnya. Sebagian orang percaya bahwa Kirana adalah perwujudan Dewi Ratih, sang Pusaka Candra yang turun ke bumi. Kepercayaan ini menempatkannya pada posisi yang rumit: antara dihormati sebagai berkah dan diperebutkan bagaikan benda sakti.
El Alicia dengan lihai menggambarkan bagaimana Kirana mencoba bertahan di tengah kepungan politik. Ia bukan tokoh yang pasrah, melainkan perempuan dengan harga diri dan keberanian. Meski berada di lingkungan keraton yang penuh aturan, Kirana tidak kehilangan identitasnya sebagai gadis pantai yang terbiasa bersuara dan melindungi dirinya. Karakter ini membuat Kirana mudah disukai—ia bukan sempurna, tetapi berani, realistis, dan cerdas, sehingga pembaca merasakan kedekatan dengannya.
Sementara itu, Prabu Aditya digambarkan sebagai pemimpin kuat dengan sisi lembut yang hanya muncul ketika bersama Kirana. Namun, posisinya sebagai adipati membuatnya tetap terikat tradisi dan politik, termasuk keberadaan selir-selir lain.
Hubungan Kirana dan Prabu Aditya tidak berjalan instan; keduanya masih saling mengukur, meraba batas, dan mencoba memahami satu sama lain. Elemen romansa hadir dengan tipis namun signifikan, memberi ruang bagi perkembangan hubungan yang lebih matang seiring berjalannya cerita.
Dari sisi alur, Pusaka Candra bergerak menggunakan pola maju yang cenderung cepat. Pembaca dibawa mengikuti perpindahan Kirana, perubahan kekuasaan, hingga teka-teki seputar identitas Pusaka Candra tanpa terseret bagian-bagian yang bertele-tele. Gaya bertutur El Alicia tetap konsisten: detail historis digambarkan secukupnya, tidak membebani pembaca, namun tetap memberikan atmosfer kuat tentang zaman yang penuh tradisi dan hirarki sosial tersebut.
Narasi novel ini terasa hidup karena penulis mampu menyeimbangkan antara penjelasan sejarah, konflik, dan adegan emosional. Deskripsi lingkungan pesisir, suasana keraton, serta dinamika para selir membuat latarnya terasa nyata. Pembaca bisa membayangkan bentuk bangunan, aroma pantai, hingga ketegangan di ruang-ruang istana. Inilah salah satu kekuatan khas El Alicia—kemampuannya menciptakan dunia yang meyakinkan tanpa perlu menjejali pembaca dengan detail berlebihan.
Dari sisi tokoh pendukung, meski tidak semua langsung diperkenalkan secara mendalam, kehadiran mereka memberi warna pada perjalanan Kirana. Ada pelayan keraton yang penuh bisik-bisik, adipati lain yang menyimpan ambisi, serta selir-selir yang melihat Kirana sebagai ancaman maupun sekutu. Keseluruhan dinamika ini membuat cerita tidak hanya bernuansa romansa, tetapi juga bernuansa politik, spiritual, dan sosial.
Aspek mitologi dan kepercayaan masyarakat yang diselipkan dalam cerita menambah daya tarik tersendiri. Pertanyaan mengenai apakah Kirana benar-benar Pusaka Candra atau hanya korban takhayul politik menjadi salah satu elemen misteri yang mendorong pembaca untuk terus mengikuti alurnya.
Kepercayaan pada Dewi Ratih serta ramalan-ramalan yang berkembang di tengah masyarakat menciptakan lapisan magis yang memperkuat atmosfer sejarahnya.
Secara keseluruhan, Pusaka Candra adalah novel yang menggabungkan kisah sejarah, romansa, dan intrik dengan sangat halus. Tidak hanya menampilkan kekuatan perempuan di tengah sistem yang mengekang, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah identitas bisa diperebutkan, dimitoskan, dan diberi makna sesuai kepentingan politik.
Menurut saya, kekuatan terbesar novel ini ada pada penggambaran Kirana yang begitu manusiawi dan kokoh, serta dunia abad ke-17 yang terasa hidup tanpa kehilangan sentuhan magisnya.
Kisahnya mengalir nyaman, plotnya menarik, dan romansa di dalamnya terasa tulus sekaligus masuk akal. Novel ini cocok untuk pembaca yang suka cerita sejarah dengan sentuhan mitologi dan dinamika hubungan yang hangat namun tidak berlebihan.
Jika kamu mencari cerita tentang perempuan yang berjuang menemukan tempatnya di tengah badai kekuasaan, Pusaka Candra adalah pilihan yang sangat layak dibaca.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS