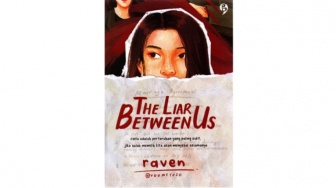Siapa sangka, semangkuk mie ayam yang sederhana, kuah bening, suwiran seadanya, dan aroma jalanan kota, dapat berubah menjadi simbol eksistensial antara hidup dan mati? Dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Khrisna, makanan yang begitu akrab itu menjadi jeda terakhir tokohnya sebelum mengambil keputusan terbesar dalam hidup. Bertahan atau menyerah.
Novel ini berangkat dari kisah nyata sejumlah penyintas depresi akut (DSS) yang diwawancarai oleh penulis. Melalui pengalaman beberapa orang itu, Bryan menyusun fragmen cerita Ale, sang tokoh utama, seorang laki-laki yang tenggelam dalam rasa hampa, kesepian, dan pertanyaan-pertanyaan tentang arti keberadaannya.
Rasa tidak percaya dirinya yang telah mengakar terlalu dalam, membuatnya selalu merasa tidak beruntung di segala hal, baik terhadap kemampuan interpersonalnya, fisiknya, dan hal-hal kecil yang membuat ia merasa selalu menjadi manusia tersial dan gagal di muka Bumi, menjadi penyebab si tokoh utama merasa dunia tidak pernah memihak padanya.
Tidak ada alur dramatis penuh plot twist. Yang ada adalah perjalanan batin yang sunyi, potret seseorang yang ingin hilang dari dunia tanpa menimbulkan kegaduhan. Salah satu aspek literer yang menonjol adalah pilihan struktur narasi berupa potongan-potongan pengalaman. Alih-alih menghadirkan kronologi rapi, novel ini mengalir seperti ingatan yang tidak pernah linear. Teknik ini memperlihatkan bagaimana depresi bekerja, hadir dalam retakan kecil, menyelinap diam-diam di sela rutinitas paling biasa.
Bahasa Bryan terasa cair, tanpa jargon medis, namun tetap tak kehilangan kedalaman emosionalnya. Justru dari kesederhanaan itulah rasa sakit menjadi dekat. Bukan sebagai konsep psikologis, melainkan pengalaman sehari-hari. Pembaca tidak diajak mengasihani Ale, melainkan memahami bagaimana seseorang bisa terus bernafas meski merasa tidak sanggup hidup.
Mie ayam sebagai metafora pun bekerja efektif. Ia menegaskan bahwa keinginan untuk mati tidak selalu hadir lewat adegan melodramatis, terkadang ia muncul saat kita sedang makan, bekerja, atau tertawa bersama teman. Sesuatu yang banal, tetapi menghantui.
Empati Tanpa Dramatisasi
Novel ini berhasil melakukan dua hal yang sulit dicapai sekaligus. Pertama berhasil menghadirkan empati tanpa dramatisasi. Kedua, mampu mengajak pembaca bercermin tanpa menggurui.
Ada momen-momen yang begitu akrab hingga saya pun harus berhenti sejenak. Perasaan tak layak hidup, kecanggungan sederhana si tokoh utama yang digambarkan selalu menunduk untuk menghindari kontak mata dengan orang lain, hingga kecemasan yang tampak remeh namun melumpuhkan. Semuanya digambarkan tanpa pretensi puitik yang berlebihan.
Novel ini membuka percakapan tentang kesehatan mental tanpa kampanye formal nan kaku. Ia mengajak pembaca untuk mengakui keberadaan luka yang sering disembunyikan rapat-rapat. Dalam diam, ia berkata, “Kamu tidak sendirian.”
Sikap Anti-Romantisasi Luka
Banyak karya yang menjadikan depresi sebagai estetika tragedy. Bryan justru berjalan ke arah sebaliknya. Ia tidak memuja luka sebagai sumber romantika hidup, tidak pula menampilkan kematian sebagai solusi heroik. Depresi ditunjukkan sebagai sesuatu yang getir, melelahkan, tetapi nyata.
Kejujuran inilah yang terasa penting dalam konteks Indonesia, di mana depresi masih dianggap kurang iman atau kurang bersyukur. Novel ini meruntuhkan stigma itu melalui cerita, bukan ceramah. Sekecil apapun tindakan kita, bisa memicu trauma terpendam. Bahkan yang mungkin tidak kita sadari sekalipun.
Depresi dan Ruang Validasi
Namun, justru karena kesederhanaannya, ada beberapa bagian yang terasa terlalu ringkas. Perjalanan Ale kembali menjalani hidup setelah keterpurukan digambarkan dengan cepat, hampir seperti lompatan emosional yang belum selesai diproses.
Padahal, fase bangkit sama pentingnya dengan fase jatuh. Penulis seperti nampak terburu-buru menyelesaikan bagian akhir, sehingga masih terdapat bagian-bagian terasa kosong. Bagaimana tempat ia bekerja dan orang-orangnya menerima ia Kembali setelah menghilang tanpa kabar, tidak dijelaskan dengan tuntas.
Karakter “malaikat penolong” yang muncul sebagai pemberi perspektif baru pun tidak dieksplorasi lebih dalam. Tokoh tersebut berpotensi menjadi penyeimbang naratif bagi Ale, representasi harapan yang lebih konkret. Tetapi ia dibiarkan menggantung, hanya menjadi fungsi cerita, bukan sosok yang memiliki lapisan-lapisan sendiri.
Di sisi lain, keberanian novel ini dalam menyuarakan depresi juga membawa risiko. Ia rawan menjadi ruang validasi yang terlalu nyaman tanpa memberi arah pemahaman lebih luas tentang akses bantuan, terapi, atau support system yang nyata. Mungkin buku ini memang tidak diniatkan ke sana, tetapi ketidakhadirannya tetap terasa.
Afirmasi Pelan dari Penulis
Meski memiliki beberapa ruang yang bisa diperkaya, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati tetap menjadi karya penting yang menempatkan isu kesehatan mental dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Tidak ada solusi ajaib di sini, tetapi ada ruang aman untuk merasa dimengerti. Ada afirmasi pelan yang berbisik dari penulis buku ini bahwa keberanian bisa sesederhana mengakui perasaan sendiri.
Menutup novel ini, saya merasakan sensasi yang mirip setelah menikmati semangkuk mie ayam, tidak sepenuhnya kenyang, tetapi cukup untuk membuat saya melangkah lagi. Hidup, betapapun pahit dan hambarnya, tetap harus ditelan. Suap demi suap. Hari demi hari. Akhirnya, novel ini bukan sekadar cerita tentang ingin mati, melainkan tentang manusia yang tetap memilih bertahan, meski hanya dengan kekuatan kecil untuk hidup sedikit lebih lama dari kemarin.