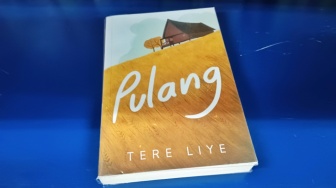Beberapa tahun lalu, saya, bapak, dan adik pernah salat Jumat di Masjid Istiqlal. Saya tak lagi ingat persis kapan itu terjadi. Namun satu hal saya ingat betul Masjid Istiqlal yang saya datangi saat itu terasa sangat berbeda dengan Masjid Istiqlal yang saya kunjungi dua bulan lalu.
Ya, pada November 2025, saya kembali ke Masjid Istiqlal. Sejak kunjungan itu, saya ingin kembali salat Jumat di sana jika ada kesempatan. Alasannya banyak.
Sejujurnya, saya sempat bingung harus mulai dari bagian mana untuk menceritakan perbedaan pengalaman salat Jumat di Istiqlal beberapa tahun lalu dengan yang saya rasakan sekarang. Namun, mari kita mulai dari hal paling sederhana transportasi.
Dulu, parkiran Masjid Istiqlal hampir selalu penuh. Akses Transjakarta juga belum semudah sekarang. Karena itu, bapak mengajak saya dan adik berangkat sejak pukul 10.30 WIB, sekitar satu setengah jam sebelum salat Jumat—menggunakan mobil pribadi demi menghindari macet di kawasan Jakarta Pusat.
Kini ceritanya berbeda. Dengan Transjakarta, saya bisa sampai ke Masjid Istiqlal hanya dalam waktu sekitar satu jam. Dari Halte Pulogadung, saya cukup menaiki Transjakarta Koridor 2 dan turun tak jauh dari masjid.
Perubahan itu belum seberapa. Masjid Istiqlal kini memiliki berbagai fasilitas penunjang yang dulu tak pernah saya lihat. Di dekat gerbang, misalnya, berdiri Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta.
Terowongan ini bukan sekadar baru bagi saya. Ia pernah dilewati Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Dikutip dari Detik, Paus Fransiskus melintasi terowongan ini bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan menyebutnya sebagai simbol penguatan persaudaraan antarumat beragama di Indonesia. Singkatnya, Terowongan Silaturahim terasa istimewa karena menjadi simbol kerukunan Islam dan Kristen di negeri ini.
Saya juga ingat betul perubahan pada sistem penitipan sandal. Meski lantainya bisa terasa panas saat terik, area penitipan kini luas dan tertata rapi. Di setiap titik, ada dua petugas yang menjaga sandal jamaah sekaligus memberikan kartu penitipan.
Di sekitar masjid, warung-warung makan tampak lebih tertib. Memang, kadang ada meja yang belum sempat dirapikan karena ramainya pengunjung. Namun sebagian besar meja berbahan besi dan terlihat bersih. Menu yang dijajakan sederhana dan terjangkau: nasi dengan lauk rumahan seperti ayam goreng, mi instan, serta jajanan ringan seperti es teh manis dan sosis tusuk.
Kemegahan Masjid Istiqlal baru benar-benar terasa ketika melangkah masuk ke dalam. Pintu masuk dan penanda arahnya kini menyerupai bandara, lengkap dengan pemeriksaan keamanan dan tangga menuju ruang utama masjid. Karena ukurannya yang besar, saya bahkan melihat beberapa turis asing datang, mengamati sekeliling, lalu berkata akan kembali setelah salat Jumat selesai.
Sebelum menaiki tangga, di sisi kiri terdapat area wudhu yang luas. Desainnya unik: lima keran melingkar pada satu tiang, lengkap dengan alas untuk meletakkan barang. Bagi jamaah yang terbiasa dengan model konvensional, tersedia pula keran berjajar pada pilar panjang.
Di area wudhu ini, kini terdapat vending machine minuman dan loker penyimpanan. Tak jauh dari sana, saya melihat dua kursi pijat otomatis. Tinggal memasukkan uang, lalu pijatan berlangsung selama beberapa menit, sesuatu yang dulu tak pernah saya bayangkan ada di dalam kompleks masjid.
Masih di lantai satu, terdapat ruang tanya jawab seputar Islam dan area yang menyerupai pesantren. Kursi-kursinya terbuat dari bambu, dipenuhi tanaman hias yang memberi kesan sejuk. Ruang pesantrennya memang tampak sepi saat itu, tetapi luasnya menunjukkan tempat ini dirancang untuk kegiatan belajar yang serius.
Saat naik ke lantai dua, barulah saya benar-benar menyadari betapa masifnya masjid rancangan Friedrich Silaban ini. Masjid Istiqlal telah direnovasi sejak era Presiden Joko Widodo dengan anggaran Rp475 miliar. Mengutip situs resmi Presiden Republik Indonesia, renovasi mencakup pembenahan interior dan eksterior serta pembangunan parkir bawah tanah dua tingkat dengan kapasitas 745 kendaraan.
Saking luasnya, arus jamaah tampak seperti lautan manusia. Di sela-selanya, pedagang parfum dan kalender berjalan beriringan. Begitu masuk ke ruang utama, kemegahan lama masih terasa kuat.
Namun ada tiga pembaruan yang langsung mencuri perhatian: kipas angin raksasa, layar proyektor jumbo yang menampilkan imam dan khatib, serta layanan penerjemah bahasa isyarat bagi jamaah tunarungu. Saat khatib menyampaikan khutbah tentang syukur atas nikmat Allah, seorang penerjemah berjas hitam berdiri di depan, menerjemahkan setiap kalimat dengan bahasa isyarat yang lugas dan penuh konsentrasi.
Kipas-kipas besar membuat ruangan sejuk tanpa terasa dingin berlebihan. Nyaman. Tenang. Saya tidak berkeringat, tetapi juga tidak menggigil.
Usai salat, saya pulang menggunakan Transjakarta. Di pintu keluar masjid, pedagang sudah berjejer. Dari kerak telor hingga suvenir Jakarta, semuanya ada: kaus, miniatur Monas, hingga mainan mobil kayu.
Saya tersenyum. Dan berharap bisa kembali salat Jumat di sana—sekalian makan kerak telor.
Ah, saya berharap bisa salat jumat lagi di sana dan makan kerak telor. Masjid Istiqlal yang sekarang, bagi saya, jauh lebih nyaman dan mewah. Sesekali, cobalah salat jumat di sana.