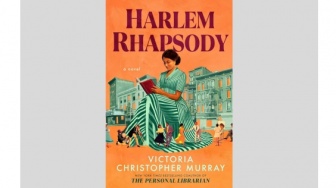Setiap pagi, taman kota itu selalu ramai oleh suara air. Selang-selang panjang meliuk di antara bunga mawar, anggrek, dan tulip yang ditanam rapi dalam barisan. Air jatuh perlahan, membasahi tanah, menyentuh daun, dan membuat kelopak-kelopak itu berkilau seolah baru saja menangis bahagia.
Para tukang kebun berjalan dengan langkah teratur, memeriksa daun yang layu, memangkas yang tumbuh tak beraturan, lalu tersenyum puas ketika melihat taman tampak indah seperti yang diharapkan.
Tak jauh dari situ, hanya beberapa langkah dari bangku taman dan trotoar batu abu-abu, ada satu hal yang tak pernah mereka perhatikan. Sehelai rumput kecil. Ia tumbuh di celah sempit antara dua batu trotoar. Tanahnya keras, retak, dan nyaris tak menyisakan ruang bernapas.
Tak ada papan nama, tak ada pot, tak ada pagar kecil yang melindunginya. Orang-orang yang lewat bahkan tak sadar mereka menginjaknya setiap hari. Rumput itu tahu, ia berbeda.
Ia bukan bunga yang ditanam dengan rencana. Ia tidak dipilih. Tidak dipuji. Tidak pernah disiram dengan sengaja. Air yang ia dapat hanyalah sisa tetes hujan yang kebetulan jatuh miring, atau percikan kecil dari selang yang tak sengaja mengarah ke trotoar.
Namun setiap pagi, ia tetap bangun. Bukan karena berharap diperhatikan, tapi karena hidup, entah bagaimana caranya, masih melekat di dalam akarnya.
Rumput itu sering melihat bunga-bunga di taman. Ia melihat bagaimana mereka tumbuh dengan percaya diri, bagaimana kelopak mereka dibersihkan, bagaimana orang-orang berhenti untuk memotret dan mengagumi warna mereka.
“Indah sekali,” kata manusia-manusia itu.
Tak ada yang pernah mengatakan hal serupa tentangnya. Jika ada yang menoleh, biasanya hanya untuk mengernyit.
“Rumput liar,” gumam seseorang.
“Merusak pemandangan,” sahut yang lain.
“Hama”
Suatu hari, seorang petugas taman berhenti tepat di depannya. Sepatu besar itu berdiri begitu dekat, membuat bayangannya menutup cahaya matahari yang biasa ia tunggu.
Rumput itu menahan napas jika ia bisa. Petugas itu menunduk sebentar, lalu melangkah pergi. Ia tidak dicabut, tapi juga tidak dianggap ada. Lebih menyakitkan dari dibuang adalah tidak diakui.
Hari demi hari, musim berganti. Matahari kadang terik tanpa ampun, membuat trotoar memanas hingga rumput itu nyaris kering. Akarnya menembus lebih dalam, mencari sisa kelembapan yang tersisa. Setiap kali hampir menyerah, hujan datang tidak lama, tidak deras, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa dunia belum sepenuhnya melupakannya.
Ia belajar sesuatu tentang bertahan.
Bertahan bukan tentang tumbuh tinggi. Bukan tentang menjadi indah. Bertahan adalah tentang tetap hidup meski tak ada yang memberi alasan.
Suatu sore, seorang anak kecil duduk di bangku taman sambil mengayunkan kakinya. Ia bosan menunggu ibunya yang sedang berbincang. Pandangannya jatuh ke trotoar, ke celah batu tempat rumput kecil itu tumbuh.
“Hah,” gumam anak itu pelan.
Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat rumput itu bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai sesuatu yang ada.
“Kok kamu bisa tumbuh di situ?” tanyanya polos, tentu saja tanpa jawaban.
Jarinya hampir menyentuh, lalu ragu. Anak itu menarik tangannya kembali, seolah takut merusaknya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berdiri dan pergi.
Rumput itu tidak tahu apa arti senyum itu, tapi hari itu terasa lebih hangat.
Tak lama setelah itu, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Taman tetap disiram, bunga tetap dijaga, tapi celah trotoar semakin kering. Rumput kecil itu mulai menguning di ujung-ujungnya. Setiap pijakan kaki terasa lebih berat. Setiap hari adalah pertanyaan yang sama, apakah hari ini aku masih bisa bertahan?
Di malam hari, ketika taman sunyi, rumput itu memandang langit yang hanya bisa ia lihat sebagian. Bintang-bintang tampak jauh dan acuh, tapi tetap ada.
“Aku tidak pernah meminta banyak,” jika ia bisa bicara, mungkin ia akan berkata begitu. “Aku hanya ingin tetap hidup.”
Suatu pagi, badai datang. Hujan turun deras, lebih deras dari biasanya. Air mengalir di sepanjang trotoar, meresap ke celah-celah batu. Tanah di sekitar rumput kecil itu akhirnya benar-benar basah. Akarnya minum lebih banyak dari yang pernah ia rasakan.
Dan sesuatu berubah. Bukan pada bentuknya. Bukan pada warnanya. Tapi pada keteguhannya.
Hari-hari berikutnya, ketika matahari kembali terik, rumput itu masih ada. Hijau tipis, sederhana, tapi hidup. Trotoar tetap diinjak, taman tetap ramai, dan bunga tetap dipuji.
Namun tanpa disadari siapa pun, rumput kecil itu menahan tanah agar tidak semakin retak. Akarnya mengikat debu agar tidak mudah terbawa angin. Ketika hujan turun lagi, air tidak langsung hanyut, melainkan terserap sedikit demi sedikit.
Ia tidak mencolok. Tapi ia berguna.
Beberapa bulan kemudian, seorang petugas baru datang. Ia melihat trotoar itu, lalu berhenti. “Aneh,” gumamnya. “Bagian sini nggak gampang retak.”
Ia tidak tahu alasannya. Ia juga tidak mencari tahu. Rumput kecil itu tetap tumbuh di sana
Tak pernah disiram.
Tak pernah dipuji.
Tak pernah dipilih.
Namun ia tetap hidup dan mungkin, justru di situlah nilainya. Bahwa tidak semua yang berharga berdiri di tengah taman. Ada yang tumbuh di celah sempit, dalam diam, menahan dunia agar tidak runtuh sedikit demi sedikit.
Rumput itu tidak pernah menjadi bunga dan ia tidak perlu. Karena bertahan tanpa perhatian bukan berarti tidak berharga kadang, itu adalah bentuk keberanian yang paling jujur.