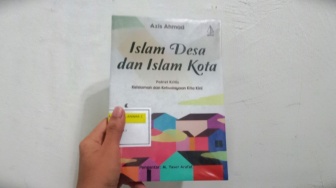Tengah malam itu menjadi titik balik dalam hidupku, saat aku menyadari bahwa maut bisa saja menjemput di jalur yang salah. Kejadiannya berlangsung musim hujan lalu, ketika langit mendung tanpa bintang sedikit pun.
Aku dan sahabatku, Bono, baru saja selesai membantu dekorasi acara nikahan teman di pelosok kabupaten. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan angka dua pagi, dan kesadaran kami mulai memudar akibat kantuk yang luar biasa.
"Jangan pernah melintasi rel tua itu saat lonceng tidak berbunyi," begitu peringatan warga pasar kepada kami para pendatang.
Meski jalur tanah merah itu dicap keramat oleh masyarakat setempat dan jarang dilalui kendaraan, kami justru nekat mengambil jalan di pinggir rel sambil menembus ilalang tinggi. Rasa lelah dan keinginan untuk segera merebahkan diri di kasur akhirnya membuat kami menantang logika serta mengabaikan semua peringatan itu.
Begitu roda motor kami menggilas kerikil rel, atmosfer mendadak mencekam. Udara menjadi sangat lembap dan berat, membatasi oksigen yang masuk ke paru-paru.
Lampu depan motor kami seolah redup, hanya mampu menerangi bayangan hitam yang menari di depan mata. Semak belukar di sisi kiri-kanan tampak bergoyang liar, meskipun tidak ada angin bertiup, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengintai.
Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah titik yang sering dibicarakan para tukang ojek: Perlintasan Mati. Perlintasan itu tanpa palang, hanya berupa potongan rel berkarat yang terhimpit pohon beringin raksasa.
Di bawah rel tersebut terdapat parit berlumpur yang mengeluarkan bau bangkai sangat tajam. Konon, area itu menuntut tumbal bagi siapa pun yang melintas tanpa permisi.
Begitu mesin motor kami berada tepat di tengah rel, suasananya mendadak senyap secara total. Bukan senyap yang menenangkan, melainkan senyap yang memekakkan telinga.
Mesin motor tiba-tiba mati total, membuat nyali kami menciut seketika. Di sanalah, di balik kabut tipis dan bayangan beringin, kengerian itu mewujud nyata.
Di balik batang beringin muncul seorang pria mengenakan seragam masinis lusuh, dengan kain yang tampak koyak akibat gesekan aspal.
Topinya compang-camping menutupi wajahnya yang pucat pasi. Awalnya kami berharap itu hanya orang gila yang tersesat. Namun napas kami tertahan saat melihat tubuhnya tembus pandang oleh sorot senter. Dia berdiri tegak, tak bergerak, mengerikan.
Langkah kaki kami semakin berat saat kita mendekati masinis itu yang berdiri mematung di kegelapan. Jantung kami seolah berhenti berdetak ketika sosoknya terlihat jelas, namun kerongkongan kami terasa tersumbat pasir hingga tak ada teriakan yang mampu keluar.
Tiba-tiba, meski pria itu tetap diam tanpa ekspresi, sebuah suara parau terdengar menggema langsung di dalam kepala kami berdua: ''Tolong… sambungkan kakiku…''.
Aku melihat dengan jelas bahwa bagian bawah tubuhnya hancur berantakan, menyisakan serpihan tulang yang menonjol keluar. Bau darah segar dan karat besi seketika menusuk indra penciuman kami. Kami melihat wajahnya, matanya putih semua tanpa pupil. Dia memaksa kami turun, menyuruh kami mencari potongan kakinya yang hilang di parit itu.
Aku tercekat, mematung di tempat dengan kaki yang terasa seberat timah. Nama Bono kupanggil berulang kali dalam bisikan panik, namun tidak ada sahutan. Saat aku menoleh ke belakang dengan harapan menemukan pundak kawanku itu, yang kulihat hanyalah kegelapan ilalang yang bergoyang.
Aku baru menyadari bahwa pengecut itu sudah lebih dulu lari tunggang langgang, meninggalkanku sendirian di hadapan kengerian ini. Jauh di ujung jalan setapak, suara deru mesin motor yang dinyalakan secara paksa memecah kesunyian, menandakan Bono sudah bersiap memacu kendaraannya.
"Tolong... sakit..."
Suara itu kembali berdenging, kali ini lebih nyaring hingga membuat telingaku berdenyut. Aku terpaksa kembali menatap ke depan. Pria itu, sang masinis, kini mulai menunduk perlahan. Gerakannya patah-patah seperti engsel pintu yang karatan.
Di bawah sorot lampu motor yang sayup-sayup dari kejauhan, aku melihat dengan jelas bahwa di bawah celana seragamnya hanya ada tulang putih yang mencuat, terputus rapi seolah habis tergilas roda besi. Tidak ada telapak kakinya.
Lampu motor Bono menyorot ke arahku sesaat sebelum ia memutar arah. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat potongan-potongan daging dan tulang berserakan di sepanjang rel, bergerak-gerak kecil seolah mencoba merayap mendekati tubuh induknya.
Nyaliku habis. Tanpa memikirkan lagi harga diri, aku memutar badan dan berlari sekuat tenaga menembus ilalang tajam yang menyayat kulit.
Aku tidak peduli pada luka-luka itu; aku hanya ingin mencapai motor sebelum Bono benar-benar menarik gasnya. Di belakangku, suara decitan logam yang beradu dengan batu rel terdengar mengejar—srek... srek... srek—seperti sesuatu yang berat sedang diseret dengan kecepatan yang tidak wajar.
"BONO! JANGAN TINGGALKAN AKU!" teriakku pecah, saat tanganku berhasil menggapai ujung behel motor tepat ketika Bono hendak meluncur pergi.
Tenagaku nyaris habis, dan dalam situasi hidup mati ini, hanya umpatan yang keluar dari mulutku. Aku mencoba menenangkan diri, memejamkan mata, dan merapal doa sekenanya sebelum akhirnya menendang pedal starter motor sekuat tenaga.
Mesin motor menyala dengan suara menggelegar. Kami melesat meninggalkan rel tersebut secepat mungkin. Aku merasakan embusan angin yang sangat dingin di tengkuk, seolah ada jari-jari besi yang nyaris menyentuh kulit leherku. Suara jeritan pilu terdengar di belakang, membuat seluruh badan kami merinding. Kami tidak berani menoleh sedikit pun.
Begitu kami menjauh dari rel dan masuk ke jalan aspal utama, mesin motor kembali lancar. Kami terus memacu kendaraan sampai menemukan pos ronda yang masih terjaga. Sesampainya di pos ronda dengan napas yang masih tersengal, kami langsung dicecar berbagai pertanyaan oleh para penjaga. Namun, mereka hanya mengangguk pelan saat mendengar pengalaman mengerikan kami.
Menurut cerita mereka, masinis itu adalah korban kecelakaan kereta puluhan tahun silam yang jasadnya hancur dan tidak pernah ditemukan secara utuh. Tak hanya sosok masinis, mereka juga berujar bahwa di rel tua itu sering terdengar suara rintihan minta tolong—terkadang suara anak kecil, kadang perempuan—yang diduga merupakan arwah korban kecelakaan kereta api lainnya yang pernah terjadi di sana.
Lalu bagaimana dengan orang lain?" tanyaku dengan suara yang masih bergetar. "Apakah semua orang yang melintas di sana seselamat kita?"
Salah satu penjaga tertua mengisap rokok lintingannya dalam-dalam, asapnya mengepul perlahan menembus remang lampu pos ronda. Ia menatap ke arah kegelapan rel yang baru saja kami lalui sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat.
"Selamat atau tidaknya itu tergantung seberapa cepat mereka lari, atau seberapa kuat jantung mereka bertahan," ujarnya tenang. Tidak semua orang beruntung bisa sampai ke pos ini dalam keadaan bernapas. Ada yang ditemukan kaku keesokan harinya di pinggir rel, tanpa luka luar, tapi matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Warga di sini percaya, mereka yang 'diambil' adalah mereka yang melintas tepat saat sang masinis berhasil menemukan potongan bagian tubuhnya yang hilang.
Ia kemudian menunjuk ke arah motor kami yang masih terparkir. "Kalian selamat karena kalian datang berdua. Penunggu di sana lebih suka mengincar mereka yang sendirian, yang lamunannya kosong. Tapi, ingat satu hal..."
Beliau menjeda kalimatnya, membuat suasana semakin mencekam. "Siapa pun yang sudah bicara atau mendengar suara mereka, biasanya akan 'ditandai'. Mereka tidak akan berhenti menghantui sebelum kalian memberikan apa yang mereka minta."
Mendengar itu, aku dan Bono saling pandang. Aku teringat tangan Bono yang tadi sempat menyentuh sesuatu yang dingin di ilalang, dan aku teringat suara parau yang menggema tepat di batok kepalaku sendiri. Rasa lega karena sampai di pos ronda tiba-tiba sirna, berganti dengan ketakutan baru yang lebih dingin.
"Maksud Kakek... dia bisa mengikuti kami sampai ke rumah?" bisik Bono nyaris tak terdengar.
Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah langit-langit pos ronda. Tiba-tiba, dari arah kejauhan—sangat jauh namun terdengar sangat jelas—terdengar bunyi lonceng yang berayun pelan sekali. Padahal, warga pasar bilang jangan melintas jika lonceng tidak berbunyi. Tapi malam ini, lonceng itu berbunyi justru saat tidak ada kereta yang lewat.