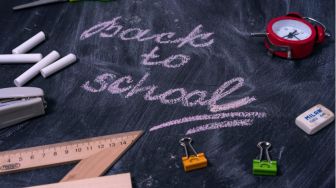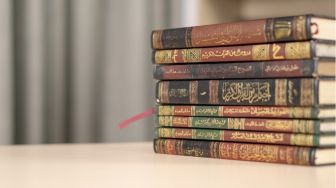Pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, para pemuda dan pemudi dari berbagai daerah berkumpul untuk mengucapkan sebuah ikrar. Ikrar tersebut masyhur dikenal dengan Sumpah Pemuda.
Pengikraran Sumpah Pemuda tentu bukan tanpa alasan. Sumpah Pemuda lahir karena didorong oleh rasa kesadaran akan kemajemukan yang dimiliki Indonesia, yang mana berpotensi memicu perpecahan bila tak disikapi secara tepat. Oleh sebab itu, esensi dari Sumpah Pemuda adalah integrasi, baik itu dari sisi tanah air, bangsa, maupun bahasa.
Dua hal yang disebutkan di awal yakni tanah air dan bangsa cukup mudah untuk dibungkus dalam rasa persatuan. Namun, lain halnya dengan bahasa. Ternyata membuat Indonesia bersatu dalam hal bahasa adalah hal yang cukup sulit.
Saat itu, tahun 1930-an hingga 1950-an, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap penjajah. Sebab, pada masa itu bahasa Belanda menjadi bahasa yang sangat dominan di Indonesia. Tak sedikit rakyat Indonesia yang lumayan kesulitan menuturkan bahasa Indonesia, misalnya Maria Ullfah, Soegiarti, dan Kajatoen Wasito.
Tahun 1931, selepas menyelesaikan kuliahnya di Universiteit Leiden (Belanda), Maria Ullfah berupaya keras mencari orang yang bisa mengajarinya berbahasa Indonesia. Satu tahun sebelumnya, pada 1930, kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) di Surabaya menghasilkan keputusan yang mewajibkan terbitan Isteri menggunakan bahasa Indonesia.
Kini, penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi telah dikukuhkan oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana dengan realita yang terjadi selama ini?
Disadari atau tidak, faktanya bahasa Indonesia masih terkesan dianaktirikan. Kita semua ‘lebih suka’ menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya dalam percakapan, melainkan juga dalam penamaan gedung-gedung dan badan usaha.
Entah bagaimana awal mulanya, menggunakan bahasa asing terkesan lebih gengsi-able daripada bahasa sendiri. Para akademisi dan pejabat pun banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dengan bumbu bahasa asing ketika menyampaikan pidato atau mengajar.
Fenomena tersebut lantas melahirkan reaksi sinis terhadap orang yang berucap, “kalau bicara jangan dicampur-campur istilah asing, bikin bingung”. Tak hanya itu, sinisme juga terjadi pada orang yang berbicara pakai bahasa Indonesia sesuai kaidah baik dan benar.
Bukankah itu merupakan hal yang tak adil? Kita melarang orang tidak suka terhadap gaya bicara bercampur bahasa asing dengan dalih belajar. Namun, kita sendiri mengejek orang yang belajar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Melihat apa yang terjadi, sepertinya bisa dipahami bahwa kita telah satu tumpah darah dan satu bangsa. Hanya saja, kita belum satu bahasa. Mungkin kita menganggap bahwa bahasa Indonesia itu terkesan jauh dari “menjanjikan akan kemajuan”. Padahal, justru dengan bahasa Indonesia kita bisa meluruhkan perbedaan makna kata dalam masing-masing bahasa daerah.
Contoh, kata amis dalam bahasa Jawa bermakna ‘bau anyir’. Namun, dalam bahasa Sunda maknanya adalah ‘manis’. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran bahasa Indonesia menjadi pemersatu komunikasi.
Posisi bahasa Indonesia saat ini menjadi begitu dilema. Kita menginginkan bahasa Indonesia mampu merekam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Tapi, di sisi lain kita justru lebih mengapresiasi bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) sebagai simbol modernisasi.
Memang benar tak ada yang salah dengan belajar bahasa asing. Malahan hal tersebut bisa dibilang bagus. Namun, akan menjadi hal yang patut dipertanyakan ketika kita lebih bangga berbahasa asing ketimbang berbahasa Indonesia. Ini tak beda jauh dengan menghilangkan secara sengaja citra dan identitas bangsa yang sebenarnya.
Ketika kita lebih bangga berbahasa asing, hal tersebut akan memberi efek pada realitas sosial. Orang akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Padahal, dahulu para pejuang berupaya keras agar bisa berbahasa Indonesia untuk mendobrak dominasi bahasa Belanda.
Bagaimana pun, upaya para pemuda dalam mengikrarkan Sumpah Pemuda harus kita apresiasi. Bukan semata melalui ‘perang ucapan selamat’ melalui pamflet, tapi juga dengan mengejawantahkan isi Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin kita bisa memulainya dengan Gernas BBI. Ini bukan Gernas BBI versi Luhut Binsar Panjaitan. Ini Gernas BBI versi kita sendiri dalam upaya mengapresiasi Sumpah Pemuda. Ya, Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Berbahasa Indonesia. Semoga suatu saat, bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa Internasional yang diakui banyak negara.