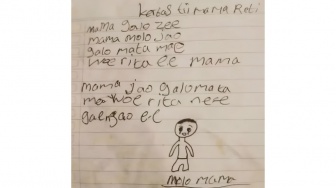Salah satu anugerah terbesar saat saya tugas belajar kembali adalah adanya program magang. Program magang tersebut memperbolehkan mahasiswa untuk magang di mana saja asal instansi yang dituju menyetujui. Kebetulan, saya pragmatis-oportunis.
Jelas saya memilih untuk magang di Ketapang tercinta, sejenak melepaskan diri dari hiruk pikuk dan suramnya Tangerang Selatan, lokasi kampus saya yang mungkin tidak perlu disebutkan namanya tapi pembaca sekalian sudah tahu kampusnya. Dua bulan bisa memeluk orang tua sepulang kerja (dan biaya hidup gratis). A great idea, isn’t it?
Anugerah tersebut disertai anugerah lainnya. Kepulangan saya ke Ketapang selama bulan September hingga Oktober (dan mungkin hingga akhir November) bertepatan dengan musim durian di Ketapang. Sesuatu yang tidak pernah saya alami lagi semenjak lulus SMA dan merantau ke pulau Jawa mulai tahun 2015.
BACA JUGA: Berkaca pada Kasus Bunuh Diri di Pekalongan, Dampak Buruk Gadget bagi Anak
Musim durian di Ketapang adalah hal yang sangat memuaskan mata, ketika melihat durian-durian lokal bertumpukan di tepi jalan. Sebut saja spot-spot favorit para penjual durian: simpang empat RSUD Agoesdjam, Transito dekat Taman Makam Pahlawan Ketapang, sepanjang Jalan S. Parman, dan daerah di seberang jembatan Pawan.
Musim durian di Ketapang juga adalah momen ketika melihat sang buah tajam tersebut tersebut kehilangan harga dirinya. Durian ukuran sekepal bahkan bisa dibanderol dengan harga Rp10ribu untuk tiga buah. Durian bahkan tidak berharga sama sekali di desa-desa asal mereka, jika kita cukup rajin untuk berjuang ke sana dengan kendaraan pribadi.
Ritual favorit saya untuk makan durian adalah bersama mamak saya. Meskipun sudah berusia 54 tahun, mamak saya masih lah seorang “hantu durian”. Nafsu makan duriannya jauh melebihi saya. Kami berdua sering sekali dan hampir tiap malam keluar rumah dan motoran menjajal spot-spot penjualan durian di Ketapang untuk mencicipi lezatnya buah sorgawi tersebut.
Pada awal musim, durian yang kami beli masih berkisar di harga Rp25ribu hingga Rp35ribu untuk ukuran sedang. Tetapi sekarang, durian ukuran sedang bisa dibanderol dengan harga Rp10ribu per buah bahkan jika kami membeli durian ke teman mamak, banderol harga ukuran sedang bisa menyentuh harga Rp100ribu untuk 12 buah. Bisa dibilang dengan harga yang begitu murah, kami rajin hampir tiap malam makan durian, entah makan di tempat maupun dibawa pulang.
Salah satu keuntungan jika makan durian di tempat berjualan adalah jaminan ganti buah jika durian yang dibuka ternyata busuk atau tidak layak dimakan. Jika durian sudah dibuka di rumah dan ternyata busuk, tidak bisa diganti. Jadi lah saya dan mamak setiap malam nongkrong di tepi-tepi jalan, duduk di alas terpal, dan menikmati buah berkat Tuhan tersebut. Secercah kebahagian kecil yang saya nikmati bersama orangtua saya dengan disertai bincang-bincang ringan dan diiringi syukur kepada Pencipta.
Saya dan mamak saya memiliki kriteria yang sama dalam hal durian terbaik: rasa pahit. Berbeda dengan kebanyakan orang yang lebih menyukai durian yang bisanya berwarna kuning dan terasa manis susu, saya dan mamak saya lebih menyukai durian dengan rasa pahit yang menendang. Semakin pahit semakin gacor, bahkan kadang-kadang mirip rasa tuak. Saya dan mamak saya juga menemukan bahwa semakin pahit suatu durian, maka semakin cepat kita mabuk. Fly high, mother!
BACA JUGA: Semakin Mewah Pernikahan, Kemungkinan Cerai Makin Tinggi, Apa Iya?
Durian-durian lokal Ketapang berasal dari berbagai desa dan kecamatan di Ketapang. Meskipun hanya durian lokal dan kelas kualitasnya dianggap di bawah durian-durian seperti musang king, montong, duri hitam, bawor, dan lain-lain tapi kami tidak ambil pusing. Durian ya durian dan yang penting harganya murah. Harga-harga durian premium, apalagi yang dijual di Jakarta seharga puluhan bahkan ratusan ribu menjadi tidak rasional di kepala saya yang hampir setiap hari menyantap belasan durian dengan budget total Rp100ribu-an saja. Subjektif dan sesuai selera memang, tapi menurut saya rasa durian lokal Ketapang tidak kalah dengan durian-durian sultan yang pernah saya cicip sesekali di Jakarta.
Sebagai penutup, semakin ke sini saya semakin melihat durian bukan hanya sebagai sekadar buah. Durian memiliki filosofinya tersendiri. Self-defence fruit. Duri-durinya yang begitu tajam dan banyak, berguna sebagai perlindungan diri, ketika jatuh dari pohonnya yang tinggi saat matang, dan ketika diganggu oleh hama. Self-defence tersebut semata-mata untuk melindungi kenikmatan rasa manis di dalamnya. Inner beauty, they said. Kecantikan dan kebaikan yang terkandung dari dalam, dilindungi oleh senjata yang begitu tajam. Tuhan memang terlampau kreatif dalam menciptakan mekanisme seperti itu. Jika durian saja memiliki sisi indah di dalam dirinya dan berusaha untuk melindunginya sekuat mungkin, bagaimana dengan kita selaku manusia?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS