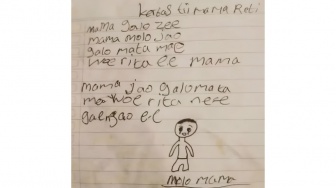Sobat Yoursay, fenomena FOMO (Fear of Missing Out) yang mencuat di kalangan publik bukan menjadi hal yang tabu lagi di mata publik.
Keberadaan istilah ini kian muncul di berbagai penelitian sebagai salah satu dampak psikologis dari penggunaan media sosial yang intens di kalangan pelajar dan generasi muda pada umumnya. Sayangnya, ternyata dampak dari FOMO ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga menggerus budaya literasi di kalangan pelajar.
FOMO pada dasarnya adalah perasaan cemas sosial yang membuat seseorang merasa terpaksa ikut serta dalam setiap hal yang sedang tren atau viral agar tidak merasa tertinggal.
Perasaan ini muncul karena keinginan untuk terus terlihat up-to-date, baik dalam berkomunikasi secara online maupun dalam kehidupan nyata. Bagi para pelajar, FOMO bisa menjadi tantangan yang cukup besar karena berkaitan erat dengan cara mereka mengatur waktu, mempertahankan fokus dalam belajar, serta minat untuk melakukan kegiatan atau membaca materi yang bermakna di luar penggunaan gadget.
![Ilustrasi pelajar sekolah. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menghapus PR menimbulkan perdebatan. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/06/11/28640-ilustrasi-pelajar-sekolah.jpg)
Berbagai studi mengungkapkan bahwa ada kaitan antara FOMO dan keterlibatan yang tinggi di media sosial.
Selain itu, melansir dari Jurnal Audiens, "Fenomena Budaya FoMO (Fear of Missing Out) di Media Sosial Tiktok pada Kalangan Gen Z" menunjukkan bahwa seringnya terlibat dalam aktivitas online, kebiasaan untuk selalu memeriksa media sosial, dan rasa khawatir akan "melewatkan sesuatu" adalah hal yang sering terjadi di lingkungan pendidikan.
Hal yang sama juga terlihat di kalangan generasi Z yang menunjukkan keinginan besar untuk mengikuti tren viral, terutama di platform seperti TikTok. (Sabila, K., 2025)
Sobat Yoursay, lantas bagaimana FOMO berhubungan dengan budaya literasi? Budaya literasi sebenarnya adalah kebiasaan untuk membaca, menulis, dan berpikir dengan kritis. Keterampilan ini seharusnya sudah mulai diajarkan sejak kecil dan terus dilatih sepanjang masa pendidikan.
Namun, ketika siswa lebih fokus untuk mengikuti tren di media sosial, waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca buku, artikel yang panjang, atau bahkan berdiskusi dengan serius menjadi berkurang. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menggulir konten yang cepat di layar, semakin sedikit waktu yang ada untuk membaca secara efektif dan reflektif.
Kita semua harus paham tentang kemajuan literasi di Indonesia. Kecenderungan membaca di antara siswa telah menjadi masalah sejak dulu.
Mengutip dari Pusmendik, Webinar Sharing Session GTK Kemendikbud, mengungkapkan hasil Survei internasional, Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan membaca di Indonesia masih jauh dari memuaskan dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
Turunnya nilai membaca bukan hanya menunjukkan bahwa keterampilan kita kurang, tetapi juga menggambarkan bahwa minat untuk membaca sebagai kebiasaan juga rendah. Fenomena digital yang disebabkan oleh rasa takut ketinggalan bisa membuat masalah ini semakin sulit untuk diatasi.
Tren Viral tidak Sepenuhnya Negatif, Semua Bisa di Kelola dengan Bijak
Fenomena ini perlu mendapat perhatian serius. Media sosial, dengan sistem yang terus menyajikan konten baru dan populer, menciptakan dorongan mendesak untuk selalu mengikuti kabar terbaru.
Akibatnya, murid kerap memilih konten yang ringan dan cepat dikonsumsi, seperti video singkat, meme, atau tantangan viral, alih-alih membaca buku atau artikel panjang yang menuntut konsentrasi lebih lama. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, kemampuan membaca dan memahami teks secara mendalam akan perlahan menurun.
Dampaknya tidak berhenti di situ. Pola konsumsi tersebut turut memengaruhi cara murid memahami realitas di sekitarnya. Buku dan teks panjang sejatinya memberi ruang untuk memahami konteks, melatih berpikir kritis, dan mengolah ide-ide kompleks.
Sebaliknya, sebagian besar konten media sosial disajikan secara instan dan fragmentaris. Ketika FOMO mendorong murid untuk terus mengejar konten viral, waktu dan ruang untuk membaca secara serius pun semakin menyempit.
Namun, media sosial tidak sepenuhnya berdampak negatif. Platform digital juga dapat menjadi alat literasi jika digunakan secara cerdas dan bijak. Media sosial bisa membantu pelajar menemukan rekomendasi buku, mengakses artikel berkualitas, atau terlibat dalam diskusi yang bermakna. Agar potensi ini terwujud, diperlukan kesadaran kritis dari pelajar serta dukungan dari berbagai pihak, terutama lingkungan pendidikan, untuk membangun literasi digital yang sehat.
Peran sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci. Dampak FOMO terhadap literasi tidak bisa diatasi secara parsial.
Pendidikan literasi digital perlu mengajarkan pelajar cara mengelola waktu bermedia sosial dan memilih konten yang bermutu. Di saat yang sama, sekolah perlu mengintegrasikan budaya literasi ke dalam kurikulum, tidak hanya sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi sebagai praktik yang hadir di setiap proses pembelajaran.
Singkatnya, FOMO telah menjadi bagian dari kehidupan digital pelajar masa kini. Tantangannya adalah bagaimana fenomena ini tidak menggerus budaya membaca dan berpikir mendalam. Membangun generasi yang tidak sekadar cepat mengikuti tren, tetapi juga kuat dalam membaca dan bernalar, merupakan tanggung jawab bersama, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebab, literasi sejati bukan soal tidak tertinggal tren, melainkan kemampuan memahami dunia secara lebih luas dan bermakna.