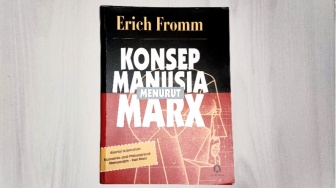Tidak ada rezim tanpa meninggalkan bekas ingatan. Semua rezim pasti meninggalkan sejarah, meninggalkan ingatan, meninggalkan wacana, dan meninggalkan pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi generasi di masa mendatang. Begitulah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Jokowi. Di masa-masa akhir pemerintahannya, ia ingin mengabadikan namanya dalam proyek besar dalam sejarah, yakni pemindahan ibu kota.
Jika kita belajar ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa setiap rezim di negeri ini pasti meninggalkan namanya dalam sebuah catatan sejarah. Misalnya Soekarno, maka kita akan terngiang dengan wacana bapak proklamator, orla (orde lama), nasionalisme, atau bahkan di era Soekarno juga pemindahan ibu kota sempat terjadi tiga kali mulai dari ke Jogja, ke Bukit Tinggi dan kembali lagi ke Jakarta.
Contoh lain juga seperti Soeharto, maka kita akan langsung teringat dengan orba (orde baru), bapak pembangunan, dan reformasi. Habibie, teknokrat, bapak teknologi dan pesawat. Gus dur, bapak pluralisme, toleransi dan presiden-presiden lainnya yang juga meninggalkan nama, wacana dan pengetahuan bagi generasi selanjutnya.
Sebagaimana gagasan dari seorang filosof kotemporer asal Prancis yakni Michel Foucault (1980, 2002) bahwa setiap rezim kekuasaan akan melahirkan sebuah wacana, pengetahuan, atau lebih ektremnya yakni melahirkan rezim kebenaran bagi masyarakatnya.
Di rezim Jokowi, kita tau bahwa program kerja terbesarnya yakni IKN, terlepas dari pembangunan-pembangunan lainnya seperti tol di berbagai daerah, Mandalika, dan lain sebagainya. Ketika anak cucu kita belajar sejarah perihal Jokowi, maka ikon sentralnya adalah IKN, karena memang capaian tertingginya adalah IKN tersebut yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.
Meskipun Soekarno pernah memindahkan ibu kota, namun itu atas dasar konflik yang terjadi saat itu dan itupun tidak berlangsung lama, serta tidak melakukan pembangunan besar-besaran. Berbeda dengan di rezim Jokowi yang konteksnya memang ingin mengentaskan berbagai problem seperti pemerataan pembangunan dan menghapus stigma jawasentris. Oleh karena kebijakan yang amat besar ini, nama Jokowi tersematkan di dalamnya.
Nama Jokowi akan ter-abadisasi di proyek IKN tersebut. Jokowi tidak perlu menyematkan namanya dalam penamaan IKN, sebagaimana beberapa waktu lalu yang diusulkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahwa IKN diberi nama “Jokowi” layaknya ibu kota Kazakhstan Nursultan yang berasal dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev. Hanya melalui penamaan IKN dengan nama “Nusantara” saja, sebenarnya nama Jokowi akan tetap eksis dan abadi dalam catatan sejarah.
Pasalnya, proyek IKN ini bukanlah proyek sekali jadi, melainkan butuh beberapa puluh tahun kemudian, atau bahkan beberapa rezim kemudian untuk menyempurnakan pembangunannya. Sedangkan, Jokowi menjadi sosok pemrakarsa dari pemindahan ibu kota ini.
Meskipun kita tau dan tidak bisa terabaikan bahwa rezim Jokowi tidak selalu berkonotasi positif selama kepemimpinannya berlangsung, misalnya banyak penggusuran lahan dengan dalih pembangunan, demo mahasiswa besar-besaran layaknya era reformasi juga terjadi di rezim tersebut, bahkan korupsi sudah seperti berita biasa yang didengar telinga masyarakat.
Kita berkaca pada orde baru yang gagal mencitrakan dirinya dengan baik meskipun pembangunan besar-besaran di rezim tersebut terjadi, karena di akhir pemimpinannya ia melepas jabatan dengan cara konflik dan peralihan reformasi yang seketika itu program kerjanya dan sumbangsihnya kepada bangsa dilupakan begitu saja.
Rezim Jokowi tentu saja sadar akan hal itu dan ia belajar dari sejarah bahwa suatu rezim akan dikenang di detik-detik akhir periodenya. Oleh karena itu, wacana mengenai pemindahan ibu kota baru dipopularkan pada akhir-akhir pemerintahannya, bukan di saat “kabinet kerja” awal ia menjadi presiden Indonesia.
Jadi, rezim Jokowi akan dapat berkonotasi negatif ataupun positif tergantung dari kinerjanya di detik-detik terakhir periode kepemimpinannya. Jika rezim ini memproduksi wacana yang justru bernilai negatif bagi masyarakat, maka wacana tersebut akan terekam oleh sejarah secara abadi dalam ingatan generasi mendatang.
Meskipun itu dalam naungan program kerja IKN sekalipun. Misalnya, awalnya pemindahan ibu kota akan disambut dengan baik oleh masyarakat dengan dalih pemerataan pembangunan, menghilangkan jawasentris, dan lain sebagainya.
Namun, ketika pembangunan IKN tersebut justru menimbulkan konflik seperti pembebasan lahan secara eksploitatif dan pembangunan hanya mementingkan kelompok pemodal alias investor, maka konotasi pemindahan IKN akan menjadi sangat negatif, dan lebih parahnya ada nama Jokowi dalam proyek agung tersebut.
Misalnya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Pemaluan dan desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kamupaten Panajam Paser Utara (Ariyanti et al., 2022; Kodir et al., 2021). Tanah mereka yang berada di ring 1 IKN (pusat pemerintahan) tidak memiliki sertifkat yang jelas, karena memang didaerah tersebut masih menggunakan hukum adat dengan bentuk pengakuan masyarakat lokal. Walhasil, tanah yang tak bersertifikat itu dianggap sebagai tanah negara begitu saja.
Belum lagi ketika pembangunan IKN yang tidak bisa terlepas dari peluang investasi baru bagi para kapital, pemodal, investor yang siap untuk menyuntik kekayaannya pada proyek besar ini (Junaidi et al., 2022). Membuka pintu para pemodal untuk kepentingan kekayaan mereka, bukan atas nama nasionalisme, kebangsaan atau kesejahteraan rakyat kecil.
Walhasil, nama Jokowi dipertaruhkan, wacana era pemerintahan Jokowi menjadi sejarah. Seolah-olah pembangunan ini merupakan tarian di atas air mata rakyat kecil yang tanahnya dirampas, Sebuah tarian di tengah ketimpangan sosial.
Anak cucu kita akan mengenang Jokowi karena proyek besarnya dalam pemindahan IKN. Namun, ketika proyek tersebut dilakukan secara eksploitatif, maka anak cucu kita akan sadar betapa mengerikannya suatu rezim demi pembangunan mengorbankan rakyatnya sendiri. Nama Jokowi akan abadi di proyek IKN, dan penilaiannya akan tergantung di detik-detik akhir periode kepemimpinannya saat ini.