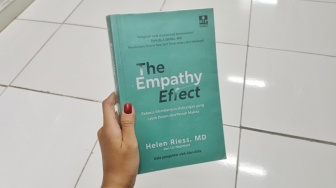Ada satu momen yang cukup mengguncang dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri baru-baru ini. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memberikan arahan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menghapus kebijakan kuota impor, terutama untuk komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurut Presiden, siapa pun yang ingin mengimpor produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia seharusnya dipersilakan, tanpa perlu mekanisme penunjukan khusus. Pernyataan ini menandai titik balik besar dalam arah kebijakan perdagangan nasional.
Selama ini, kuota impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kuota bukan sekadar alat administrasi, tapi juga merupakan instrumen proteksi agar pasar domestik tidak sepenuhnya dikuasai barang luar negeri.
Kebijakan ini, bila benar dijalankan tanpa batas, tentu akan mengubah lanskap ekonomi nasional secara drastis. Bukan hanya karena akan membanjiri pasar dengan produk luar, tetapi juga karena ia mengirim pesan: bahwa pemerintah lebih percaya pada mekanisme pasar bebas ketimbang pada kekuatan produksi dalam negeri.
Membuka keran impor tanpa kuota, di permukaan, memang tampak seperti langkah progresif: mempercepat arus barang, menekan harga, dan merespons kebutuhan masyarakat. Tapi dalam dunia nyata, kebijakan ekonomi tak pernah sesederhana itu. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah komoditas pangan, sesuatu yang sangat erat dengan produksi lokal, lapangan kerja, dan ketahanan nasional.
Ambil contoh daging sapi, yang sering disebut sebagai salah satu komoditas yang akan diimpor dalam jumlah besar demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Eliza Mardian dari CORE, kebijakan ini bisa membebani neraca perdagangan pangan kita yang saat ini pun sudah sangat bergantung pada impor. Sebelum program MBG berjalan pun, 54% konsumsi daging dan 80% konsumsi susu masih berasal dari luar negeri. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa memperparah ketergantungan tersebut.
Namun isu ini bukan cuma soal sapi. Ini juga tentang beras, garam, sayuran, buah, bahkan ikan asin. Dan ini yang membuat banyak orang khawatir, bukan karena impor itu selalu buruk, tapi karena pemerintah tampaknya tidak punya strategi besar selain membuka seluas-luasnya pintu masuk barang dari luar.
Kebijakan ini juga terasa janggal jika melihat situasi global. Amerika Serikat, misalnya, baru saja menerapkan tarif 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Artinya, akses ekspor kita dipersempit. Tapi anehnya, kita justru membuka akses impor tanpa syarat yang ketat.
Kepala Pusat Industri dan Perdagangan INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut kombinasi ini sangat berbahaya. Ekspor ditekan, impor dibebaskan, dan cadangan devisa bisa terkuras. Dalam tiga tahun terakhir saja, surplus perdagangan Indonesia terus menyusut: dari USD 54,5 miliar pada 2022 menjadi USD 31 miliar di 2024. Jika tren ini dibiarkan, defisit perdagangan bukan hal yang mustahil.
Efek dominonya nyata. Rupiah bisa melemah, daya beli masyarakat turun, dan konsumsi rumah tanggapenopang utama ekonomi nasional akan terpukul. Apa artinya membuka impor seluas-luasnya kalau masyarakat tidak mampu membeli?
Tulisan ini tidak sedang menolak impor. Dunia modern memang tak bisa hidup tanpa perdagangan global. Tapi membuka keran impor tanpa arah yang jelas, tanpa peta jalan perlindungan untuk sektor strategis domestik, adalah bentuk kebijakan reaktif yang bisa berbalik menjadi bumerang.
Yang dibutuhkan hari ini bukan respons cepat untuk memadamkan keluhan sesaat, melainkan strategi jangka panjang yang kokoh. Kita butuh kebijakan pangan dan perdagangan yang berpihak pada produsen lokal, bukan sekadar menggembirakan investor dan importir. Karena jika semua bisa diimpor, lalu apa yang tersisa untuk kita bangun sendiri?