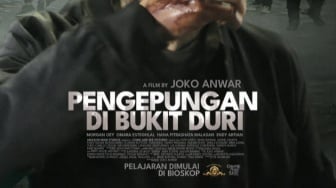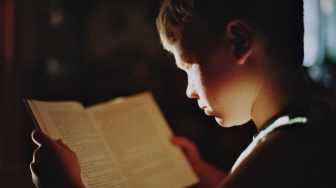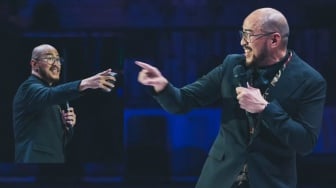Ketika pemerintah hari ini menggaungkan slogan “Merdeka Belajar”, tak sedikit dari kita mengira bahwa ini adalah gagasan baru yang progresif. Padahal, jauh sebelum Indonesia merdeka secara politik pada 1945, Ki Hadjar Dewantara sudah lebih dulu memerdekakan pendidikan melalui sebuah gerakan bernama Tamansiswa.
Didirikan pada tahun 1922, Tamansiswa bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah bentuk perlawanan kultural terhadap sistem pendidikan kolonial yang elitis, diskriminatif, dan menjauhkan rakyat dari akar budayanya.
Di tengah arus pendidikan Belanda yang hanya bisa diakses kaum priyayi dan keturunan Eropa, Tamansiswa hadir sebagai taman belajar bagi semua anak bangsa, terlepas dari kelas sosial, agama, maupun latar belakang etnis.
Ki Hadjar meyakini bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menundukkan. “Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak,” begitu salah satu asas dasar Tamansiswa.
Dalam kalimat itu, tersimpan keyakinan mendalam bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi, dan tugas pendidikan adalah membantu mereka menemukan serta mengembangkannya.
Berbeda dengan sistem kolonial yang menjadikan pendidikan sebagai alat domestikasi, mencetak tenaga kerja terampil tapi tidak kritis. Tamansiswa membangun model pendidikan yang humanis dan membumi. Pelajaran disampaikan dalam bahasa ibu. Materi disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial murid.
Tamansiswa juga memposisikan guru bukan sebagai otoritas tunggal, tetapi sebagai "pamong", yaitu pembimbing yang sejajar dan membangun dialog dengan muridnya.
Secara sadar, Tamansiswa menempatkan dirinya dalam jalur perjuangan politik yang lebih halus: perjuangan melalui kebudayaan. Pendidikan dipandang bukan sebagai ruang netral, tetapi sebagai arena pertarungan ideologi.
Dalam konteks itu, Tamansiswa bukan hanya mendidik anak-anak untuk pandai membaca dan berhitung, tetapi juga untuk mengenal jati diri, mencintai bangsanya, dan berani berpikir merdeka.
Inilah yang menjadikan Tamansiswa sebagai institusi politik dalam arti yang lebih dalam. Bukan politik elektoral atau partai, tetapi politik pembentukan kesadaran.
Ki Hadjar memahami bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya persoalan mengganti bendera penjajah dengan bendera sendiri, melainkan membebaskan cara berpikir manusia Indonesia dari ketergantungan, inferioritas, dan imitasi buta terhadap budaya asing.
Apakah “Merdeka Belajar” Hari Ini Benar-Benar Mewarisi Semangat Tamansiswa?

Sayangnya, meskipun istilahnya sama, semangatnya sering kali berbeda. Kita masih melihat pendidikan yang terlalu berorientasi pada angka, nilai, dan peringkat.
Kurikulum terlalu sering berganti mengikuti kepentingan politik. Siswa diajarkan untuk patuh, bukan berpikir kritis. Guru dibebani administrasi, bukan diberdayakan sebagai pendidik sejati.
Lebih dari itu, pendidikan kita masih sangat terjebak dalam logika pasar. Lembaga pendidikan tinggi berlomba-lomba menjual “kompetensi” sebagai komoditas.
Sekolah swasta menjamur, tetapi hanya bisa diakses oleh kalangan ekonomi atas. Pendidikan negeri pun tidak lepas dari kesenjangan kualitas antara daerah kota dan pelosok.
Padahal, jika kita kembali ke akar pemikiran Ki Hadjar, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan, bukan mempertegasnya. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh menjadi manusia utuh, bukan sekadar manusia kerja.
Tamansiswa mengajarkan bahwa pendidikan adalah peristiwa budaya. Ia tidak bisa dilepaskan dari nilai, kearifan lokal, dan realitas sosial masyarakat. Inilah yang membuatnya relevan hingga hari ini.
Ketika kita berbicara tentang merdeka belajar, kita tidak sedang mencari formula baru, melainkan seharusnya sedang menggali warisan yang pernah dibangun oleh Ki Hadjar hampir seabad lalu.
Tugas kita hari ini bukan menciptakan ulang gagasan, tetapi menghidupkan kembali semangatnya dalam sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan membebaskan.
Karena merdeka belajar bukan sekadar kebijakan birokrasi, melainkan filosofi perjuangan. Dan Tamansiswa adalah buktinya: bahwa sebelum bangsa ini merdeka secara politik, pendidikan sudah lebih dulu memerdekakan manusia-manusianya.
Konsep pendidikan Tamansiswa yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara bukan sekadar warisan sejarah, melainkan visi besar yang justru semakin relevan di tengah krisis nilai dan kemandekan sistem pendidikan saat ini.
Dengan filosofi among, asah, asih, asuh, pendidikan ditekankan sebagai proses membimbing, bukan menekan. Guru ideal bukanlah penguasa di ruang kelas, tetapi panutan yang menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa ingin tahu murid.
Tak kalah penting, Tamansiswa mengakar kuat pada nilai Trisakti Jiwa: kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Di tengah gempuran arus globalisasi dan budaya instan, pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter.
Kurikulum pun semestinya tak hanya mengejar nilai ujian, tapi juga menyisipkan pelajaran hidup, tentang gotong royong, keberagaman, dan cinta tanah air. Sekolah dapat menjadi ruang hidup yang menghargai budaya lokal, membiasakan empati sosial, dan membentuk siswa yang tak hanya cerdas, tapi juga berintegritas.
Lebih dari itu, Ki Hadjar jauh mendahului zamannya dengan gagasan kemerdekaan belajar, bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sesuai kodratnya sendiri.
Saatnya sekolah memberi ruang bagi eksplorasi, proyek kreatif, serta pemanfaatan teknologi yang memerdekakan proses belajar.
Jika ide-ide Tamansiswa dihidupkan kembali secara progresif, kita tak hanya mengenangnya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai inspirasi nyata untuk merevolusi pendidikan Indonesia hari ini.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS