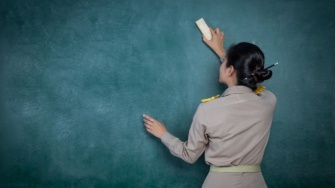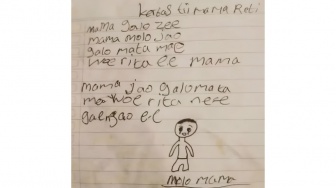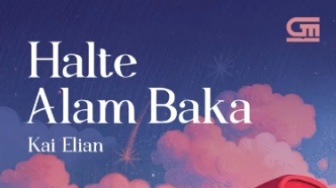Satu hal yang selalu menggelitik ketika kita berbicara tentang organisasi kemahasiswaan adalah semangat awal yang membara, namun sayangnya sering redup di tengah jalan. Di permukaan, mahasiswa tampak berbondong-bondong mendaftar menjadi relawan organisasi, seolah menjadi aktivis kampus adalah hal paling penting setelah IPK dan sertifikat TOEFL. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bertahan dan menunjukkan komitmen jangka panjang? Pertanyaan ini menjadi nyawa dari sebuah penelitian yang baru-baru ini terbit di Jurnal Psikologi Integratif berjudul “Peran Self-Regulation dan Self-Perceived Employability terhadap Komitmen Afektif Relawan Mahasiswa” oleh Humairah dan Herlena (2024) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbit dalam jurnal psikologi integratif.
Sekilas, judulnya terdengar akademis, bahkan terlalu akademis bagi sebagian orang. Tapi jangan buru-buru menyepelekannya. Di balik jargon psikologis seperti “self-regulation” dan “self-perceived employability”, tersembunyi satu ironi besar yang sebenarnya sedang terjadi di banyak organisasi mahasiswa: banyak yang ikut karena tren, sedikit yang betul-betul terlibat.
Humairah dan Herlena menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, melibatkan 201 mahasiswa tahun akhir yang aktif (setidaknya secara administratif) sebagai relawan di organisasi kampus. Mereka menemukan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengatur diri dan persepsi mereka terhadap kelayakan kerja (alias: “seberapa yakin saya akan dapat kerja nanti?”) punya hubungan yang signifikan terhadap komitmen afektif mereka sebagai relawan. Komitmen afektif di sini bukan sekadar hadir rapat atau ikut kegiatan, tetapi mencakup keterikatan emosional dan loyalitas terhadap organisasi.
Temuan mereka bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi tetap menyentil. Kita hidup di era di mana aktivisme mahasiswa lebih sering jadi alat marketing personal. Organisasi bukan lagi rumah ideologis, melainkan tempat menambal CV yang bolong. Bahkan dalam penelitian ini disebutkan, ada organisasi yang tingkat ketidakhadiran anggotanya mencapai 40,94%, dan 50,73% anggota dinyatakan tidak aktif. Bukankah ini angka yang cukup memalukan jika mengingat betapa banyak organisasi berlomba-lomba rekrut anggota tiap tahun?
Yang menarik (dan menyedihkan) adalah alasan mengapa mahasiswa bergabung. Banyak yang melakukannya demi “nilai tambah” saat melamar kerja. Ya, organisasi kini diposisikan sebagai semacam pelengkap penderita dari proses menuju dunia kerja. Bukan sebagai ruang aktualisasi, pembentukan karakter, atau laboratorium sosial. Apakah ini sepenuhnya salah? Tentu tidak. Tapi mari kita renungkan: jika organisasi hanya dijadikan alat transaksional untuk masa depan yang belum tentu, apa yang tersisa dari nilai gotong royong, ideologi kolektif, atau semangat pergerakan?
Penelitian ini menyoroti bahwa mahasiswa dengan kemampuan self-regulation yang tinggi cenderung memiliki komitmen afektif yang lebih kuat. Artinya, mereka yang tahu cara mengatur waktu, menetapkan tujuan, dan mengevaluasi diri akan lebih mungkin bertahan dan terlibat aktif. Di sisi lain, mahasiswa yang memiliki persepsi positif terhadap kelayakan kerja juga menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Logikanya sederhana: ketika seseorang merasa dirinya kompeten dan punya peluang besar di masa depan, maka ia akan memilih aktivitas yang benar-benar bermakna termasuk dalam organisasi.
Namun, di sinilah letak kerumitan yang tidak sempat dikupas tuntas oleh penulis. Komitmen bukan hanya perkara individual. Ia tumbuh dalam konteks. Bahkan self-regulation dan perceived employability sekalipun bisa menjadi hampa jika organisasi tidak menawarkan ruang yang sehat untuk bertumbuh. Budaya organisasi yang hierarkis, eksklusif, penuh drama, atau sekadar copy-paste dari tahun sebelumnya bisa jadi penyebab utama apatisme anggota. Ironisnya, hal ini jarang dibahas dalam laporan evaluasi tahunan organisasi.
Penelitian ini kuat secara metodologis, tetapi tetap menyisakan ruang kosong dalam menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” relawan mahasiswa kehilangan komitmennya. Data kuantitatif memberikan korelasi, tapi tidak bisa menafsirkan makna. Apa yang dirasakan mahasiswa ketika mereka dipinggirkan oleh senior? Bagaimana pengalaman menjadi ‘anak bawang’ dalam rapat-rapat penting memengaruhi rasa memiliki mereka terhadap organisasi? Apakah mereka merasa organisasi memberi dampak nyata dalam kehidupan mereka, atau sekadar menyita waktu?
Bayangkan jika penelitian ini dilengkapi dengan suara-suara personal dari mahasiswa yang nyaris drop-out dari organisasi karena frustasi, atau dari mereka yang memilih hengkang karena merasa tidak ada ruang untuk berkontribusi. Di situlah kita bisa menangkap dinamika afektif sesungguhnya bukan sekadar skor rata-rata dari skala Likert.
Belum lagi faktor-faktor eksternal yang tak bisa diabaikan: tekanan akademik, beban kerja part-time, tanggung jawab keluarga, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap struktur organisasi itu sendiri. Komitmen dalam organisasi mahasiswa bukanlah soal kemauan semata, tetapi juga soal kesempatan, keadilan, dan rasa dihargai. Jika ruang-ruang itu tidak tersedia, maka sebaik apa pun kemampuan regulasi diri seseorang, ia akan tetap memilih mundur secara perlahan.
Dari sisi praktis, artikel ini menawarkan satu pesan penting bagi para pengelola organisasi mahasiswa dan pembina kemahasiswaan: berhentilah berpikir bahwa masalah rendahnya komitmen adalah kesalahan individu. Sudah saatnya organisasi bercermin. Apakah struktur dan budaya internal sudah cukup ramah bagi generasi muda yang cepat bosan tapi punya banyak potensi? Apakah ruang pengembangan diri dibuka lebar, atau hanya untuk mereka yang ‘dekat’ dengan pengurus inti?
Organisasi kemahasiswaan semestinya menjadi ruang pelatihan kepemimpinan, bukan sekadar mesin administrasi atau tempat formalitas berkegiatan. Di sana seharusnya tumbuh nilai loyalitas, tanggung jawab, empati, dan kemampuan berkolaborasi semua itu tidak muncul dalam ruang yang kaku dan sarat politisasi. Maka, jika kita serius ingin meningkatkan komitmen relawan mahasiswa, mulailah dari membangun organisasi yang sehat, terbuka, dan bermakna.
Dalam dunia kerja, orang yang loyal dan punya komitmen tinggi bukan mereka yang pandai menjilat, tetapi mereka yang merasa dihargai dan dilibatkan secara utuh. Begitu juga dalam organisasi mahasiswa. Komitmen bukan dibentuk dari SK pengangkatan atau sertifikat penghargaan, melainkan dari pengalaman emosional yang bermakna dan konsisten. Jika kita gagal menciptakan itu, maka tak usah heran jika organisasi hanya akan jadi tempat numpang nama, bukan ladang pembentukan karakter.
Penelitian Humairah dan Herlena adalah langkah awal yang bagus untuk membongkar realitas ini. Tapi pekerjaan rumahnya masih panjang. Komitmen afektif adalah sesuatu yang tumbuh dari hubungan timbal balik. Dan selama organisasi masih menganggap anggotanya sebagai angka, bukan manusia utuh dengan potensi dan dinamika, maka kita hanya akan melihat siklus yang berulang: rekrutmen besar-besaran di awal tahun, lalu ghosting massal beberapa bulan kemudian.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.