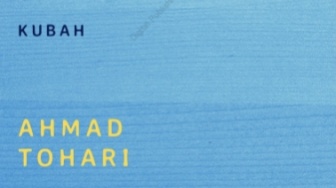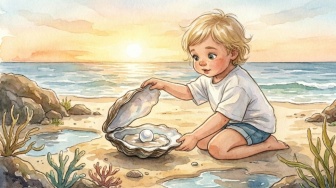Di tengah gempuran budaya populer global yang nyaris tanpa henti, siapa sangka bahwa kekuatan ponsel, kreativitas lokal, dan semangat komunitas mampu melawan arus dengan cara yang mengejutkan: membumikan budaya sendiri lewat media sosial. Itulah yang tengah terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tempat tradisi Pacu Jalur balap perahu tradisional yang sudah berusia lebih dari satu abad kembali menggaung ke seluruh penjuru negeri, bahkan dunia, berkat tangan-tangan kreatif para konten kreator lokal.
Tidak lagi hanya menjadi tontonan musiman di tepi Sungai Kuantan, Pacu Jalur kini telah menjelma menjadi fenomena digital. Videonya berseliweran di linimasa Instagram dan TikTok, menggugah rasa bangga, rasa ingin tahu, dan bahkan rindu akan akar tradisi. Namun siapa aktor di balik semua ini? Mereka adalah akun-akun Instagram seperti @pacujalur_net, @pacujalur_mendunia, @pacujalur.fanatic, @pacu_jalur_tradisional, @kuantanesia, @kuansing_footage, dan @infokuansing. Dalam keheningan algoritma, mereka bekerja tanpa sorotan besar, tetapi dengan dampak yang tidak bisa dianggap remeh.
Budaya daerah seringkali menghadapi paradoks: kaya secara makna, miskin secara perhatian. Banyak tradisi besar yang hilang ditelan zaman bukan karena tidak relevan, melainkan karena tidak terdengar. Di sinilah pentingnya peran mediasi budaya dan hari ini, mediasi itu dilakukan oleh para konten kreator.
Dalam konteks Pacu Jalur, keberadaan akun-akun tersebut bukan sekadar dokumentasi biasa. Mereka melakukan kerja budaya yang nyaris setara dengan lembaga pelestarian tradisional. Mereka membingkai ulang tradisi agar relevan di era digital: menjadikannya konten visual yang estetis, emosional, dan informatif. Momen-momen dramatis saat perahu melaju membelah air, sorak sorai penonton di tepian, hingga ekspresi penuh haru para anak jalur direkam dengan sensitivitas yang tinggi. Mereka tak hanya merekam, mereka menghidupkan ulang suasana mengajak warganet seolah-olah turut berada di sana.
Menariknya, hampir semua akun tersebut digerakkan oleh komunitas atau individu secara swadaya. Tak ada anggaran APBD, tak ada gelar adat, tak pula gaji bulanan. Yang ada hanyalah semangat. Mereka membeli peralatan sendiri, meluangkan waktu untuk menyunting video, mencari spot terbaik di tengah kerumunan, menunggu momen yang pas, dan beradu cepat dengan algoritma Instagram agar unggahan mereka bisa tampil di halaman eksplor pengguna.
Sebagian bahkan tetap bekerja di sektor lain guru, mahasiswa, pegawai honorer, petani tetapi tetap konsisten menyisihkan waktu untuk mengabdi pada budaya lewat medium digital. Ini adalah bentuk baru dari aktivisme budaya: sunyi, melelahkan, tetapi vital.
@pacujalur_net, misalnya, secara konsisten menghadirkan liputan langsung dari arena pacu, lengkap dengan narasi dan penjelasan historis yang edukatif. @kuansing_footage menghadirkan dokumentasi dalam format sinematik, menjadikan Pacu Jalur bukan hanya tontonan lokal, tetapi juga estetika visual yang pantas dibanggakan secara global. Sementara @infokuansing memperluas jangkauan narasi dengan menyajikan sisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi tradisi tersebut. Inilah kolaborasi yang tidak dirancang oleh negara, tetapi lahir dari panggilan kolektif.
Namun demikian, peran para konten kreator ini juga patut kita lihat dengan kaca mata kritis. Sebab, di tengah sorotan dan ketenaran digital, selalu ada risiko bahwa budaya bisa terjebak dalam komodifikasi yang dangkal. Akankah Pacu Jalur tetap menjadi tradisi yang sarat nilai spiritual dan komunitas, atau justru bergeser menjadi “atraksi” untuk dijual demi engagement?
Pertanyaan ini penting karena tidak semua yang tampil di layar bisa menangkap kedalaman makna. Jika tak berhati-hati, narasi yang terbangun bisa berubah menjadi euforia kosong yang menekankan hiburan visual semata dan melupakan konteks sosial budaya yang menyertainya.
Oleh karena itu, tantangan bagi para konten kreator lokal hari ini adalah membangun narasi ganda: menarik dan menghibur, sekaligus mendidik dan merefleksikan. Ini bukan hal mudah. Tetapi beberapa akun terbukti mampu melakukannya. Mereka tidak hanya menyoroti perahu yang melaju kencang, tetapi juga kisah anak jalur yang berlatih di tengah keterbatasan, para tukang jalur yang mengukir perahu dengan nilai-nilai adat, serta bagaimana tradisi ini menjadi ruang pertemuan sosial lintas usia dan kelas.
Yang juga patut dicatat adalah bagaimana media sosial membuka ruang bagi demokratisasi representasi budaya. Dulu, narasi budaya daerah sangat tergantung pada media arus utama: surat kabar, televisi nasional, atau dokumentasi pemerintah. Siapa yang bisa tampil, dan bagaimana budaya digambarkan, seringkali ditentukan oleh kuasa redaksi atau birokrasi.
Kini, semua berubah. Anak muda dengan kamera HP dan akun Instagram bisa menjadi narator budaya. Mereka punya kuasa untuk memilih angle, menentukan tone cerita, dan menyebarkannya secara masif. Budaya lokal tak lagi dimonopoli oleh narasi elit. Ia tumbuh secara organik dari bawah dari masyarakat untuk masyarakat.
@pacujalur.fanatic, misalnya, kerap membagikan konten buatan warga biasa: video dari penonton di pinggir sungai, foto keluarga yang membawa anak kecil menyaksikan pacu, hingga komentar-komentar bernuansa nostalgia dari perantau. Ini adalah bentuk partisipasi budaya yang otentik dan berdaya.
Tidak dapat dimungkiri, popularitas Pacu Jalur hari ini yang mulai dikenal di luar Riau, bahkan di luar negeri tidak lepas dari sumbangan para konten kreator ini. Bahkan, ketika nama Pacu Jalur muncul di halaman media nasional atau ditonton oleh youtuber internasional seperti Joe Hattab, jejak digital dari akun-akun lokal ini telah lebih dahulu menyiapkan panggung.
Di sinilah letak nilai strategis mereka: menjadi garda terdepan dalam membangun identitas kolektif dan memperjuangkan eksistensi budaya daerah di kancah nasional. Pacu Jalur bukan sekadar lomba mendayung. Ia adalah simbol perjuangan, kegigihan, solidaritas, dan warisan sejarah masyarakat Melayu Kuantan. Dan berkat konten kreator, nilai-nilai ini tak hanya dikenang, tetapi juga disebarkan dan dihidupi oleh generasi baru.
Namun masa depan tradisi ini juga bergantung pada sejauh mana negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan mau mengakui dan mendukung kerja-kerja budaya dari para konten kreator lokal. Mereka seharusnya tidak diposisikan semata sebagai “penggembira” festival, tetapi sebagai mitra strategis dalam pelestarian budaya. Sudah saatnya pemda setempat mengintegrasikan peran mereka dalam strategi kebudayaan daerah: lewat pelatihan, kolaborasi konten, hingga dukungan logistik.
Satu lagi tantangan yang membayangi adalah ancaman monetisasi berlebihan. Ketika konten budaya mulai dilirik oleh sponsor dan platform, ada risiko bahwa narasi akan bergeser demi kepentingan komersial. Ini bukan sesuatu yang salah selama tetap mengedepankan autentisitas.
Para konten kreator lokal harus pandai menjaga integritas narasi budaya agar tidak terjebak dalam glorifikasi palsu. Mereka perlu membangun prinsip editorial sendiri: apa yang layak ditampilkan, bagaimana tradisi dikisahkan, dan sejauh mana hiburan boleh mengalahkan nilai. Ini adalah dilema kreatif yang sulit, tetapi penting.
Perjalanan Pacu Jalur dari sungai ke layar ponsel adalah bukti bahwa budaya bisa hidup dan berkembang tanpa harus kehilangan akarnya asal ada niat, ada upaya, dan ada komunitas yang peduli. Para konten kreator lokal yang selama ini bekerja di balik layar adalah pahlawan budaya yang tak banyak disorot. Mereka mengubah kamera menjadi alat pelestarian, menjadikan likes dan views sebagai jalan untuk membangkitkan kesadaran kolektif.
Sudah saatnya kita memandang mereka bukan sekadar “pengunggah konten,” tetapi sebagai penjaga nilai. Sebab dalam setiap video yang mereka unggah, ada cinta pada budaya, ada kerja keras, dan ada tekad untuk menjaga agar kita tidak lupa dari mana kita berasal.
Kepada para pembaca: jika suatu hari Anda menemukan video Pacu Jalur lewat ponsel Anda, berhentilah sejenak, tontonlah dengan mata yang terbuka dan hati yang peka. Di balik setiap kayuhan perahu itu, ada sejarah. Dan di balik setiap unggahan itu, ada anak negeri yang sedang memperjuangkan martabat budayanya dengan kamera, dengan sinyal, dengan cinta.