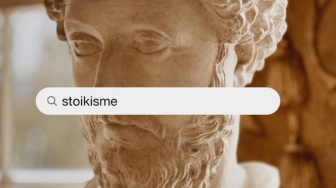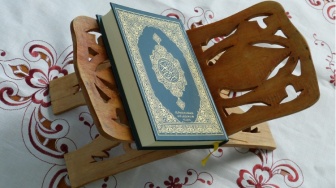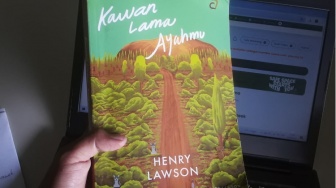Perubahan iklim bukan lagi isu yang bisa disikapi seolah masih jauh di cakrawala. Ia telah hadir, nyata dan merusak. Mengancam kesehatan publik, merenggut kehidupan, dan memperuncing ketimpangan sosial yang telah lama mengakar.
Dampaknya tak hanya terasa dari naiknya suhu atau cuaca yang tak menentu, tapi juga dari instabilitas ekonomi, politik, hingga krisis kemanusiaan yang makin sulit diprediksi.
Krisis ini bergerak kian kompleks, menjelma menjadi persoalan multidimensi yang menuntut respons serius dan terkoordinasi.
Indonesia, meskipun hanya menyumbang sekitar 1,3 persen emisi karbon global, merupakan salah satu negara yang paling rentan terkena imbasnya. Dari tenggelamnya pesisir akibat kenaikan permukaan laut, banjir musiman yang makin sering, kekeringan berkepanjangan, hingga bencana hidrometeorologis lainnya, negeri ini berada di garis depan ancaman iklim.
Di sinilah letak urgensinya: keterlibatan publik menjadi kunci. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam merespons isu iklim masih jauh dari memadai. Kesadaran kolektif belum tumbuh sepadan dengan ancaman yang dihadapi. Hanya sebagian kecil warga yang mengambil peran aktif dalam upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.
Salah satu akar persoalannya adalah lemahnya strategi komunikasi dan penyebaran literasi iklim. Informasi tentang krisis ini tak jarang berhenti di ruang-ruang akademik atau jargon teknokratis yang tak menjangkau publik luas.
Tanpa pembenahan cara menyampaikan narasi lingkungan, ketimpangan pengetahuan akan terus membentang, menghambat terciptanya gerakan bersama yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis terbesar abad ini.
Perubahan iklim bukan sekadar soal suhu atau cuaca. Ia adalah soal keberlangsungan hidup. Dan sejauh ini, kita belum cukup siap.
Sirine bahaya krisis iklim tak lagi terdengar samar. Dunia memanas, dan masa depan generasi muda dipertaruhkan. Di tengah meningkatnya ancaman ekologis, pendidikan semestinya menjadi benteng pertama, bukan sekadar menara gading yang abai. Ia memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran kolektif dan mendorong perubahan perilaku lintas generasi.
Sejumlah riset menunjukkan, pendidikan lingkungan yang dirancang secara sistematis tidak hanya menumbuhkan kepedulian di kalangan anak-anak, tetapi juga menular kepada keluarga mereka.
Di negara seperti Indonesia, hanya separuh populasi meyakini bahwa pemanasan global disebabkan oleh ulah manusia, peran pendidikan menjadi jauh lebih krusial.
UNESCO telah menegaskan pentingnya pendidikan sebagai garda terdepan menghadapi perubahan iklim. Melalui program Pendidikan Perubahan Iklim, badan PBB itu mendorong sistem pendidikan—baik formal, non-formal, maupun informal—untuk membekali warga dengan kemampuan membaca, menghadapi, serta berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan yang kian akut.
Di sisi lain, sistem pendidikan Indonesia yang terdesentralisasi kerap menjadikan isu iklim sebagai pilihan opsional, bukan prioritas. Daerah memiliki keleluasaan menentukan orientasi pendidikan, yang membuat pendidikan lingkungan sering kali kalah suara dibanding mata pelajaran lain.
UNESCO bahkan menyatakan keprihatinan: hampir separuh kurikulum dunia masih belum memasukkan materi krisis iklim, dan hanya segelintir guru yang merasa cukup kompeten untuk mengajarkannya.
Sementara itu, negara lain melangkah lebih progresif. Jepang, misalnya, berhasil menyelipkan prinsip Education for Sustainable Development (ESD) ke dalam kurikulum nasional mereka. Pelajaran tentang efisiensi energi dan gaya hidup ramah lingkungan diajarkan sejak dini, sejalan dengan agenda mitigasi perubahan iklim nasional mereka. Greta Thunberg tak mungkin lahir dari ruang kosong—ia muncul dari sistem pendidikan yang sadar akan urgensi lingkungan.
Indonesia perlu belajar dari pendekatan semacam itu. Literasi iklim harus diperdalam sejak dini, tak cukup sekadar disisipkan dalam pelajaran IPA.
Pemerintah perlu memperluas jangkauan konten edukatif melalui berbagai kanal, termasuk digital. Australia, misalnya, memiliki Curious Climate, platform interaktif yang menjawab pertanyaan anak-anak tentang iklim secara langsung dari para ilmuwan.
Lebih jauh, pendidikan berbasis proyek (project-based learning) mesti diperluas. Siswa harus diberi ruang untuk berpikir kritis, menyusun solusi, dan terlibat langsung dalam konteks lokal perubahan iklim. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace dan Walhi bisa memperkaya materi sekaligus membuka ruang aksi konkret bagi para siswa.
Sektor swasta pun tak bisa cuci tangan. Dunia usaha bisa turut serta dengan menyediakan program magang di sektor green jobs dan membimbing siswa pada praktik keberlanjutan yang aplikatif.
Namun, peran paling mendasar tetap ada pada keluarga. Pendidikan iklim sejatinya dimulai di meja makan, dalam obrolan sehari-hari, dan keputusan-keputusan kecil di rumah tangga.
Membangun sistem pendidikan perubahan iklim bukan hanya soal menyusun panduan atau memasukkan tema ke dalam silabus. Ini adalah soal keberanian politik untuk menggeser paradigma, dari pendidikan yang hanya mentransfer pengetahuan menjadi pendidikan yang memantik kesadaran.
Generasi mendatang berhak atas masa depan yang layak, dan tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan mereka cukup siap untuk memperjuangkannya.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS