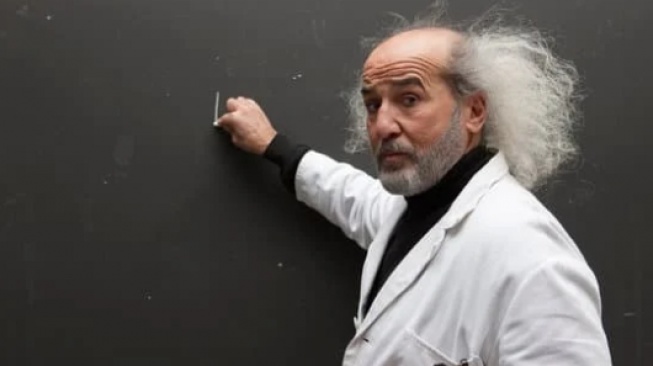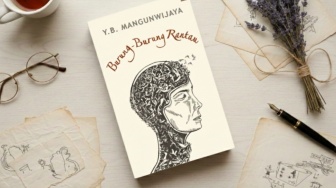Bayangkan sebuah universitas yang tampil di panggung dunia, dielu-elukan karena masuk “Top 500” versi pemeringkatan global. Kampus Indonesia ini punya mural digital di lobi rektorat bertuliskan “World Class University”, lengkap dengan sambutan marching band dan baliho bergambar Rektor tersenyum bijak. Namun, di balik parade itu, data berbicara lain. Laporan RI2—Research Integrity Risk Index—menampar kita semua, keras dan tanpa basa-basi.
Disusun oleh Prof. Lokman Meho dari American University of Beirut, RI2 adalah indeks pertama di dunia yang secara empiris mengukur risiko integritas riset. Hasilnya? Tak tanggung-tanggung, 13 perguruan tinggi besar Indonesia, termasuk yang konon terbaik seperti UI, UGM, dan Unair, masuk daftar merah: kategori buruk, berisiko tinggi, dan wajib dipantau. Lha, bagaimana bisa universitas yang bersinar di ranking dunia malah kusam dalam etika ilmiah?
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ini adalah panggilan darurat bagi dunia akademik Indonesia yang, alih-alih menjadi mercusuar ilmu, justru jadi tempat praktik kucing-kucingan akademik. Di sinilah ironi kita dimulai.
Akademisi Jadi Atlet Publikasi — Tapi Lari dari Etika
Dunia akademik Indonesia hari ini mirip kontes lari estafet, dosen-dosen saling oper tongkat publikasi demi mengejar angka. Target SKP, insentif jabatan, dan kebijakan Permendikbudristek No 39/2021 telah menjadikan publikasi sebagai tiket emas. Tapi seperti atlet doping, banyak kampus memilih jalan pintas.
RI2 memotret dua indikator utama: R-Rate (jumlah artikel yang ditarik per 1.000 publikasi) dan D-Rate (persentase artikel yang dihapus dari database pengindeks seperti Scopus dan WoS). Semakin tinggi angkanya, semakin besar dugaan pelanggaran integritas. Dan kita? Kita ada di papan atas—bukan karena prestasi, tapi karena "prestasi menarik artikel".
Pell dan Amigud (2022) menyebut bahwa target publikasi numerik memicu pelanggaran seperti plagiarisme dan submission ke jurnal predator. Di Indonesia, kita bahkan punya "paket hemat": submit sekali, dapat lima co-author, dan kadang bonus pencatutan nama mahasiswa. Publikasi menjadi komoditas, bukan kontribusi.
Kampus-kampus kita, dengan semangat "asal publish asal naik pangkat", seringkali abai pada substansi. Kalau ada dosen yang bertanya, “Ini jurnal predatory atau tidak?” maka jawabannya bukan dicek, tapi: “Yang penting sudah di Scopus, Pak.” Integritas? Nanti dulu.
Universitas Kita dan Ritual Pencitraan Akademik
Sebagian kampus menyambut laporan RI2 dengan sikap diplomatis ala korporat: “Kami akan evaluasi internal.” Tapi kita tahu, evaluasi macam apa yang dilakukan? Seperti audit kopi-kopi di ruang dosen—ramai di awal, hilang tanpa jejak.
Dokumen integritas akademik di banyak kampus hanya sebatas naskah sakral yang dibacakan saat yudisium. Etika akademik seolah-olah cukup diikrarkan, tak perlu dilaksanakan. Ini bukan sekadar kegagalan individu, melainkan cermin buruknya tata kelola institusi.
Farahat (2022) menyoroti bagaimana tekanan sosial dan budaya “hasil instan” berkontribusi pada perilaku akademik curang. Mahasiswa mencontek, dosen mencatut. Universitas tutup mata, selama angka publikasi naik dan akreditasi tak terganggu.
Coba tengok situs web kampus kita: dipenuhi banner “Scopus indexed!”, “Penulis Top ASEAN!”, bahkan “Publikasi Terbanyak di Asia Tenggara!” Tapi tidak ada satu pun yang bertanya: berapa yang ditarik karena pelanggaran? Berapa yang mencatut nama? Berapa yang menjiplak tugas akhir mahasiswa?
Dalam dunia akademik kita, pencitraan menjadi lebih penting daripada kebenaran. Dan di sinilah tragedinya: kampus tidak lagi menjadi benteng intelektual, melainkan biro pemasaran reputasi.
Ketika Etika Jadi Ekstra Kurikuler
Ada anggapan umum bahwa integritas akademik adalah tanggung jawab personal. Tapi RI2 menegaskan: ini persoalan institusional. Plagiarisme bukan semata hasil dari satu dosen nakal, melainkan kegagalan sistemik: pembimbing yang cuek, fakultas yang permisif, dan universitas yang tidak punya mekanisme kontrol.
Sozon et al. (2024) menunjukkan bahwa banyak mahasiswa dan dosen tidak mendapat pelatihan etika akademik yang memadai. Di Indonesia, pelatihan semacam ini sering kali formalitas—dua jam webinar, lalu tanda tangan kehadiran, selesai.
Pernah ada kasus di salah satu universitas Islam negeri, di mana guru besar mencatut hasil tesis mahasiswa. Ketika diusut, pihak kampus mengatakan “itu miskomunikasi.” Seolah-olah karya ilmiah adalah sepiring gorengan—bisa direbut kalau tidak cepat dimakan.
Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia difasilitasi oleh sistem yang memaafkan, kadang malah melindungi pelanggar. Bahkan ada dosen yang sudah dicabut publikasinya, tapi tetap dilantik jadi rektor. Ajaib? Tidak. Sistem kita memang sering berpihak pada yang lihai, bukan yang lurus.
Dari Permendikbudristek ke Perombakan Paradigma
Permendikbudristek No 39/2021 memberi insentif besar pada publikasi. Sayangnya, tidak ada mekanisme ketat untuk mengaudit kanal publikasi yang digunakan. Akibatnya, jurnal predator tumbuh subur, dan universitas berlomba mengisi halaman-halaman kosong itu dengan “tulisan apa saja”.
Sudah waktunya regulasi ini direvisi. Audit integritas harus jadi kewajiban, bukan pilihan. Kampus yang ingin insentif dari negara wajib memiliki sistem evaluasi etik yang kredibel, bukan sekadar deklaratif. Tidak cukup hanya mengejar angka publikasi—kita harus memastikan bahwa publikasi itu layak, sahih, dan etis.
Sebagai ide segar, pemerintah bisa membentuk Lembaga Audit Integritas Akademik Nasional (LAIN), yang bertugas melakukan investigasi independen terhadap kasus plagiarisme, pencatutan, dan manipulasi publikasi. Lembaga ini harus punya kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada institusi, bukan hanya individu.
Kita juga butuh whistleblower system yang aman dan anonim, agar mahasiswa atau dosen muda yang menemukan pelanggaran bisa melapor tanpa takut intimidasi. Karena hari ini, banyak suara dikubur sebelum sempat menggema.
Kembali ke Makna Ilmu, Bukan Hanya Laporan Tahunan
Universitas, menurut etimologinya, adalah komunitas pencari kebenaran. Tapi hari ini, banyak yang lebih mirip korporasi yang menjual indeks, branding, dan sertifikasi. Kita punya fakultas dengan nama "Ilmu" tapi kehilangan nilai-nilai keilmuannya.
Ranking dunia tidak boleh jadi kedok atas aib lokal. Dunia boleh mengagumi kita, tapi jika rumah sendiri penuh kebohongan, maka itu bukan prestasi—itu sandiwara. Kita tak bisa bicara “World Class” jika masih bergelut dengan praktik kelas bawah seperti menjiplak, mencatut, dan menipu sistem.
Pendidikan tinggi Indonesia harus berani mereformasi diri, bukan sekadar berbenah wajah. Mari kita jadikan integritas bukan sebagai syarat administrasi, tapi napas dari setiap penelitian dan pengajaran. Karena tanpa itu, kampus hanyalah gedung kosong yang gemar membohongi dirinya sendiri.