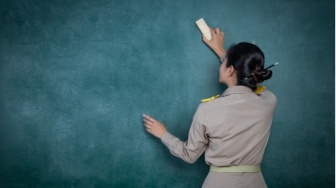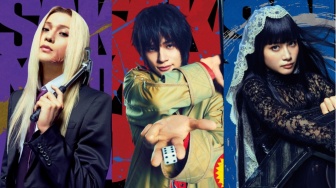Putusan terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Ia dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp750 juta karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016.
Namun, di balik vonis itu, mencuat satu pertanyaan fundamental: di mana letak mens rea atau niat jahat dari seorang pejabat negara yang menjalankan kebijakan?
Kritik utama tertuju pada absennya pertimbangan terhadap unsur mens rea dalam pertimbangan majelis hakim. Padahal, baik secara teori maupun praktik, niat atau sikap batin pelaku adalah salah satu elemen pokok dalam hukum pidana.
Tanpa niat jahat, pemidanaan kehilangan fondasi moralnya. Lebih jauh, keputusan ini berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap setiap pengambilan kebijakan publik yang menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
Majelis hakim menyebut Tom Lembong bersalah karena menerbitkan surat persetujuan impor tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian.
Namun tidak pernah dijelaskan apakah kebijakan tersebut dilandasi kehendak jahat atau keuntungan pribadi. Tidak ditemukan pula bukti bahwa Tom menerima suap, gratifikasi, atau imbalan dari perusahaan yang memperoleh izin impor.
Prinsip dasar hukum pidana mengenal adagium “actus non facit reum nisi mens sit rea”—sebuah tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat di baliknya.
Di sistem hukum Anglo-Saxon, adagium ini menjadi patokan dalam menentukan apakah sebuah tindakan layak dipidana. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena perbuatannya, melainkan juga harus dibuktikan adanya kehendak untuk melanggar hukum.
Unsur mens rea tidak hanya berbicara soal niat jahat eksplisit. Ia juga mencakup kelalaian yang disengaja atau kekeliruan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam kasus Tom Lembong, absennya proses birokrasi bukan serta-merta menjadi bukti adanya itikad buruk.
Sebagai pejabat negara, Tom menjalankan diskresi kebijakan yang seharusnya berada dalam ruang kewenangannya, kecuali terbukti digunakan untuk memperkaya diri atau pihak lain secara melawan hukum.
Dalam banyak kasus tindak pidana, mens rea menjadi batas yang membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan.
Jika batas ini dihapuskan, maka semua kesalahan prosedural berpotensi dijerat pidana, termasuk kebijakan yang dibuat dengan itikad baik namun berdampak merugikan secara administratif. Ini adalah bahaya laten yang tidak hanya mengancam kebebasan individu, tetapi juga mengekang keberanian pejabat publik untuk mengambil keputusan strategis.
Putusan ini memperlihatkan kekhawatiran yang lebih besar: kaburnya garis pemisah antara kebijakan dan pidana. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri merupakan pembantu presiden yang diberi diskresi dalam menjalankan tugasnya.
Jika semua tindakan kebijakan dinilai berdasarkan tafsir prosedural semata, maka negara bisa terjebak dalam ketakutan birokratik yang stagnan.
Dengan menafikan unsur niat, vonis terhadap Tom Lembong meninggalkan preseden yang berbahaya. Ia menyamakan kesalahan administratif dengan kejahatan korupsi, padahal keduanya berangkat dari pijakan moral dan hukum yang sangat berbeda.
Pemidanaan seharusnya menjadi alat terakhir (ultimum remedium), bukan respons pertama terhadap setiap kegagalan tata kelola. Hukum pidana dibuat untuk menjerat niat jahat, bukan membungkam diskresi pejabat negara. Dan jika prinsip ini dilanggar, maka bukan hanya satu orang yang dikorbankan, melainkan keberanian para pengambil kebijakan secara keseluruhan.
Vonis terhadap Tom Lembong menunjukkan kekeliruan serius dalam penegakan hukum pidana, terutama karena mengabaikan unsur mens rea atau niat jahat. Padahal, dalam prinsip dasar hukum pidana, niat adalah fondasi utama yang membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan kriminal.
Tanpa pembuktian adanya kehendak jahat, pemidanaan terhadap pejabat yang menjalankan kebijakan berisiko menciptakan preseden berbahaya: kebijakan publik bisa dikriminalisasi.
Putusan ini bukan hanya soal nasib satu orang, tetapi mencerminkan kecenderungan hukum yang mulai bergeser dari asas keadilan substantif menuju tafsir sempit yang prosedural. Jika dibiarkan, hal ini akan mengekang ruang diskresi pejabat, menurunkan keberanian mengambil keputusan strategis, dan pada akhirnya melumpuhkan birokrasi negara.
Hukum pidana harus digunakan dengan hati-hati, bukan sebagai alat untuk menghukum kekeliruan administratif, tetapi untuk menjerat kejahatan yang disertai niat jahat. Sebab, keadilan bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi juga mengapa dan dengan maksud apa perbuatan itu dilakukan.