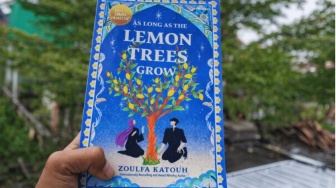Cerita tentang ibu dan anak itu nggak pernah benar-benar sederhana. Apalagi kalau sudah bicara tentang Malin Kundang. Sejak kecil, kita dicekoki kisah anak durhaka yang akhirnya dikutuk jadi batu. Seakan-akan semua dosa ada di pihak sang anak, sementara ibu ditempatkan di sisi yang ‘benar’ dan nggak tersentuh ‘salah’. Kita hafal kisah itu, bahkan mungkin menirukan kisahnya saat pentas di sekolah dasar dulu. Namun, pernahkah kita bertanya, “Benarkah segalanya sesederhana itu?”
Film Legenda Kelam Malin Kundang disutradarai Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo serta diproduseri Joko Anwar sekaligus menulis skripnya, tampaknya hadir untuk mengacak-acak logika berpikir kita dalam mengingat dongeng itu.
Di sini, hubungan ibu dan anak bukan lagi hitam-putih. Bukan sebatas soal siapa benar dan siapa salah. Ada lapisan lain yang lebih kompleks terkait trauma yang dialami para karakter, luka, amarah, bahkan cinta yang nggak pernah ‘selesai’ diungkapkan.
Alif Sang Malin Kundang?

Tokoh utamanya, Alif, dia pelukis micro painting. Seni melukis di ruang yang nyaris nggak terlihat. Kalau kita ngomongin micro painting, kanvasnya itu bisa sekecil butiran beras, kepala jarum, atau bahkan sepotong kuku. Lukisannya tetap detail. Ada wajah, ada pemandangan, bahkan ada ekspresi, tapi ukurannya kecil banget.
Profesinya terasa puitis sekaligus tragis, seolah-olah hidup Alif adalah kanvas kecil yang penuh detail, tapi ada satu ruang kosong yang nggak sanggup dia sentuh. Mungkin cinta seorang ibu.
Alif tiba-tiba kehilangan ingatan setelah kecelakaan. Dia punya istri dan anak. Namun, ketika ibunya datang, dia menolak untuk mengenali, menolak untuk menerima. Dan di situlah ketegangan sebenarnya dimulai. Apa yang membuat seorang anak begitu menolak ibunya sendiri? Apa yang pernah terjadi di masa lalu sehingga ingatan itu lebih baik dikubur daripada dihidupkan kembali?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bikin filmnya terasa jauh lebih relevan ketimbang sebatas kisah anak durhaka klasik. Karena faktanya, banyak dari kita hidup dengan luka yang dihasilkan orang tua.
Ada anak-anak yang belajar memendam sakit hati karena merasa nggak pernah didengar. Ada pula ibu-ibu yang tanpa sadar melukai, entah lewat kata, sikap, atau ambisi yang ditumpahkan ke pundak anak. Hubungan itu begitu intim, begitu dekat, sampai-sampai ketika retak, retaknya pun terdengar seperti gemuruh yang mengguncang jiwa.
Di sinilah Film Legenda Kelam Malin Kundang jadi lebih puitis sekaligus menakutkan. Ketika kisah lama dibawa ke dunia modern, makna ‘kutukan’ bisa berubah. Bukan lagi sekadar jadi batu di tepi pantai, tapi jadi jiwa yang membeku. Malin Kundang versi lama dihukum alam semesta. Malin Kundang versi baru mungkin dihukum ingatannya sendiri.
Dan menariknya, film ini seolah-olah ingin bilang, “Jangan buru-buru menghakimi! Ibu nggak selalu malaikat. Anak nggak selalu pemberontak yang nggak tahu diri.”
Paham, ya? Ada dinamika yang rapuh di antara hubungan anak dan orang tua. Saling menyayangi tapi juga saling melukai. Itulah realita yang jarang kita bicarakan, karena budaya kita lebih sering menuntut anak untuk patuh, sementara orang tua jarang diajak bertanggung jawab atas luka yang mereka tinggalkan.
Buatku, inilah sisi paling kuat dari ‘Legenda Kelam Malin Kundang’. Kayak menantang kita buat melihat lagi cerita lama dengan kacamata baru. Bahwa di balik kata ‘durhaka’, ada cerita panjang tentang luka batin, penolakan, dan cinta yang berubah jadi bayangan hitam.
Pada akhirnya, film ini mungkin akan membuat kita merenung tentang bagaimana hubungan kita dengan ibu. Apa yang selama ini kita simpan rapat-rapat, dan nggak pernah diucapkan? Dan yang lebih menakutkan lagi, berapa banyak Malin Kundang lain yang hidup di sekitar kita, bukan di batu karang, tapi di tubuh yang masih bernapas, di hati yang masih berdetak, tapi membatu akibat luka lama?
Dan bila Sobat Yoursay merasa perlu tahu kisah selengkapnya, sabar dulu sampai rilis 27 November 2025, ya!
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS