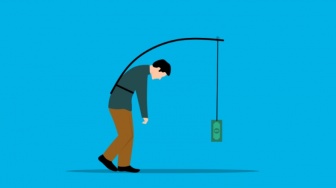Kolom
Demokrasi Digital, Kuasa Influencer dan Krisis Kepakaran

- Bahasa sederhana, kedekatan emosional, dan algoritma membuat opini mereka cepat viral.
- Netizen dituntut kritis agar popularitas tidak menggeser fakta dan kepakaran.
- Influencer kini lebih berpengaruh membentuk opini publik dibanding pakar.
Di era digital, ruang publik yang dulu didominasi media arus utama kini bertransformasi menjadi lanskap yang cair, cepat, dan personal. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi pembawa opini, dari komentar santai hingga analisis mendalam. Setiap unggahan, setiap video, dan setiap thread bisa menjadi sumber informasi yang memengaruhi cara orang berpikir dan bersikap.
Dalam konteks ini, influencer muncul sebagai figur sentral yang memiliki kuasa luar biasa atas opini publik. Likes, shares, dan komentar bukan sekadar metrik popularitas tetapi juga alat pengaruh. Opini mereka yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan gaya yang mudah dicerna, seringkali lebih cepat diterima daripada argumen panjang yang disampaikan oleh para pakar.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks demokrasi digital. Di satu sisi akses terhadap informasi semakin terbuka dan demokratis, di sisi lain kualitas dan kredibilitas informasi bisa tergerus oleh popularitas. Netizen yang awam dengan isu tertentu cenderung mengikuti figur yang mereka sukai atau yang populer, bukan yang ahli atau memiliki kapabilitas formal.
Hal ini menimbulkan krisis kepakaran karena opini publik lebih mudah terbentuk dari figur yang dikenal dan dipercaya secara personal, bukan dari mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam di bidang tertentu. Orang lebih percaya pada influencer daripada ilmuwan, ekonom, atau praktisi hukum meski isu yang dibahas sangat kompleks dan berdampak besar pada kehidupan publik.
Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya karena bahasa yang digunakan influencer mudah dicerna. Influencer mengemas isu yang kompleks menjadi narasi yang sederhana dan relatable. Mereka mampu menyampaikan pandangan dengan humor, emosi, atau gaya bercerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Sebaliknya, para pakar sering menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh publik luas. Hal ini membuat informasi dari sumber otoritatif terasa jauh dan tidak relevan bagi orang yang baru mengenal topik tersebut.
Selain itu, influencer membangun kedekatan emosional dan identitas dengan audiensnya. Mereka tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membentuk hubungan, menghadirkan pengalaman yang terasa personal. Audiens merasa mengenal mereka secara pribadi, merasa bisa berdiskusi, dan bahkan merasa ikut berperan dalam proses pemikiran influencer. Kedekatan ini sulit dicapai oleh para pakar yang biasanya tampil formal dan jarang hadir di ruang interaksi publik yang santai.
Kecepatan dan instanitas informasi di media sosial juga memainkan peran besar. Opini yang sederhana, catchy, dan mudah diingat lebih cepat viral daripada analisis mendalam yang membutuhkan waktu dan konsentrasi. Di saat yang sama, algoritma platform cenderung mendorong konten yang memicu reaksi emosional dan interaksi cepat, bukan konten yang menuntut pemikiran kritis dan analisis mendalam. Ini semakin memperkuat dominasi influencer sebagai pembentuk opini publik.
Situasi ini menuntut netizen untuk bersikap lebih kritis. Tidak semua yang viral atau populer layak dipercaya. Memeriksa sumber informasi, mengevaluasi kredibilitas pembicara, dan memahami konteks isu menjadi langkah penting. Netizen perlu menumbuhkan kebiasaan mempertanyakan apakah opini ini berdasar data dan fakta, apakah pembicara memiliki kapasitas untuk memberikan analisis mendalam, dan apakah ada bias atau konflik kepentingan yang memengaruhi sudut pandang mereka. Sikap kritis ini bukan berarti menolak semua opini influencer tetapi mampu memilah mana yang informatif dan mana yang sekadar menarik perhatian.
Krisis kepakaran ini juga terkait dengan budaya digital yang lebih menghargai sensasi dan popularitas daripada kompetensi. Di banyak kasus, orang lebih cepat membagikan opini yang menghibur atau menggerakkan emosi daripada opini yang berdasarkan fakta dan analisis.
Fenomena ini membuat orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam menjadi kurang terdengar, sementara orang yang populer secara sosial mampu membentuk opini publik dengan cepat. Dampaknya bukan sekadar miskomunikasi tetapi juga potensi manipulasi opini publik dalam isu-isu penting seperti politik, ekonomi, atau hukum.
Demokrasi digital memberi kebebasan tetapi juga menuntut tanggung jawab intelektual. Jika publik tidak mampu bersikap kritis, opini publik akan semakin mudah dimanipulasi, dan ruang demokrasi justru tergerus oleh logika popularitas bukan logika rasional dan fakta.
Netizen perlu belajar bahwa popularitas tidak selalu sejalan dengan kebenaran dan kredibilitas. Mengikuti influencer sah-sah saja, tetapi tanpa kemampuan menilai informasi secara kritis, opini publik bisa diseret ke arah yang salah dan membahayakan proses pengambilan keputusan yang rasional di masyarakat.
Tantangan besar bagi kita semua adalah menyeimbangkan kebebasan digital dengan kecerdasan kritis, menghormati opini populer sekaligus menghargai kepakaran. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa paling banyak didengar tetapi tentang siapa yang paling mampu menghadirkan kebenaran dan pemahaman yang memadai.
Influencer bisa menjadi bagian dari ekosistem informasi tetapi kepakaran tidak boleh tersingkirkan oleh popularitas semata. Netizen yang kritis dan sadar kapasitas sumber informasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Mereka mampu menikmati informasi yang populer tanpa kehilangan kemampuan menilai, menyaring, dan memilih apa yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.