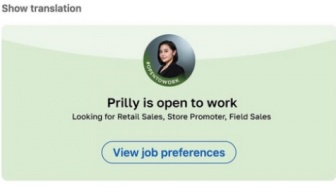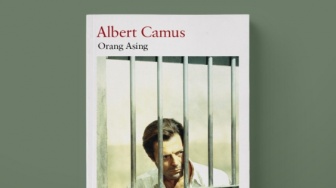Sekolah dan kampus sejatinya adalah tempat yang aman, tempat setiap individu bisa belajar, tumbuh, dan dihargai apa adanya. Tapi ketika perundungan (bullying) masih terus terjadi, rasa aman itu menjadi pertanyaan besar, masih adakah ruang yang benar-benar aman di dunia pendidikan kita?
Kasus tragis yang menimpa TAS, mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal dunia diduga akibat perundungan, kembali membuka luka lama. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Setiap kali tragedi seperti ini mencuat ke publik, kita marah, berduka, lalu perlahan melupakan. Reaksi publik selalu sama: heboh sesaat, namun jarang berubah menjadi kesadaran kolektif.
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, pada tahun 2023 tercatat 285 kasus kekerasan di dunia pendidikan, dan pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 573 kasus, naik lebih dari 100 persen. Dari angka itu, sekitar 31 persen terkait langsung dengan perundungan. Artinya, bullying masih menjadi bentuk kekerasan paling dominan di lingkungan sekolah dan kampus.
Sayangnya, setiap kali kasus mencuat, respons yang muncul sering hanya bersifat seremonial: dibentuk tim etik, dibuat peraturan baru, atau digelar seminar anti-bullying. Semua langkah itu penting, tapi tak menyentuh akar masalah sebenarnya. Bullying bukan sekadar perilaku buruk individu, ia adalah cermin dari krisis empati yang melanda masyarakat kita.
Budaya ejekan dan candaan yang merendahkan sudah terlalu lama dianggap biasa. Ucapan seperti “Bercanda kok baper” menjadi tameng untuk menutupi perilaku yang menyakiti. Padahal, di balik tawa, ada hati yang terluka. Banyak korban memilih diam karena takut dicap lemah. Luka itu tumbuh dalam diam, berubah menjadi tekanan batin, bahkan depresi. Di titik ini, kita sebenarnya sedang menghadapi masalah serius: hilangnya kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain.
Carl Rogers (1957) menyebut empati sebagai kemampuan untuk memahami pengalaman batin orang lain tanpa kehilangan jati diri. Daniel Goleman (1995) menekankan bahwa empati adalah kunci penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Sementara Hoffman (2000) menambahkan, empati mampu memicu perilaku prososial—dorongan untuk berbuat baik dan menolong. Empati bukan sekadar rasa kasihan; ia adalah kemampuan moral dan emosional yang menumbuhkan kepedulian.
Sekolah dan kampus semestinya menjadi tempat belajar tentang empati. Melalui interaksi sosial, contoh dari guru atau dosen, serta budaya saling menghargai, anak dan mahasiswa seharusnya dilatih untuk memahami perasaan orang lain. Namun ketika pendidikan hanya berfokus pada nilai dan prestasi akademik, aspek emosional sering terabaikan. Hasilnya, kita mencetak manusia pintar tapi tidak peka.
Krisis empati ini makin parah di era digital. Dunia maya kini menjadi arena baru bagi perundungan. Komentar jahat di media sosial, ejekan di grup chat, atau meme yang menghina sering dianggap lucu padahal menyakitkan. Dalam hitungan detik, satu ejekan bisa menyebar luas dan menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Bullying digital sering kali bahkan lebih berbahaya karena dampaknya bisa terus menghantui tanpa batas waktu.
Mencegah perundungan tidak cukup hanya dengan sanksi atau kampanye moral. Empati perlu ditumbuhkan sejak dini, melalui kebiasaan refleksi, dialog, dan kehadiran yang tulus. Kadang, tindakan paling sederhana seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi bentuk empati yang menyembuhkan. Tapi sayangnya, di dunia akademik yang sibuk mengejar target, kehadiran emosional seperti ini justru menjadi hal yang langka.
Tragedi seperti yang menimpa TAS seharusnya menggugah kesadaran kita bersama. Ini bukan sekadar kisah duka individu, tapi cermin dari sistem sosial dan pendidikan yang kehilangan rasa kemanusiaan. Kampus dan sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, melainkan ruang pembentukan karakter dan empati. Karena tanpa empati, ilmu hanyalah pengetahuan tanpa jiwa.
Pendidikan komunikasi empatik bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Mengajarkan siswa dan mahasiswa untuk mendengarkan dengan hati, menghormati perbedaan, dan memvalidasi perasaan orang lain adalah bagian penting dari proses belajar menjadi manusia seutuhnya. Guru, dosen, dan orang tua berperan besar sebagai teladan dalam hal ini.
Akhirnya, komunikasi empatik adalah lawan sejati dari perundungan. Ia mengajarkan kita untuk melihat manusia lain dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Empati bukan kelembutan yang lemah, tapi keberanian untuk memahami dan menjaga. Dan dari keberanian itulah, langkah kecil untuk menghapus bullying bisa benar-benar dimulai.