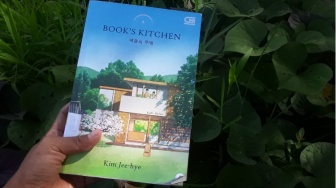Saya melihat ada satu fenomena menarik yang sejak lama telah dianggap “wajar”, padahal rasanya menggores hati. Fenomena itu bernama intergenerational bullying, atau perundungan antar generasi. Istilah ini terdengar asing, memang. Tapi sebenarnya, praktiknya sudah akrab kita alami dan rasakan sejak kita kecil, bahkan sejak pertama kali kita diberi tahu bahwa pendapat kita tidak sepenting pendapat orang dewasa.
Fenomena ini muncul ketika kelompok usia berbeda mulai dari Gen Z dan Milenial sampai Gen X dan Boomer—saling melempar candaan, sindiran halus, atau komentar soal kebiasaan dan karakter khas generasi masing-masing.
Biasanya bentuknya macam-macam. Di media sosial, lewat meme, video TikTok, atau tweet yang menonjolkan perbedaan cara ngomong, cara kerja, sampai selera hiburan antar generasi.
Lalu generasi milenial dan gen Z yang mengejek orang tua gaptek atau lambat adaptasi teknologi, sementara generasi yang lebih tua membalas dengan komentar tentang “mental anak sekarang”. Dalam obrolan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah, percakapan ringan sering berubah jadi saling sindir soal cara berpikir atau nilai-nilai yang berbeda.
Kenapa fenomena ini meskipun sering terjadi tapi sulit dibahas? Benar, kita bahkan tidak mengakuinya sebagai perundungan.
Banyak dari kita menyebutnya dengan istilah yang lebih halus dan lebih sopan baik ke generasi yang lebih muda maupun yang lebih tua, seperti:
“Beda zaman.”
“Beda pola pikir.”
“Kamu mentalnya lemah.”
Padahal, di dalamnya ada pola yang sama yaitu: merendahkan yang lebih muda, menganggap pendapat mereka kurang berharga, dan menggunakan perbedaan usia sebagai legitimasi. Sementara anak-anak muda menganggap generasi tua kolot, gaptek, dan sebagainya.
Perbedaan Usia sebagai Dalih Meremehkan
Sejak kecil, terutama di lingkungan saya tumbuh, banyak yang sudah hafal kalimat-kalimat seperti:
“Kamu masih kecil, diam dulu.”
“Dengarkan yang tua, kamu belum tahu apa-apa.”
Lama-lama, kita belajar bahwa diam saat diremehkan adalah standar sopan santun. Bahwa pendapat anak muda otomatis tidak valid hanya karena ia lahir lebih belakangan.
Dan anehnya, budaya ini terus diwariskan dan dianggap normal. Generasi yang lebih tua merasa generasi setelahnya lebih “payah” hanya karena hidup di zaman yang berbeda. Mereka melihat fasilitas, teknologi, dan akses yang lebih mudah lalu menyimpulkan bahwa generasi muda pasti hidupnya lebih enak.
Padahal, realitasnya jauh lebih rumit. Generasi muda — terutama Gen Z dan Gen Alpha — hidup dalam dunia persaingan yang lebih besar, ritme hidup yang lebih cepat, standar sosial yang lebih tinggi, dan ekspektasi yang lebih berat. Mereka tumbuh di tengah banjir informasi, krisis iklim, keresahan ekonomi, dan standar produktivitas tanpa henti.
Tetapi tetap saja, label itu menempel dan membentuk siklus yang terus diwariskan. Millennials dianggap “generasi gagal” oleh sebagian Gen X. Gen Z dianggap “lemah dan gampang baper.” Gen Alpha dianggap “susah diatur.”
Semua itu diucapkan dengan ringan, seolah mereka hanya bercanda. Padahal efeknya nyata dan menyakitkan. Sebaliknya, generasi yang terkena labeling menjadi tersulut dan punya kebencian terhadap generasi lain yang memberi perkataan-perkataan tersebut.
Media Sosial: Mesin yang Memperbesar Jurang
Seperti yang sudah kita tahu, saat ini media sosial justru memperbesar kemungkinan perilaku perundungan antar generasi ini. Karena konten-konten roasting antar generasi menjadi sangat empuk dan disukai.
Jika dulu perundungan antar generasi hanya terjadi di rumah atau kantor, sekarang media sosial memperkuatnya. Lihat saja bagaimana meme tentang “Gen Z fragile”, “Millennial cupu”, atau roasting antar generasi selalu viral. Begitu juga konten tentang Childfree vs Parenting, kerja kantoran vs WFH, semua jadi arena pertempuran.
Yang lebih mengerikan adalah, konten-konten roasting antar generasi di media sosial tersebut banyak yang dibungkus humor. Dan humor membuat kekerasan terlihat lucu, padahal dampaknya tetap saja menyakiti. Kita akhirnya menyerang satu sama lain sambil bersembunyi di balik identitas generasi, seolah-olah itu pembenaran.
Solusi: Mengubah Wacana Menjadi Dialog yang Sehat
Sebenarnya jika akar nya adalah untuk membangun, kritik antar generasi itu sama sekali tidak masalah. Karena tiap generasi punya kekurangan dan kellebihannya masing-masing. Generasi milenial dan Gen Z, misalnya, yang saat ini lebih melek parenting yang lebih gentle yang berdampak baik bagi mental.
Sebaliknya, generasi bawah juga harus belajar respek dan sopan untuk berkomentar dan bicara dengan yang lebih tua. Ketika kritik disampaikan untuk membangun, itu baik. Tetapi ketika kritik berubah menjadi meremehkan, itulah yang menjadi masalah.
Solusi utamanya bukan memilih siapa yang paling benar, tapi bagaimana menghadirkan mutual respect. Tentu saja, ini bisa dilakukan dari rumah, misalnya dengan membangun budaya diskusi yang menghargai pendapat tanpa memandang usia. Di mana anak muda belajar menyampaikan argumen tanpa defensif. Sementara orang tua belajar mendengarkan tanpa merasa dikoreksi.
Hal sederhana seperti itu sebenarnya bisa mengubah banyak hal. Karena ketika sebuah keluarga mulai berdialog tanpa saling meremehkan, generasi setelahnya otomatis lebih sehat dalam memperlakukan orang lain. Begitu juga dengan rasa benci antar generasi juga tidak akan sebesar itu
Jadi, gap usia sebenarnya bukan alasan untuk saling merendahkan dan perbedaan generasi bukan untuk dipertentangkan, tapi bagaimana saling memahami melalui dialog yang sehat.