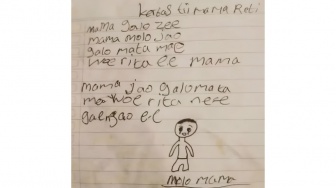Dalam tiga semester terakhir, saya rutin memberi tugas kepada mahasiswa untuk menonton film Istirahatlah Kata-Kata. Setelah itu, mereka diminta menganalisisnya menggunakan perspektif sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Tujuan saya sederhana—agar film ini tidak sekadar dipahami sebagai karya seni atau arsip sejarah, melainkan sebagai refleksi etis tentang kemanusiaan dan kekuasaan.
Namun, respons mahasiswa kerap membuat saya terdiam.
Sekitar tiga puluh menit setelah film diputar, saya biasanya bertanya, “Bagaimana, filmnya bagus atau tidak?”
Mayoritas menjawab singkat, datar, tanpa antusiasme. Ada pula yang jujur mengatakan, “Bosan, Pak. Kami kurang mengerti alurnya.”

Alih-alih kecewa, saya justru mengapresiasi kejujuran itu. Dari situlah saya menyadari bahwa masalahnya bukan semata pada film, melainkan pada jarak generasi muda dengan konteks sejarah yang melingkupinya.
Istirahatlah Kata-Kata karya Yosep Anggi Noen bukan film biografi konvensional. Minim dialog, penuh jeda, dan sunyi. Ia merekam masa pelarian Widji Thukul di Pontianak, setelah peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996—salah satu episode represi politik Orde Baru menjelang kejatuhannya.
Film ini berbicara tentang ketakutan, keterasingan, dan keberanian, bukan lewat narasi verbal, melainkan melalui kesunyian.
Beberapa puisi Widji Thukul dibacakan dalam film. Namun, bagi banyak mahasiswa, nama Widji Thukul tetap terasa asing. Puisinya pun tidak membekas, apalagi dikenali. Di titik inilah pertanyaan penting muncul: mengapa sosok dan karya sepenting itu nyaris tak dikenal oleh generasi muda?
Jawabannya barangkali sederhana sekaligus mengkhawatirkan. Widji Thukul dan karya-karyanya tidak diwariskan secara sistematis dalam pendidikan formal.
Berbeda dengan Chairil Anwar yang akrab lewat buku pelajaran, puisi-puisi Widji Thukul nyaris absen dari kurikulum. Padahal, secara historis dan tematis, puisinya merekam pengalaman kemanusiaan yang getir—tentang ketidakadilan, represi, dan perlawanan warga negara terhadap kekuasaan.
Ironisnya, kondisi tersebut tetap terjadi meskipun salah satu kawan seperjuangan Widji Thukul, Hilmar Farid, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.
Setahu saya, salah satu kebijakan penting pada masa itu adalah penayangan film Istirahatlah Kata-Kata di TVRI melalui program Belajar dari Rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 16 Juni 2020. Namun, ketika saya menanyakan hal ini kepada mahasiswa—yang sebagian besar lahir setelah tahun 2000—hampir semuanya menyatakan belum pernah menonton film tersebut.
Ini menandakan bahwa persoalannya bukan hanya soal minat, tetapi soal terputusnya pewarisan ingatan. Tanpa pengenalan yang memadai, karya-karya yang lahir dari pergulatan kemanusiaan berisiko menghilang dari kesadaran generasi berikutnya.
Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika kita meletakkannya dalam konteks politik mutakhir. Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintahan Prabowo, misalnya, menghadirkan dilema etis dan pedagogis.
Secara administratif sah, tetapi secara moral memunculkan pertanyaan: bagaimana mengajarkan puisi-puisi perlawanan Widji Thukul secara jujur, ketika simbol utama kekuasaan yang dilawannya kini diberi gelar kehormatan negara?
Setelah presentasi mahasiswa, saya selalu mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah penculikan aktivis dan penghilangan paksa sejalan dengan sila kedua Pancasila?
Jawaban mereka hampir selalu sama: tidak. Kedua, bagaimana pandangan mereka terhadap penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menggiring pada kesimpulan tunggal. Ia justru dimaksudkan agar ruang pendidikan tetap menjadi tempat dialog kritis—tempat nilai kemanusiaan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diperdebatkan secara sadar.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang tersisa dari film Istirahatlah Kata-Kata bukan hanya soal Widji Thukul atau Orde Baru.
Ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar: apakah kita sungguh-sungguh merawat nilai kemanusiaan dalam pendidikan dan kebijakan publik, atau hanya mengulangnya sebagai kata-kata indah yang boleh—dan mudah—dilupakan.