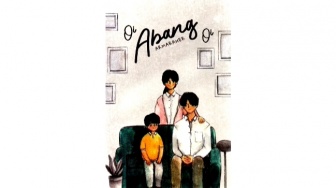Baru-baru ini viral kasus yang menimpa dari artis cantik Aurélie Moeremans. Artis cantik tersebut viral karena merilis buku yang berjudul Broken Strings. Broken Strings sendiri merupakan buku bergenre reflektif emosional yang ditulis Aurelie Moeremans sebagai ruang ekspresi atas pengalaman hidup, relasi, luka batin, dan proses penyembuhan diri.
Akibat itu, tentu kasus yang menimpa Aurilie beberapa waktu lalu kembali membuka mata publik tentang satu kejahatan yang selama ini sering luput disadari yakni, child grooming. Bukan penculikan, bukan kekerasan yang datang tiba-tiba, melainkan proses manipulasi perlahan yang dibungkus perhatian, empati, dan rasa aman palsu. Kasus Aurilie menjadi pengingat pahit bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing yang tampak mencurigakan.
Definisi Child Grooming
Dilansir dari siloamhospitals.com, Child Grooming adalah tindakan di mana orang dewasa membangun hubungan, kepercayaan, dan kendali atas seorang anak atau remaja dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara fisik, emosional, atau seksual. Dalam kasus seperti itu, pelaku juga dapat mengisolasi atau bahkan menyalahgunakan korban.
Sangat penting untuk menyadari perilaku child grooming, hal ini karena seringkali menjadi langkah awal menuju pelecehan seksual, radikalisasi, dan eksploitasi kriminal atau seksual terhadap anak-anak. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan anak.
Child Grooming adalah Tindakan yang Terencana
Child grooming adalah strategi terencana. Pelaku punya strategi untuk punya tindakan-tindakan berbahaya. Pelaku akan membangun relasi emosional dengan anak. Caranya pun beragam, mereka akan mulai mengobrol intens, memberi dukungan, hadiah, atau validasi hingga korban merasa memiliki ikatan khusus. Layaknya yang ada dalam kasus Aurilie, relasi tersebut berkembang tanpa disadari sebagai bentuk kejahatan. Di sinilah letak bahayanya, bagaimana kemudian grooming bekerja di wilayah psikologis, bukan fisik.
Yang menjadi masalah kemudian di zaman ini adalah Ruang digital. Hal ini dikarenakan dengan adanya ruang digital aka semakin mempercepat dan mempermudah praktik ini. Tak bisa dipungkiri bahwa media sosial, aplikasi pesan, hingga platform hiburan daring membuka ruang komunikasi privat yang sulit diawasi.
Akibatnya adalah anak-anak, yang secara emosional masih berkembang, rentan terjebak dalam relasi yang tampak aman namun sebenarnya timpang. Pelaku memahami betul cara membaca kebutuhan emosional anak. Bagaimana mereka menangani emosi anak dalam berbagai hal seperti kesepian, kebutuhan akan perhatian, atau keinginan untuk didengar.
Waspada kasus Child Grooming
Ada satu hal yang menurut penulis harus diubah ketika mendengar kasus child grooming ini. Bagaimana kita harus bereaksi, menurut penulis ketika ada kasus yang seperti ini reaksi publik kerap bergeser ke arah yang keliru dan itu harus diubah.
Mempertanyakan korban bagaimana korban bisa mudah diperdaya ataupun mengapa tak melaporkan lebih awal harus disudahi. Padahal, kita sendiri sudah paham bahwa child grooming justru bekerja dengan menumpulkan kewaspadaan korban. Rasa percaya itu bukan kesalahan anak, melainkan hasil manipulasi yang disengaja oleh pelaku.
Yang juga perlu digarisbawahi, grooming tidak selalu berujung pada kekerasan fisik secara langsung. Banyak korban mengalami tekanan psikologis berkepanjangan, rasa bersalah, takut, dan kebingungan. Dalam banyak kasus dampak tersebut terasa jelas, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada keluarga yang menyadari bahwa ancaman bisa masuk tanpa disadari dari ruang mana saja termasuk ruang digital.
Masalah ini diperparah oleh budaya tabu dalam membicarakan seksualitas dan relasi sehat di Indonesia. Pendidikan seks masih sering disalahpahami sebagai sesuatu yang "tidak pantas" padahal justru menjadi alat perlindungan. Anak yang memahami batasan tubuh, consent, dan relasi kuasa akan lebih mampu mengenali situasi berbahaya.
Orang tua dan pendidik pun perlu beranjak dari pendekatan kontrol menuju komunikasi. Larangan keras tanpa dialog hanya akan mendorong anak mencari tempat aman di luar rumah. Hal ini bisa saja justru menjadi pintu masuk pelaku grooming.
Belajar dari kasus Aurilie menunjukkan betapa pentingnya ruang aman bagi anak untuk bercerita tanpa takut dihakimi.
Kehadiran Negara yang Punya Dampak Penting
Di sisi lain, negara dan platform digital tidak bisa lepas tangan. Penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital masih sering lambat dan berbelit. Sistem pelaporan yang tidak ramah korban membuat banyak kasus berhenti di tengah jalan.
Selain itu, dalam hal ruang digital yang menjadi permasalahan adalah mereka harus lebih bertanggung jawab. Tepatnya untuk bukan sekadar menyediakan fitur, tetapi juga memastikan perlindungan nyata bagi pengguna anak.
Bagi penulis, kasus child grooming seharusnya tidak hanya berhenti sebagai sebuah keviralan. Kasus-kasus ini harusnya menjadi alarm keras bahwa child grooming nyata, dekat, dan bisa menimpa siapa saja. Kejahatan ini memang sunyi, tetapi dampaknya panjang. Jika kita terus menormalisasi kelengahan dan menyalahkan korban, yang kita lakukan hanyalah memberi ruang lebih luas bagi pelaku.
Melindungi anak bukan berarti mengurung mereka dari dunia luar ataupun dunia digital, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan, kepercayaan, dan sistem yang berpihak.