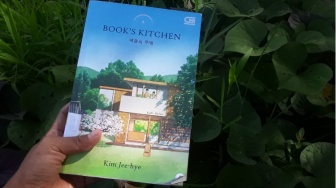Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kabar usulan wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Sebagai tanggapan pun, banyak aksi dan suara yang disampaikan sebagai sebuah bentuk penolakan. Salah satunya, ada aksi ratusan mahasiswa di Jawa Timur yang menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD bukan sekadar unjuk rasa rutin.
Aksi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat adalah sebuah cerminan dari kegelisahan publik yang luas. Penulis merasa bahwa ada rasa kekhawatiran dari publik akan mundurnya kualitas demokrasi di tengah narasi efisiensi biaya politik. Di titik inilah perdebatan Pilkada kembali menemukan relevansinya.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa baru-bari ini ada wacana Pilkada lewat DPRD yang kembali mengemuka. Banyak faktor wacana ini dibentuk, namun penulis ingin menyoroti alasan klasik yang diberikan yakni biaya pemilu yang mahal.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan semata soal anggaran, melainkan soal siapa yang seharusnya memegang kedaulatan dalam memilih pemimpin daerah.
Efisiensi Bukan Alasan Menghapus Hak Politik
Tidak dapat dipungkiri, Pilkada langsung memang menelan biaya besar, baik bagi negara maupun kandidat. Politik uang, konflik horizontal, dan logistik yang rumit sering dijadikan argumen pembenar untuk mengusulkan sistem tidak langsung. Namun, efisiensi administratif tidak bisa dijadikan alasan untuk memangkas hak politik warga.
Hak memilih pemimpin secara langsung adalah salah satu capaian penting reformasi. Mengembalikan kewenangan tersebut ke DPRD berarti menggeser kedaulatan dari rakyat ke elite politik. Di sinilah letak kekhawatiran masyarakat terjadi. Masyarakat merasa bahwa demokrasi berisiko direduksi menjadi sekadar prosedur elit, bukan partisipasi publik.
Trauma Politik Transaksional
Penolakan terhadap Pilkada via DPRD juga tidak lahir dari ruang hampa. Indonesia pernah mengalami fase di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif. Hasilnya bukan efisiensi yang bersih, melainkan praktik lobi tertutup, transaksi politik, dan akuntabilitas yang kabur.
Aksi dari mahasiswa hingga penolakan dari masyarakat seakan mengingatkan bahwa masalah utama bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas sistem politik. Jika DPRD masih dipersepsikan sebagai ruang kompromi kepentingan partai, sulit meyakinkan publik bahwa Pilkada tidak langsung akan lebih sehat.
Demokrasi Mahal, Tapi Otoritarianisme Lebih Mahal
Argumen bahwa demokrasi itu mahal sering kali benar, tetapi tidak pernah lengkap. Demokrasi memang membutuhkan biaya, namun biaya sosial dan politik dari melemahnya demokrasi jauh lebih besar. Ketika rakyat merasa suaranya tidak lagi menentukan, apatisme politik meningkat dan jarak antara pemerintah dan warga makin lebar.
Dalam jangka panjang, demokrasi yang kehilangan partisipasi justru menciptakan instabilitas. Ketidakpercayaan publik bisa berubah menjadi resistensi sosial yang lebih mahal daripada anggaran Pemilu itu sendiri.
Alih-alih mengembalikan Pilkada ke DPRD, pemerintah dan DPR seharusnya lebih serius membahas alternatif lain. Ada banyak cara seperti Digitalisasi Pemilu, penguatan pengawasan dana kampanye, hingga pengetatan sanksi politik uang adalah opsi yang jarang dibahas secara konsisten.
Mahasiswa sebagai Penjaga Nalar Publik
Aksi mahasiswa hingga penolakan dari masyarakat seakan menunjukkan peran penting sebagai penjaga nalar demokrasi. Di saat elite politik berbicara soal efisiensi dan stabilitas, mahasiswa dan masyarakat mampu mengingatkan soal prinsip dan nilai.
Penolakan ini bukan berarti menutup ruang diskusi, melainkan menuntut agar diskusi tidak melupakan esensi demokrasi itu sendiri, yakni, kedaulatan rakyat. Selama wacana Pilkada tidak langsung masih berpotensi menggerus hak pilih, resistensi publik akan terus muncul.
Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan, penulis merasa bahwa pilkada bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan cerminan relasi negara dengan warganya.
Jika demokrasi dianggap terlalu mahal, mungkin yang perlu dievaluasi bukan sistemnya, melainkan cara negara mengelolanya.