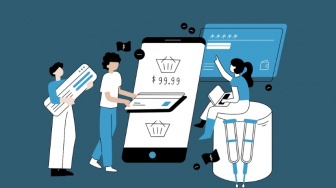Memasuki tahun 2026, perang genderang terhadap ketergantungan pangan asing ditabuh lebih ketat dari sebelumnya. Pemerintah dengan percaya diri memperbaiki target swasembada pangan total, mulai dari beras, jagung, hingga gula.
Namun, di tengah riuh rendahnya optimisme birokrasi, ada kegelisahan yang nyata di akar rumput. Sebagaimana dilansir Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), ambisi swasembada pangan di Indonesia sering kali terjebak pada angka-angka statistik semu, sementara kesejahteraan petani dan keberlanjutan lahan justru semakin terpinggirkan akibat kebijakan yang bersifat top-down.
Kita harus jujur bertanya dengan nada yang paling kritis, "untuk siapa sebenarnya swasembada ini dirancang?"
Jika tujuannya adalah ekologi, maka seharusnya instrumen pertama yang diperkuat adalah manusia yang memegang cangkul dan mengelola lumpur, bukan sekadar mengganti impor dengan proyek mercusuar mencetak lahan baru (food estate) yang berulang kali membahas kegagalan ekologis di berbagai wilayah.
Menutup keran impor adalah langkah yang tampak gagah di podium pidato, namun tanpa kesiapan basis produksi dalam negeri yang mumpuni, kebijakan ini tak mengubahnya "membunuh diri" ekonomi yang akan memicu inflasi harga pangan secara gila-gilaan di pasar domestik.
Realitas di lapangan jauh dari kata manis serupa yang dijelaskan dalam laporan-laporan kementerian. Saat pemerintah bermimpi tentang swasembada, konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, jalan tol, dan perumahan elit terus melaju tanpa rem yang pakem.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemandirian pangan, jika setiap tahun, ribuan hektar sawah pinggiran kota di Jawa, justru bersalin rupa menjadi beton-beton bisu?
Petani kita saat ini bukan hanya kekurangan lahan, tetapi juga dihimpit oleh mahalnya harga pupuk dan benih yang kualitasnya sering kali tidak konsisten. Ironisnya, ketika panen raya tiba, harga sering kali jatuh, namun ketika paceklik, mereka tetap tidak menikmati keuntungan karena harga diatur oleh tengkulak.
Lebih tajam lagi, narasi swasembada pangan tahun 2026 ini seolah hanya mengejar target kuantitas demi memuaskan ego politik. Kita dipaksa untuk memproduksi satu atau dua jenis komoditas secara masif, tetapi berdampak terhadap diversitas pangan lokal yang jauh lebih berkelanjutan.
Obsesi berlebihan pada beras telah membuat kita lupa, bahwa nusantara memiliki kekayaan pangan fungsional lain seperti sagu, jagung, sorgum, dan umbi-umbian. Pangan-pangan lokal ini sebenarnya jauh lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang tidak dapat diubah.
Memaksakan swasembada satu jenis komoditas dengan cara-cara industri, justru membuat sistem pangan kita rapuh terhadap serangan hama dan anomali cuaca ekstrem yang kini menjadi ancaman nyata di depan mata.
Selain itu, perlu dialamatkan pada rantai distribusi pangan kita yang masih dikuasai oleh segelintir pemain besar atau mafia pangan. Swasembada tanpa pembenahan tata niaga yang radikal hanyalah cara lain untuk menggemukkan kantong para spekulan.
Kita sering menyaksikan paradoks yang menyakitkan seperti, petani tetap menjual hasil buminya dengan harga murah yang nyaris tidak menutupi biaya produksi, sementara konsumen di perkotaan harus menjerit karena harga di rak supermarket tetap melambung tinggi.
Jika rantai distribusi yang panjang dan eksploitatif ini tidak diubah secara revolusioner, maka kata "swasembada" hanya akan menjadi jargon politik yang manis di telinga namun tetap terasa hambar di lidah masyarakat bawah.
Sudah saatnya kita berhenti memuja angka produksi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan pertanian. Swasembada pangan yang sejati hendaknya diukur dari sejauh mana petani kita mampu tersenyum karena harga jual yang layak, sejauh mana regenerasi petani muda terjadi, dan sejauh mana rakyat bisa mengakses makanan bergizi tanpa harus menguras seluruh isi kantong.
Jangan sampai demi mengejar gengsi "bebas impor" di mata dunia, kita justru mengabaikan tangisan mereka yang selama ini memberi kita makan tetapi sering kali tidak mampu membeli makanan yang mereka tanam sendiri.
Kebijakan pangan 2026 haruslah membumi dan menyentuh kenyataan sosial, bukan sekadar mimpi di atas kertas kerja para birokrat yang jarang turun ke pematang sawah.
Jika pemerintah gagal menjembatani antara ambisi kedaulatan dan realitas kepemilikan lahan petani, maka swasembada ini tidak lebih dari sekadar fatamorgana—terlihat indah dari jarak jauh baliho politik, namun terasa kering, palsu, dan menyesakkan saat didekati secara nyata. Kita butuh kedamaian, bukan sekadar statistik yang dipaksakan.