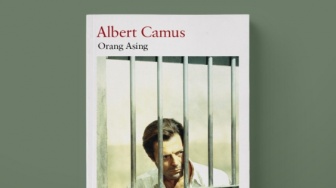Malam telah mencapai pertengahannya. Tanda waktu telah menunjukkan pukul 24.00.
Rinai-rinai hujan pun mulai turun, menambah kelamnya malam ini.
Sementara gerbang-gerbang kota,sejak beberapa jam lalu telah tertutup. Demi membatasi pergerakan manusia yang lalu lalang.
Aku menanti dengan harap-harap cemas kepulangan suamiku sedari tadi. Semoga malam ini ada sebungkus nasi yang bisa mengganjal perut kami
Kulihat si sulung telah tertidur. Sedari tadi ia mengeluhkan rasa lapar. Meski hancur hati ini mendengar pengakuannya, aku hanya bisa membesarkan hatinya.
Kupalingkan pandanganku pada si bungsu. Bayiku yang baru berumur beberapa bulan. Ia juga telah tertidur, kelelahan. Kecapekan karena rewel.
Sedari tadi ASI ku telah mengering. Mungkin karena itulah penyebab ia rewel.
Jujur, sudah beberapa hari ini aku dan suami sering kebingungan bagaimana akan menjalani hari-hari kami.
Beras, lauk, harus kami beli pakai uang dari mana?
Listrik, PDAM, kontrakan, harus kami bayar pakai apa?
Terlebih kebutuhan anak-anak kami, harus dipenuhi dengan cara seperti apa?
Apalagi jika salah satu dari kami sakit. Sungguh pusing untuk memikirkannya.
Belumlah lagi hutang-hutang lain yang minta segera dilunasi. Hanya bisa mengelus dada.
Entah sampai kapan situasi seperti ini harus kami jalani. Sungguh berat.
Orang-orang besar kebanyakan hanya bisa menyalahkan kami orang kecil. Katanya kami penyebab kerumunan.
Padahal kami hanya mencari receh demi receh untuk sekadar menyambung hidup.
Kami berteriak meminta para penguasa untuk mengulurkan tangan menolong kami. Tapi apa yang kami dapat? Sebuah pengkhianatan yang kami terima.
Hanya Tuhanlah yang tersisa bagi kami.
Hanya Dia yang memahami situasi kami.
Maka, beberapa saat sebelum suamiku pulang, cepat-cepat aku menuju ke jalan depan gang kontrakan kami.
Kubawa beberapa sisa kaleng cat pilok milik suamiku.
Di bawah rintik-rintik hujan, kutorehkan rangkaian huruf ke tembok besar di dekat jalan.
Huruf-huruf itu mewakili gundah gulanaku.
"Tuhan, anakku lapar!"