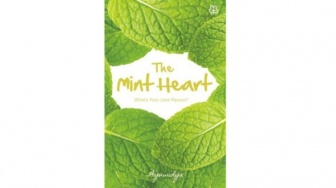Kami benar-benar kembali ke rumah ini setelah lima tahun menolak untuk menengok lagi. Daun pintu jati berukiran sulur tidak lagi mengkilap seperti dulu sebab debu menjadi saksi ketiadaan orang dalam jangka waktu yang lama di sini.
Dua kursi kayu dan satu meja bundar teronggok begitu saja di depan jendela yang senantiasa tertutup. Bunga telang yang dulu dirawat Nini kini sudah menjadi liar, nyaris menutup hampir keseluruhan tempayan tempat aku dulu dimandikan saat kecil. Rumah ini benar-benar mati bersama kepergian Nini lima tahun silam.
Kami pernah menghidupi rumah ini layaknya surga yang akan jadi peristirahatan di akhirat nanti. Semburat matahari terbit dan tenggelam merembet dari celah jendela yang selalu dibiarkan terbuka menjadi tanda bahwa kami benar-benar hidup dalam kedamaian.
Asap yang mengepul dari tungku di dapur selalu berhasil menghangatkan kami sebab itulah tanda Nini sedang memasak sesuatu.
Lalu tibalah hari ketika kami menyadari Nini bukan makhluk abadi. Kepergian Nini bakda subuh menjadi kabar duka yang mendadak.
Nini jatuh dalam pelukan hawa dingin bulan Agustus yang menusuk tulang rusuk hingga ke jantungnya. Membiarkan ia kesakitan menemui ajal saat tak ada seorang pun di antara kami yang duduk bersamanya.
Begitulah kematian Nini menjadi trauma mendalam bagi keluarga kami sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, rumah ini dibiarkan tertinggal begitu saja.
Dan di sinilah aku, berdiri di depan daun pintu yang sudah tampak begitu rapuh. Motif kembang sulur yang dulu selalu menarik perhatian kini justru memantik rasa prihatinku.
Kami telah begitu lama membiarkan rumah ini berdiri dalam kedinginan, kesunyian, dan kesendirian yang memuakkan. Bahkan Ibu dan Bapak yang mempersilakan diri mereka masuk ke dalam lebih dulu tidak berhasil menghidupkan kembali raga kosong itu.
Sama sepertiku yang juga enggan beranjak, kulihat Bapak berdiri di tengah ruang tamu yang biasa kami gunakan untuk bergurau dulu.
Sementara itu, Ibu sudah mondar-mandir membuka jendela yang kaku karena lama sekali tak tersentuh. Rumah ini bukan lagi tak berpenghuni, tapi hampir mati tertelan ketiadaan yang beradu sunyi.
"Sudah mantap, Bu?" tanyaku ketika melihat Ibu berdiri mematung di depan jendela yang daunnya baru saja terbuka.
Kulihat kembang melati terselip di antara gelungan rambutnya. Kebiasaan ini jelas turun dari Nini yang gemar mengumpulkan bunga melati yang sudah tanggal dari tangkai, lalu menjadikannya sebagai wewangian alami agar rambutnya tidak apak.
"Sudah sepakat harga, Nduk," balasnya sambil tersenyum simpul.
Genap lima tahun kepergian Nini rupanya menyisakan duka mendalam bagi Ibu. Rumah yang menjadi persinggahannya sejak lahir tidak lagi menghangatkan sebab kehadiran Nini terasa begitu hampa tanpa raganya.
Keputusan menjual rumah lantas terpikirkan saat Ibu datang bersilaturahmi ke rumah kakak tertua lebaran tahun lalu. Rumah itu menyimpan banyak cerita, tapi tak sanggup pula jika Ibu atau kerabat yang lain untuk merawatnya.
"Apa tidak sayang?" tanyaku lagi.
"Ibu bukan sekali dua kali berpikir ingin menjual rumah ini. Kepergian dan kematian Nini jadi babak terakhir rumah ini karena Ibu, Budhe, atau yang lain tak sanggup merawat. Lagi pula, sudah lima tahun tidak ada yang menghuni. Lama-lama rumah bagus seperti ini jadi jelek juga, kan?"
"Ibu nggak sayang sama kenangan di sini?"
Kulihat ia terdiam. Matanya tampak menerawang ke luar jendela, tepat di halaman rumah yang sama hampanya dengan di dalam sini. Di situlah Ibu dan Budhe dulu menghabiskan waktu dari pagi hingga malam.
Maka, bukan perkara mudah bagi mereka untuk melepas begitu saja rumah ini bersama dengan memori yang ada dalam setiap perjalanan langkah mereka di sini.
"Lebih menyakitkan mana dengan membiarkan rumah ini tidak pernah kita sambangi lalu rusak begini atau kita serahkan ke orang lain untuk dirawat?" begitu katanya sambil menatapku.
"Nduk," ia memegang pundakku. "Ada kalanya kita harus melepas sesuatu, termasuk masa lalu."
Usai berkata demikian, Ibu memberi pungkasan tanpa penjelasan panjang. Aku masih tertegun di depan daun jendela yang rupanya masih kokoh membingkai kenangan lama. Satu per satu kepingan memori yang sempat terpendam akhirnya muncul bagai riak ombak yang menghilang saat bersentuhan dengan pasir pantai.
Barangkali Ibu sama denganku. Enggan menyingkirkan segala kenangan yang terbentuk dalam rumah ini. Namun, tiada lagi yang bisa menyangkal masa depan sebab kami benar-benar harus memilih.
Kami benar-benar harus melanjutkan hidup, dengan atau tanpa kehadiran Nini dan rumah ini. Lagi pun, Nini akan tetap tinggal bersama kami dalam bayang-bayang langkah yang mengantarkan pada kehidupan abadi.
Pukul enam sore, mentari yang semula terik kini perlahan menghangatkan rumah dingin ini. Ia berpendar dari horizon di ujung barat menuju peristirahatan sebelum berganti rembulan.
Kepulangan kami ke rumah ini adalah perpisahan paling nyata. Ibu diam-diam menghabiskan waktu di kamar tengah, tempat yang dulu menjadi ruang pribadinya. Sementara itu, Bapak sudah duduk di teras sembari menyesap kopi hitam yang dibeli dari warung seberang.
Lantas aku menyadari bahwa pertemuan adalah kemustahilan, sedang perpisahan nyata adanya. Aku memilih bersandar pada daun pintu yang dibiarkan terus terbuka. Menyadari bahwa kehadiran kami adalah salam perjumpaan dan perpisahan antara masa lalu yang menyesakkan.
Kematian Nini adalah duka mendalam bagi kami. Melepas rumah ini rupanya cara Ibu untuk berpisah dan mengikhlaskan kepergian Nini sepenuhnya.