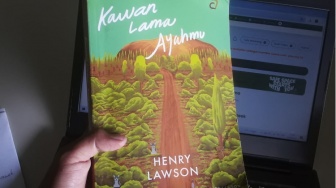Maya selalu membenci aroma karbol dan pemutih lantai. Baginya, aroma itu adalah bau kekalahan. Selama enam bulan terakhir, hidupnya menyempit di dalam kamar bernomor 402, sebuah ruangan putih pucat di mana waktu seolah berhenti berputar, kecuali pada monitor jantung yang terus berkedip gelisah.
Di atas ranjang itu, Adrian terbaring. Lelaki yang dulu gemar mendaki gunung dan tertawa hingga matanya menyipit itu kini tampak begitu asing. Kanker telah mencuri daging dari tulang-tulangnya, menyisakan kulit pucat dan napas yang harus dibantu oleh selang-selang dingin.
"Maya," bisik Adrian suatu sore, saat matahari senja menyelinap masuk melalui celah gorden. Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh desis mesin oksigen.
Maya segera menggenggam tangan Adrian yang dingin. "Aku di sini, Ndri. Jangan banyak bicara dulu."
Adrian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyayat hati Maya. "Jangan membenci hujan setelah aku pergi nanti. Berjanjilah. Karena setiap rintiknya adalah cara semesta menyampaikan pelukanku yang tak sampai."
Maya menggeleng kuat, air matanya jatuh tanpa permisi, membasahi punggung tangan Adrian. "Jangan bicara seolah kau akan pergi. Kita masih punya daftar tempat yang belum dikunjungi. Kau janji akan membawaku melihat kunang-kunang di kaki gunung, ingat?"
Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan binar mata yang redup namun penuh cinta. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adrian tidur dengan raut wajah yang sangat tenang. Begitu tenang, hingga pada pukul tiga dini hari, garis hijau di monitor jantung itu perlahan menjadi datar. Suara panjang yang melengking memenuhi ruangan, menandakan bahwa perjalanan Adrian telah selesai. Adrian pergi saat dunia sedang sunyi-sunyinya, meninggalkan Maya yang meraung dalam diam di pelukan perawat.
Dua minggu setelah pemakaman, rumah mereka terasa seperti gua hantu. Sunyi itu begitu berat, seolah memiliki beban tonase yang menekan pundak Maya. Setiap sudut ruangan adalah luka. Sikat gigi Adrian yang masih ada di gelas porselen, jaket denim yang masih menggantung di balik pintu, hingga aroma parfum kayu cendana yang mulai memudar dari bantal.
Maya terduduk di lantai kamar, di depan sebuah kotak kayu yang ditemukan di bawah tempat tidur Adrian. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat yang diberi tanggal untuk masa depan.
Ia mengambil satu surat teratas. Tertulis di sana: “Dibuka saat kau merasa rindu itu tak lagi tertahankan.”
Maya merobek amplopnya.
“Maya, cintaku. Maafkan tubuhku yang menyerah lebih dulu. Saat kau membaca ini, mungkin kau sedang marah pada Tuhan, atau mungkin kau sedang menatap kursi kosong di meja makan kita. Aku ingin kau tahu, mencintaimu adalah bagian terbaik dari hidupku yang singkat ini. Sakit ini memang merenggut fisikku, tapi ia tak pernah bisa menyentuh ingatanku tentang tawa kita.
Tolong, habiskan kopi yang aku tinggalkan di lemari. Pakai jaket denimku jika kau merasa kedinginan. Dan yang terpenting, teruslah hidup. Bukan karena aku ingin kau melupakanku, tapi karena aku ingin hidup melalui matamu.”
Maya terisak hebat, mendekap surat itu di dadanya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara rintiknya menghantam jendela, berirama dan konstan. Maya memejamkan mata, membiarkan dinginnya udara menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Adrian, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa dipeluk oleh hujan, persis seperti janji Adrian.
Adrian memang telah pergi, namun di setiap embusan napas Maya dan di setiap rintik yang jatuh ke bumi, cintanya akan tetap bergemuruh, abadi dalam kenangan yang takkan pernah usai.