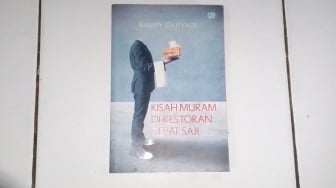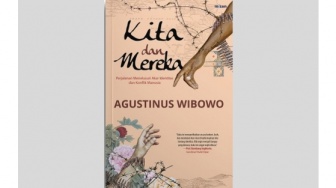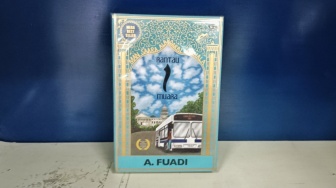Pagi itu, suara motor tua Pak Suratman terdengar pelan dari arah jalan. Biasanya ia berhenti tepat di depan rumah, di bawah pohon mangga yang daunnya mulai berguguran. Tapi kali ini, suaranya terhenti lebih jauh di ujung gang. Aku mengintip dari celah gorden, berharap melihat sosoknya membawa sepeda motornya ke sini. Namun, yang terlihat hanyalah sepeda tua milik Lani, tetangga sebelah yang terparkir di sana.
Aku duduk lagi di meja makan. Piring-piring kotor berserakan, bekas sarapan yang kulewatkan begitu saja. Teh di cangkir sudah dingin sejak tadi. Kupikir, dia akan datang hari ini. Tapi rupanya, suara motor itu bukan miliknya.
"Pintu depan belum kau tutup, Bu," kata Dira dari balik ruang tamu, matanya tak lepas dari layar ponsel yang terus ia gulirkan dengan cepat. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Seperti segala hal dalam rumah ini sejak beberapa minggu terakhir, hampa.
Aku menatap pintu yang dibiarkan sedikit terbuka, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dalam kepala, aku mendengar suaranya. "Kita tak pernah tahu siapa yang akan mengetuk pintu kita, kan?" Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan begitu ringan beberapa bulan yang lalu, ketika ia berdiri di sana, di ambang pintu, sebelum pergi membawa tas ransel besar di punggungnya.
Kini, suara pintu itu semakin jarang berbunyi.
"Aku akan menutupnya nanti," jawabku, nyaris tanpa sadar. Mata Dira masih melekat di layar ponselnya, sama sekali tak tertarik dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku tahu, ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Jarak yang mungkin sudah ada sejak awal, hanya saja baru sekarang terasa begitu nyata.
Dira semakin diam sejak ayahnya pergi. Tidak ada penjelasan, tidak ada janji kapan ia akan kembali. Hanya pesan singkat yang tak pernah terjawab. "Aku perlu waktu," begitu katanya, tiga bulan yang lalu. Dan waktu itu terasa seperti selimut tebal yang semakin membungkus kami dalam kebisuan.
Hari-hari berlalu seperti biasa. Ada yang berangkat ke sekolah, ada yang pulang membawa laporan yang sama setiap harinya. Ada piring yang tetap dicuci, lantai yang tetap disapu, dan gorden yang tetap dibuka setiap pagi. Namun, ada yang hilang dari kebiasaan itu. Sesuatu yang tak bisa kukembalikan, meski setiap sudut rumah ini masih mengenalinya.
"Dira, apa kau mau makan siang di luar nanti?" tanyaku, berharap bisa memecah keheningan di antara kami.
Dia hanya menggeleng pelan, tanpa memandangku. "Nggak. Aku mau di rumah aja."
Ada jeda di antara kata-katanya. Seperti jeda yang selalu muncul setiap kali ada pertanyaan tentang ayahnya. Aku menatapnya lama, melihat bayangan dirinya yang dulu, anak perempuan yang selalu bertanya tentang segalanya. Tentang bagaimana hujan terbentuk, mengapa burung bisa terbang, mengapa daun mangga berubah warna ketika musim kemarau. Tapi sekarang, pertanyaan itu tak lagi datang. Mungkin karena jawabannya tak lagi ia percaya.
Kepalaku terasa berat, seperti ada beban yang tak bisa kulenyapkan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Dira, rasanya selalu ada tembok tak kasatmata yang memisahkan kami. Bukan sekadar karena umurnya yang beranjak remaja, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang juga tak kumengerti sepenuhnya. Ia sedang kehilangan, seperti aku.
"Apa Ayah akan pulang?" tanya Dira tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang.
Pertanyaan itu sudah kutunggu sejak lama, tapi tetap saja, ketika ia benar-benar mengucapkannya, aku tak tahu harus menjawab apa.
"Ayah... mungkin sedang butuh waktu untuk sendiri," jawabku akhirnya, dengan suara yang bahkan terdengar ragu di telingaku sendiri.
"Mungkin atau pasti?" Dira mendongak, kali ini tatapannya benar-benar tertuju padaku. Mata itu—mata yang dulu penuh rasa ingin tahu, sekarang tampak lelah. Aku melihat pantulan diriku di sana, seseorang yang juga tak punya jawaban pasti.
Aku ingin menjawabnya dengan pasti, memberikan kepastian yang menenangkan, tapi aku tahu aku tak bisa. Tidak kali ini.
"Mungkin, Ra. Kadang, kita semua butuh waktu sendiri."
Dira tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali tenggelam dalam dunianya sendiri, meski aku tahu, pertanyaan itu masih ada di dalam kepalanya. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang selalu datang di malam hari, ketika rumah ini sunyi dan aku terjaga, menatap langit-langit kamar yang hampa. Aku tak bisa berhenti memikirkan ke mana dia pergi, apa yang membuatnya memilih pergi, dan apakah ada cara untuk membawanya kembali.
Tapi seberapa lama pun aku memikirkannya, jawabannya tetap tak pernah muncul.
Siang berganti sore, dan matahari mulai condong ke barat. Suara motor kembali terdengar dari jauh, kali ini lebih keras, lebih dekat. Aku beranjak dari meja makan, membiarkan piring-piring kotor tetap di sana. Hatiku berdebar-debar, meski aku tak tahu apa yang sedang kutunggu.
Pintu depan masih sedikit terbuka, seperti pagiku tadi. Dan ketika aku sampai di ambang pintu, mataku bertemu dengan seseorang di luar sana.
Bukan dia.
Pak Suratman datang membawa seikat sayuran segar di tangannya. "Ini dari kebun saya, Bu. Lumayan buat makan malam."
Aku tersenyum kecil, menutupi kekecewaan yang tiba-tiba menghantam. "Terima kasih, Pak."
Setelah mengambil sayuran itu, aku kembali ke dalam, menutup pintu perlahan. Kali ini, pintu benar-benar tertutup. Tapi entah mengapa, meski pintu sudah tertutup rapat, aku merasa masih ada sesuatu yang terbuka di dalam hatiku. Sesuatu yang menunggu untuk dijawab, meski jawabannya mungkin tak akan pernah datang.
***
Kuningan, 26 September 2024