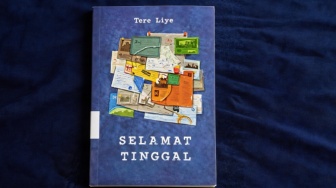Di sudut perpustakaan sekolah, buku-buku tebal berjajar rapi, bagai penjaga kuil pengetahuan yang diam-diam menanti siswa untuk membuka halamannya. Aroma kertas tua dan derit rak kayu menjadi saksi perjuangan siswa menyelami ilmu dari sumber yang terbatas.
Sementara itu, di dunia kampus, jurnal akademik online bagaikan lautan digital yang tak bertepi, menawarkan artikel-artikel mutakhir hanya dengan sekali klik.
Perbandingan antara buku perpustakaan dan jurnal akademik bukan sekadar soal media, melainkan cerminan perjalanan literasi informasi: dari langkah pelan di lorong-lorong berdebu menuju lari kencang di jagat maya.
Bagaimana kedua sumber ini membentuk cara siswa dan mahasiswa menyelami pengetahuan, dan apa artinya bagi kemampuan mereka menavigasi lautan informasi?
Buku perpustakaan, sebagaimana dijelaskan oleh Harisanty, Sugihartati, Srimulyo, dan Obille (2025) dalam Libraries in the Digital Age, do they survive?, menjadi fondasi awal literasi informasi bagi siswa sekolah.
Penelitian mereka menyoroti bahwa perpustakaan sekolah, meski terbatas oleh koleksi fisik, mengajarkan keterampilan dasar seperti mencari referensi, memahami struktur buku, dan mengevaluasi informasi.
Buku-buku teks, ensiklopedia, atau novel di perpustakaan sekolah bagaikan peta tua yang andal namun kaku—memberi landasan kokoh, tetapi sering tertinggal oleh arus perubahan zaman.
Siswa harus bersabar menelusuri indeks atau daftar isi, seperti penjelajah yang mencari harta karun di tengah hutan kertas. Proses ini, meski lambat, melatih ketelitian dan kesabaran, dua pilar penting dalam literasi informasi.
Sebaliknya, jurnal akademik online adalah pintu gerbang menuju pengetahuan yang serba cepat dan tak terbatas. Mahasiswa, dengan akses ke Google Scholar atau database universitas, bisa menyelami penelitian terbaru dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Jika buku perpustakaan adalah peta kuno, jurnal akademik adalah GPS modern—cepat, tepat, dan selalu diperbarui.
Seorang mahasiswa sosiologi, misalnya, bisa langsung mengakses artikel tentang dinamika media sosial, sementara siswa sekolah mungkin hanya menemukan buku teori dasar dari dekade lalu. Namun, kecepatan ini bukan tanpa risiko.
Harisanty dkk. (2025) menekankan bahwa banjir informasi digital menuntut literasi informasi yang lebih canggih, seperti kemampuan memilah sumber kredibel dari lautan artikel yang sering kali menyesatkan.
Literasi informasi, inti dari perbandingan ini, adalah seperti kompas yang menuntun pelancong di tengah badai pengetahuan. Di sekolah, buku perpustakaan mengajarkan dasar-dasar: cara membaca daftar pustaka, memahami struktur bab, atau merangkum isi. Proses ini, meski terasa kuno, membangun fondasi yang kuat, seperti akar pohon yang menancap dalam.
Namun, siswa sekolah sering terhambat oleh keterbatasan koleksi atau minimnya pelatihan untuk menilai kredibilitas sumber.
Mahasiswa, di sisi lain, dipaksa menyelam ke dalam lautan jurnal akademik, di mana mereka harus belajar membedakan artikel peer-reviewed dari opini biasa, seperti memisahkan mutiara dari kerikil.
Harisanty dkk. menegaskan bahwa literasi informasi yang baik memungkinkan pengguna untuk tidak hanya mengakses, tetapi juga menganalisis dan mensintesis pengetahuan, sebuah keterampilan yang krusial di era digital.
Namun, kemudahan jurnal online juga menyimpan jebakan. Mahasiswa sering kali tergoda untuk sekadar mengutip abstrak atau mengambil artikel pertama yang muncul di mesin pencari, seperti memetik buah yang tampak ranum tanpa memeriksa isinya. Ini adalah sindrom “Google Scholar pertama”, kecepatan mengalahkan kedalaman.
Sebaliknya, buku perpustakaan, dengan keterbatasannya, memaksa siswa untuk membaca secara menyeluruh, seperti menggali tambang dengan tangan kosong. Ironisnya, keterbatasan ini justru melatih ketekunan, sesuatu yang kadang hilang di tengah kemudahan digital.
Jurnal akademik menawarkan relevansi dan kecepatan, tetapi tanpa literasi informasi yang mumpuni, mahasiswa berisiko menjadi penutur ulang informasi, bukan pencipta wawasan.
Ada pula sisi emosional dalam kedua pengalaman ini. Perpustakaan sekolah, dengan keheningannya yang nyaris magis, sering jadi tempat siswa menemukan inspirasi di antara deretan buku, seperti menyelami cerita-cerita kuno di kuil pengetahuan.
Jurnal akademik, sebaliknya, sering diakses di tengah hiruk-pikuk kampus—di sela notifikasi ponsel atau deadline tugas—membuat proses belajar terasa lebih mekanis.
Namun, di sinilah letak keajaiban literasi informasi: baik buku maupun jurnal, jika digunakan dengan bijak, adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih luas.
Buku perpustakaan mengajarkan kesabaran dan kedalaman, sementara jurnal akademik mengajarkan ketangkasan dan kepekaan terhadap tren. Keduanya, seperti dua sisi mata pedang, saling melengkapi dalam membentuk pikiran yang kritis.
Perjalanan dari buku perpustakaan ke jurnal akademik adalah metafora dari pendewasaan intelektual. Siswa sekolah belajar merangkak dengan buku, membangun fondasi literasi informasi. Mahasiswa, dengan jurnal akademik, belajar melesat, mengejar kebaruan dan kedalaman. Namun, tanpa literasi informasi sebagai kompas, keduanya tak akan membawa jauh.
Seperti yang ditunjukkan Harisanty dkk. (2025), literasi informasi adalah kunci untuk memanfaatkan sumber belajar, baik yang berwujud kertas maupun piksel.
Maka, pertanyaannya bukan tentang memilih buku atau jurnal, tetapi bagaimana kita mengajarkan generasi muda untuk menari di antara keduanya—mengambil kebijaksanaan dari masa lalu dan keberanian dari masa kini, untuk merangkai masa depan yang lebih cerdas.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS