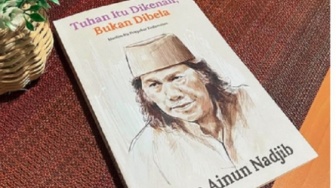Sobat yoursay, kita semua pasti sudah lelah membaca berita tentang bullying yang seolah tak ada habisnya.
Baru-baru ini, dua kasus kembali mengguncang Indonesia. MH, siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal setelah dipukul memakai bangku besi oleh teman sekelasnya, dan kasus seorang siswa SMP di Purworejo yang dianiaya oleh anak SD dan videonya disebarkan di media sosial.
Dua peristiwa berbeda, tapi akarnya sama, yaitu ekosistem kekerasan yang sudah lama kita biarkan tumbuh, berkembang, dan beranak-pinak.
Kadang kita sibuk bertanya siapa yang salah? Pelaku? Guru? Orang tua? Sekolah? Namun jarang kita bertanya apa yang salah pada lingkungan yang membentuk anak-anak ini. Karena, Sobat Yoursay, anak-anak tidak tiba-tiba menjadi kejam dalam semalam. Mereka belajar dari suatu tempat.
Dan sayangnya, tempat itu sering kali lebih dekat dari yang kita kira.
Banyak anak Indonesia dibesarkan dalam dunia yang keras, bukan karena mereka mau, tapi karena itulah yang dicontohkan orang dewasa di sekeliling mereka. Kita sering mendengar kalimat seperti, “Jangan manja!”, “Kenapa sih lambat banget?”, “Kamu bikin malu!”
Pernah dengar, sobat yoursay? Atau malah pernah mengucapkannya?
Budaya membentak seolah sudah mendarah daging. Anak dianggap miniatur orang dewasa yang harus tahan ucapan kasar. Padahal, di sinilah benih kekerasan pertama kali disiram.
Anak yang terbiasa dimarahi belajar bahwa cara menyelesaikan masalah adalah dengan meninggikan suara. Anak yang dipermalukan belajar bahwa merendahkan orang lain adalah hal biasa.
Dalam kasus MH di Tangsel, korban mengaku sudah berkali-kali dipukul sebelum kejadian fatal terjadi. Bayangkan, normalisasi kekerasan itu sudah berlangsung lama, dan tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menghentikan.
Bagaimana bisa?
Karena lingkungan kita sibuk membahas perilaku anak, tapi jarang membahas pola asuh orang dewasa.
Sekolah seharusnya menjadi ruang aman kedua setelah rumah. Tapi realitasnya, banyak sekolah justru menjadi arena kekuasaan kecil-kecilan. Anak yang kuat menindas yang lemah. Anak yang populer memutuskan siapa yang boleh eksis. Sementara guru? Banyak yang bahkan tidak punya kewenangan lagi untuk bersikap tegas.
Di sisi lain, sekolah juga sering gagal mendeteksi tanda kekerasan. MH menunjukkan gejala sakit sehari setelah pemukulan, tapi perundungan sebelumnya tidak pernah terlihat oleh sistem sekolah. Mengapa?
Karena sekolah kita lebih sibuk mengejar nilai dan akreditasi ketimbang kesehatan emosional siswa.
Guru BK sering dipersepsikan sebagai polisi pelanggaran, alih-alih pendamping psikologis. Tidak ada konselor profesional, tidak ada kurikulum empati yang serius, dan tidak ada audit ruang rawan bullying.
Sementara itu, anak-anak belajar bahwa sekolah tidak akan membantu mereka. Maka mereka menyelesaikan cara dengan apa yang paling mereka kenal, yaitu kekerasan.
Lalu kita masuk ke dunia digital, ruang tanpa batas yang seolah menjadi perpanjangan tangan dari kekerasan nyata. Di sinilah kasus Purworejo menjadi contoh paling jelas.
Di era seperti ini, bullying tidak hanya terjadi di halaman sekolah, tapi juga muncul melalui layar ponsel, dan menghantui korban kapan pun algoritma memutuskan untuk menghadirkan ulang traumanya.
Di media sosial, kekerasan bisa menjadi konten, dan konten bisa menjadi hiburan. Anak-anak yang sejak kecil menonton prank kasar, adu pukul, atau konten penghinaan tanpa filter akhirnya tidak lagi melihat batas antara bercanda dan menyakiti.
Ironisnya, negara pun tidak benar-benar hadir secara sistemik. Kita punya banyak slogan anti-bullying, tetapi minim implementasi. Tidak ada standar nasional yang mengatur bagaimana sekolah harus menangani kekerasan. Tidak ada konselor profesional yang diwajibkan. Tidak ada program rehabilitasi untuk pelaku maupun korban. Kita cenderung bergerak setelah tragedi, bukan sebelum tragedi.
Semua itu diperparah oleh budaya permisif kita. Betapa sering kita mendengar ungkapan “namanya juga anak-anak”?
Kalimat itu sebenarnya sangat berbahaya. Ia membuat kita meremehkan tanda-tanda awal kekerasan, dan membuat kita lupa bahwa banyak kasus bullying fatal bermula dari candaan yang dibiarkan tumbuh tanpa batas.
Sobat yoursay, jika kita terus membiarkan ekosistem kekerasan ini hidup, maka kasus MH dan kasus Purworejo bukanlah yang terakhir. Mereka hanya pengingat bahwa masa depan Indonesia sedang dibentuk oleh generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak ramah.
Lalu, apakah kita mau mengubahnya sebelum semuanya terlambat?