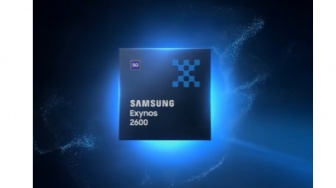Setiap kali muncul berita tentang remaja yang terlibat kekerasan, ujaran kebencian, atau perilaku yang dianggap “kebablasan”, reaksi publik hampir selalu sama: mengeluh. Media sosial ramai dengan komentar bernada kecewa, orang dewasa menggelengkan kepala, lalu kesimpulan cepat pun muncul: moral remaja sekarang sudah rusak. Tapi pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab adalah yang paling penting: salah siapa sebenarnya?
Menyalahkan remaja adalah jalan paling mudah. Mereka yang terlihat di permukaan, mereka yang aksinya viral, mereka yang dianggap “berbeda” dari generasi sebelumnya. Padahal, moral bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia dibentuk, dipelajari, dan yang paling krusial, dicontohkan. Jika moral remaja hari ini kian menipis, mustahil itu terjadi tanpa proses panjang yang melibatkan lingkungan di sekitarnya.
Kita hidup di zaman yang serba cepat, bising, dan penuh tuntutan. Remaja tumbuh di tengah arus informasi tanpa henti, di mana batas antara benar dan salah sering kabur. Media sosial memberi panggung bagi siapa pun untuk bicara, tapi jarang mengajarkan cara mendengar. Yang paling lantang sering menang, yang paling sopan justru tenggelam. Dalam ekosistem seperti ini, nilai moral mudah tergeser oleh kebutuhan akan validasi.
Namun, media sosial bukan akar masalah, hanya pengeras suara. Masalah sebenarnya ada pada cara kita orang dewasa membiarkan ruang itu menjadi sekolah tanpa kurikulum etika. Kita memberi gawai sebelum memberi pegangan nilai. Kita menuntut anak untuk bijak di dunia digital, sementara kita sendiri kerap gagal menunjukkan kedewasaan yang sama. Remaja belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang kita ceramahkan.
Di rumah, situasinya sering tidak lebih baik. Banyak orangtua sibuk bekerja, lelah mengejar stabilitas ekonomi, lalu berharap sekolah atau agama mengurus sisanya. Percakapan tentang nilai, empati, dan tanggung jawab kalah oleh jadwal yang padat dan komunikasi yang dangkal. Remaja tumbuh dengan fasilitas, tapi minim dialog. Mereka tahu cara menggunakan teknologi, tapi tidak selalu tahu cara mengelola emosi.
Sekolah pun tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Sistem pendidikan terlalu lama menempatkan prestasi akademik sebagai tujuan utama. Nilai rapor, peringkat, dan capaian formal sering lebih dihargai daripada sikap. Anak yang pintar tapi arogan masih dipuji, sementara anak yang sopan tapi biasa-biasa saja jarang disorot. Pesan yang diterima remaja sederhana: hasil lebih penting daripada proses, pintar lebih penting daripada beradab.
Lalu ada masyarakat luas, yang sering lupa bercermin. Kita marah ketika remaja berbicara kasar, tapi terbiasa menyaksikan orang dewasa saling merendahkan di ruang publik. Kita mengutuk intoleransi, tapi mudah menghakimi yang berbeda. Kita menuntut sopan santun, tapi menormalisasi kekerasan verbal sebagai hiburan. Remaja tidak hidup di ruang hampa; mereka menyerap apa yang kita anggap biasa.
Masalah moral remaja juga tidak bisa dilepaskan dari krisis teladan. Figur publik yang seharusnya menjadi contoh sering justru mempertontonkan sikap sebaliknya. Kebohongan, arogansi, dan ketidak bertanggung jawaban kerap lolos tanpa konsekuensi serius. Ketika pelanggaran moral tidak dihukum, bahkan dirayakan, remaja belajar satu hal penting: nilai itu fleksibel, tergantung posisi dan popularitas.
Di sisi lain, kita juga terlalu gemar menghakimi tanpa mendengar. Remaja yang salah cepat dicap “tidak bermoral”, jarang diajak bicara tentang apa yang mereka rasakan dan hadapi. Tekanan mental, kebingungan identitas, dan kecemasan masa depan sering diabaikan. Kita menuntut mereka dewasa, tapi enggan menyediakan ruang aman untuk bertumbuh.
Apakah ini berarti remaja bebas dari tanggung jawab? Tentu tidak. Setiap individu tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Namun, menaruh seluruh beban di pundak remaja adalah bentuk kemalasan kolektif. Lebih mudah menunjuk daripada membenahi. Lebih nyaman mengeluh daripada terlibat.
Jika kita jujur, penipisan moral remaja adalah cermin dari kegagalan bersama. Kegagalan membangun lingkungan yang konsisten antara kata dan perbuatan. Kegagalan menghadirkan teladan yang utuh. Kegagalan mendengarkan sebelum menilai. Remaja hari ini adalah produk dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat bertahun-tahun lalu.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya “kenapa remaja sekarang begini?” dan mulai bertanya “apa yang sudah kita contohkan?” Moral tidak tumbuh dari larangan semata, tapi dari kebiasaan. Dari dialog yang jujur, dari keberanian mengakui salah, dari konsistensi bersikap bahkan saat tidak ada yang menonton.
Moral remaja tidak sedang menipis tanpa sebab. Ia terkikis sedikit demi sedikit oleh dunia yang sering tidak memberi arah, hanya kecepatan. Jika kita ingin perubahan, jawabannya bukan ceramah tambahan, melainkan keterlibatan nyata. Bukan tuntutan sepihak, melainkan tanggung jawab bersama.
Karena pada akhirnya, remaja bukan masalah yang harus diselesaikan, melainkan amanah yang harus dijaga. Dan jika moral mereka hari ini rapuh, itu adalah alarm bagi kita semua bahwa ada yang perlu dibenahi, dimulai dari diri kita sendiri.