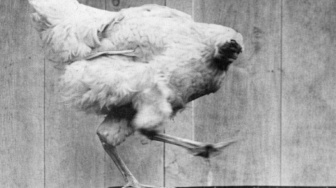Ramadan selalu datang dengan cara yang tenang, tetapi dampaknya bisa mengguncang. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memaksa siapa pun berubah. Namun bagi yang mau merenung, Ramadan seperti cahaya yang menyorot sudut-sudut diri yang sering kita abaikan.
Kita sering menganggap Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Jadwal sahur disiapkan, waktu berbuka ditunggu, tarawih dijalankan. Semua terasa familiar. Namun justru karena terlalu akrab, kita kadang lupa bahwa Ramadan bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah ruang untuk jujur pada diri sendiri.
Menahan lapar memang tidak mudah. Tenggorokan kering di siang hari, tubuh terasa lemah, pekerjaan tetap menuntut diselesaikan. Tetapi sesungguhnya, yang lebih berat bukanlah menahan makan dan minum. Yang lebih berat adalah menahan ego.
Ramadan menguji hal-hal yang tidak terlihat. Saat lelah membuat emosi naik, di situlah kesabaran diuji. Saat ada kesempatan berkata kasar namun kita memilih diam, di situlah puasa menemukan maknanya. Puasa bukan hanya tentang apa yang tidak kita konsumsi, tetapi juga tentang apa yang tidak kita lepaskan dari lisan dan hati.
Saya sering merasa Ramadan seperti cermin yang jujur. Ia memantulkan kembali siapa diri kita sebenarnya. Jika kita mudah tersinggung saat lapar, mungkin selama ini kita memang kurang sabar. Jika kita berat berbagi padahal mampu, mungkin empati kita belum tumbuh sepenuhnya. Ramadan tidak menghakimi, tetapi ia memperlihatkan.
Di sisi lain, ada kehangatan yang sulit digantikan. Suara peralatan makan saat sahur, langkah kaki menuju masjid, dan detik-detik menjelang azan magrib menghadirkan rasa yang berbeda. Segelas air putih terasa seperti nikmat yang luar biasa. Sederhana, tetapi menggetarkan.
Di tengah kesibukan dunia yang sering bising dan penuh persaingan, Ramadan memberi jeda. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tetapi juga tentang menahan. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi. Kita diingatkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari seberapa banyak yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa mampu ia mengendalikan dirinya.
Yang sering terlupakan adalah pertanyaan setelahnya: apakah kita berubah?
Ramadan bukan panggung untuk terlihat lebih religius dari orang lain. Ia adalah ruang sunyi untuk memperbaiki diri tanpa perlu diumumkan. Jika setelahnya kita lebih sabar, lebih lembut dalam berbicara, lebih ringan tangan membantu, maka Ramadan telah bekerja di dalam diri kita.
Pada akhirnya, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk berani melihat kekurangan, mengakui kelemahan, dan memulai perbaikan tanpa menunggu waktu yang sempurna.
Karena yang diuji bukan hanya seberapa kuat kita menahan lapar, tetapi seberapa tulus kita berubah.
Dan mungkin, di situlah makna Ramadan yang sesungguhnya