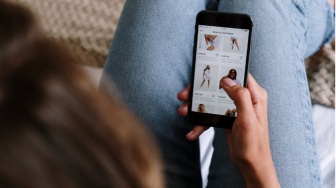Insiden penumpang tunanetra yang terjatuh ke saluran air di sekitar halte Transjakarta baru-baru ini bukan sekadar kabar viral yang segera dilupakan. Ia adalah alarm keras tentang betapa rapuhnya sistem aksesibilitas kita ketika diuji oleh kenyataan di lapangan. Di atas kertas, Jakarta telah memiliki berbagai kebijakan yang menyatakan diri sebagai kota ramah semua kalangan. Namun, di atas trotoar, di halte, dan di koridor transportasi publik, janji itu kerap runtuh oleh kelalaian kecil yang berdampak besar.
Transportasi publik adalah nadi kota modern. Ia bukan hanya alat mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak warga untuk bergerak dengan aman dan bermartabat. Ketika seorang penyandang disabilitas jatuh karena tidak didampingi secara layak, yang runtuh bukan hanya tubuhnya, melainkan juga kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi.
Aksesibilitas Bukan Fasilitas Tambahan
Selama ini, aksesibilitas sering dipahami sebagai fasilitas pelengkap. Guiding block dipasang setelah trotoar selesai dibangun. Lift dan ramp ditambahkan sebagai aksesori, bukan sebagai bagian inti dari desain. Cara berpikir ini keliru. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas bukan kemewahan, melainkan syarat dasar untuk dapat menggunakan ruang publik.
Dalam konteks transportasi publik, aksesibilitas mencakup banyak hal. Ia meliputi desain halte yang aman, jalur pejalan kaki yang tidak terputus, informasi yang dapat diakses oleh berbagai indra, serta prosedur pendampingan yang jelas. Ketika salah satu elemen ini rapuh, keseluruhan sistem menjadi tidak aman bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
Insiden di sekitar halte Transjakarta menunjukkan bahwa infrastruktur dan layanan tidak bisa dipisahkan. Seaman apa pun desain fisik sebuah halte, ia akan menjadi berbahaya jika tidak diiringi dengan layanan manusia yang memahami dan menghormati kebutuhan pengguna. Sebaliknya, sebaik apa pun niat petugas, hal itu akan sia-sia jika lingkungan fisiknya penuh jebakan.
Kota inklusif menuntut kita untuk memulai dari perspektif pengguna yang paling rentan. Jika seorang tunanetra, lansia, atau pengguna kursi roda merasa aman dan nyaman, hampir pasti warga lain juga akan merasakan hal yang sama. Prinsip ini seharusnya menjadi dasar dalam setiap perencanaan dan evaluasi transportasi publik.
Peran Kunci Pegawai di Garda Terdepan
Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Dalam layanan publik, pegawai di garda terdepan adalah wajah negara. Mereka yang menyapa, mendampingi, dan mengantar penumpang sesungguhnya sedang menjalankan mandat konstitusional untuk melayani warga negara tanpa diskriminasi.
Kasus penumpang tunanetra yang dilepas tanpa pendampingan fisik memperlihatkan betapa krusialnya komitmen personal seorang petugas. Prosedur operasi standar bisa saja tertulis rapi, tetapi tanpa kesadaran dan empati, prosedur itu mudah diabaikan. Dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas, detail kecil menentukan keselamatan. Memegang lengan, memastikan pijakan aman, atau menunggu hingga penumpang benar-benar berada di jalur yang tepat bukan sekadar formalitas, melainkan tindakan penyelamatan.
Pelatihan teknis harus dibarengi dengan pendidikan nilai. Pegawai transportasi publik perlu memahami bahwa mereka tidak sedang membantu orang yang lemah, melainkan sedang memenuhi hak warga yang setara. Perspektif ini penting agar pendampingan tidak dilakukan setengah hati atau sekadar menggugurkan kewajiban.
Selain itu, sistem pengawasan dan akuntabilitas perlu diperkuat. Kesalahan dalam layanan kepada kelompok rentan harus diperlakukan secara serius, bukan ditutupi dengan permintaan maaf semata. Evaluasi, sanksi, dan perbaikan prosedur harus berjalan seiring agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Dari Insiden Menuju Perubahan Sistemik
Setiap kota besar pasti pernah mengalami kegagalan layanan. Yang membedakan kota yang belajar dengan kota yang stagnan adalah kemampuannya menjadikan insiden sebagai titik balik. Peristiwa yang menimpa penumpang tunanetra seharusnya mendorong evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada satu unit layanan, melainkan pada keseluruhan ekosistem transportasi publik.
Pemerintah daerah, operator, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk meninjau kembali standar aksesibilitas. Audit terhadap jalur pejalan kaki, halte, dan prosedur pendampingan harus dilakukan dengan melibatkan komunitas disabilitas sebagai mitra, bukan sekadar objek. Mereka yang mengalami langsung hambatan di lapangan adalah sumber pengetahuan paling berharga untuk merancang solusi.
Lebih jauh, kita perlu membangun budaya melayani yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Transportasi publik bukan pabrik yang mengejar target jumlah penumpang, melainkan ruang sosial di mana berbagai latar belakang bertemu. Di ruang ini, kepekaan dan kepedulian harus menjadi bagian dari profesionalisme.
Pada akhirnya, kota yang benar-benar modern tidak diukur dari panjang jalur busway atau jumlah armada, tetapi dari seberapa aman dan dihormatinya warga yang paling rentan. Ketika seorang penyandang disabilitas dapat bepergian tanpa rasa takut, kita semua sebenarnya sedang menikmati buah dari sistem yang lebih adil. Dari situlah, makna kota inklusif menemukan wujudnya yang paling nyata.