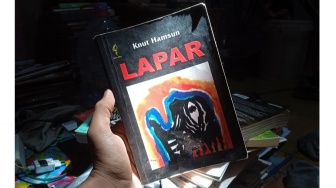Menyusuri lorong gelap ditemani seabrek buku di dalam tasnya. Ipu pergi meninggalkan gemerlap kota yang telah membawanya terlena. Ia bersama teman-temannya bersua di rumah ria yang menawarkan apa itu duniawi dan kenikmatan.
Menggenakan kemeja berwarna merah dan celana jeans dengan style robek dibagian dengkulnya, Ipu mengencangkan celananya karena sering melorot ketika dipakai. Kehidupan kota membawanya pada gemerlap penuh suka cita, terkadang melupakan kampung halaman yang sepi dan kelabu.
Hampir empat tahun Ipu tinggal di kota itu, untuk menuntut Ilmu. Seabrek pengalaman telah didapatkan. Dari mulai bertahan hidup sehari dengan uang sepuluh ribu rupiah hingga bertikai dengan preman, kala memalak Ipu yang nekat berjualan di emperan jalan pinggir kota.
Hidup Ipu memang berbeda dengan teman-temannya yang selalu meringis ceria dan tebal dompetnya. Maklum saja, Ipu hanya anak seorang buruh yang dipaksa kuliah, karena orang tuanya tak mau menderita seperti mereka. Harapannya bisa lebih baik.
Batin Ipu kadang tertusuk sedih, pasalnya hidupnya selalu diambang penderitaan. Tetapi, ia tak pernah mengurungkan niatnya melibas segala problema yang menghadang. Tak ada jalan lain selain menerjang dan melawan. Keberanian sebagai nyawanya.
Lorong gelapn dan suara jangkrik saling beriringan. Ia teringat bagaimana kondisi desa malah hari dengan diselimuti angin dingin dan rasa sepi yang hangat kala berkumpul dengan keluarga diruang tengah bertembok kayu. Ia kadang malu, bila saja orang tuanya tahu, Apa yang dilakukannya malam itu.
Ipu selalu berjalan kaki dan naik bus kota. Mobil atau motor tak punya. Hanya dengkul dan setumpuk koin agar bisa mengelilingi kota dan bercengkrama dengan teman-temannya di kampus. Beberapa temannya kadang menawarkan tumpangan untuk Ipu, agar tak capek sampai di gubuknya.
Sampainya diujung lorong, ia melihat tunawisma sedang tertidur di rumah tua yang tak berpenghuni peninggalan komprador jaman penjajahan. Angin malam membuat dingin leher Ipu, dibalutlah lehernya dengan kain hangat rajutan ibunya, yang selalu ia bawa ketika bepergian.
Masih berjalan didepan bibir lorong. Nampaknya tempat itu sebagai tempat favorit, bagi tunawisma untuk meredakan punggungnya dan beristirahat di tengah kota penuh sesak itu. Hampir belasa orang dari anak-anak hingga manula berkumpul di tempat itu.
Ipu teringat di tasnya masih ada sisa lima buah roti gandum. Hati nuraninya terketuk untuk menemui dan memberikannya kepada tunawisma. Langkah kaki Ipu ragu-ragu dan takut bila saja, makanannya akan ditolak atau barang bawaannya akan dirampok.
Menarik nafas dalam ia berjalan menuju gerombolan tunawisma. "Permisi, bolehkah saya duduk disini?" Tunawisma dan sorotan mata lain nampak kaget atas apa yang Ipu inginkan. Penampilan bersih dan berbau wangi terbesit di dalam pikir para tunawisma, mengapa ia berani dan enggan duduk bersama mereka.
"Iya, boleh, silahkan." Tikar merah bermotif merak dan berlubang di bagian pinggirnya di gelar, sebagai rasa hormat untuk Ipu. Ipu merasa malu, karena diperlakukan seperti raja. Mungkin saja, peribahasa tamu adalah raja itu, sudah dahulu ada dalam pikiran orang-orang.
Ipu berfikir lamat-lamat untuk membuka pembicaraan agar lebih hangat kondisi malam itu. Tunawisma, lebih dahulu menanyakan Ipu, dengan kata "Dari mana?" Ipu menjawab dengan jujur, muka murung yang ditutupi senyum dengan balutan gigi hitamnya, nampak canggung apa yang dilakukan Ipu. Menghamburkan uang, bagi mereka adalah kesalahan.
Kondisi kota, yang baru saja dilanda krisis hebat, membuat beberapa toko tutup. Dan beberapa lagi bunuh diri, karena tak kuat mengahadapi gejolak dunia yang membuat derita. "Sudah berapa lama abang tinggal disini?" tanya Ipu grogi sambil memainkan jempolnya. Menghela napas, tunawisma menajab dengan begitu harap.
"Kami tinggal disini kurang lebih dua tahun mas. Sebelumnya saya tinggal dirumah kontrakan dan bekerja di bagian tukang kebun. Karena perusahaan saya hancur karena krisis. Bos memecat saya dan akhirnya rumah kontrkan tak bisa dibayar. Saya pun terpaksa tidur di emperan jalan". Muka berbentuk kota dan sedikit luka dibagian dagu, berbicara dengan lesu.
Pembicaraan semakin hangat. Ipu pun memberikan roti gandum kepada tunawisma. Rasa ingin tahu karena lapar, bocah kurang lebih berumur sepulun tahun mengampiri Ipu. Ipu pun terketuk untuk memberika roti kepanya nya. Dengan penuh lahap ia menelan seluruh roti, karena lapar yang ditahan.
Ipu terketuk hatinya, karena ia sadar pederitaan yang selama ini rasakan. Tak sebanding dengan para tunawisma yang lebih parah penderitaannya. Ia melihat sekeliling lokasi yang kumuh dan penuh nyamuk menghinggapi hidup dan dahi Ipu.
"Ketika aku melihat orang sepertimu, maka aku ingin kembali meniti sebuah jalan terjal dan bergulat sebaik mungkin". tunawisma menyampaikan kepada Ipu dengan semangat yang begiut kuat.
Ipu terdiam dan hanya melihat tunawisma dengan seksama. Ia tak bisa lama-lama bergurau dan berbincang dengan teman-teman barunya. Ia teringat ada sebuah tugas yang harus segera diselesaikan. Izin untuk kembali dan bersalama. Tunawisma dengan harap anak muda itu kembali bersua dengannya.
Ipu kembali berjalan dan menyisir malam di kota yang begitu dingin, tak seperti hari-hari sebelumnya. Di pojok gedung, ia melihat geliat dan gerak-gerik begitu aneh ditengah gelap malam, dilihatnya lamat-lamat, ia menyesal karena menggunakan matanya untuk hal amoral seperti itu.
Seks bebas dan penyakit amoral menjangkit kaula muda. Bebas karena konstruk sosial yang menyebabkan ayah dan ibu mereka jarang memberikan petuah etika dan moral. Mereka lebih sibuk untuk bekerja dan tunduk kepada bos-bos mereka. Anak dan masa depan kadang terusik oleh hal ini.
Memang, kritik akan modernisme dan kuatnya kapitalisme yang telah mengakar, ada sisi baiknya di kritik. Tergerusnya budaya lama dengan budaya baru menimbulkan alienasi yang terkadang membuat kikuk orang yang tadinya tata krama berubah menjadi individualis kolot. Tetapi, terkadang bingung juga. Modernisme diidentikan dengan kemajuan, sedangkan budaya lama dilabeli sebagai ketertinggalan.
Ipu dibuat bingung dengan pikirannya sendiri. Ia menganggap hal itu wajar, karena masih bersyukur menggunakan akalnya atas pemberian tuhan. Mungkin saja, tuhan marah, bila saja orang-orang tak mau berfikir.